- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
NKRI dan Makar Konstitusional
TS
tanmalako091539
NKRI dan Makar Konstitusional
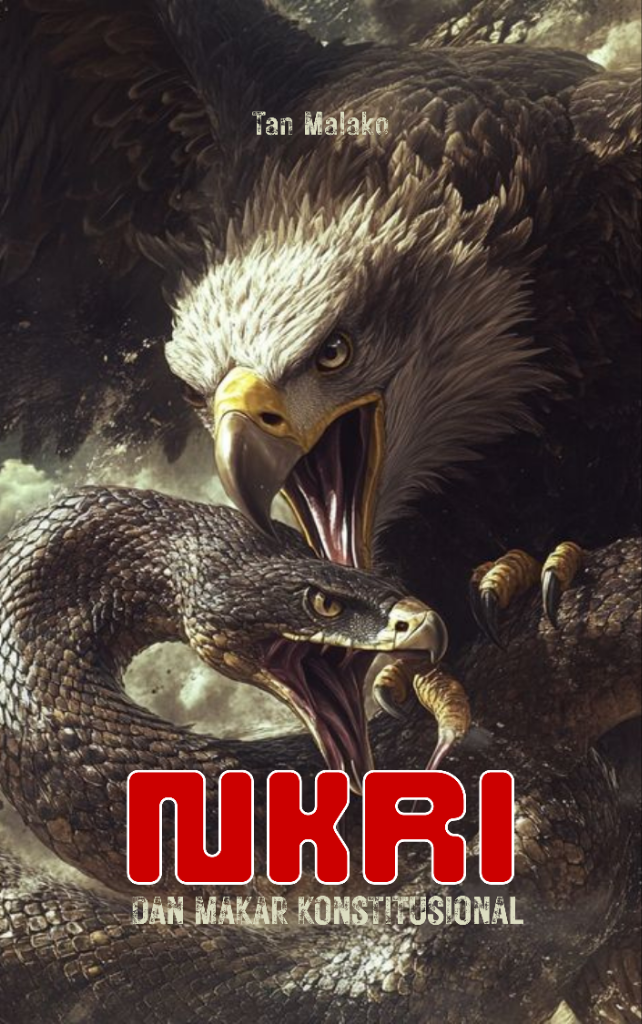
Dalam sejarah hukum dan ketatanegaraan Indonesia, jarang terdapat istilah yang begitu sering diucapkan, namun begitu jarang dipahami secara yuridis, seperti frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia bergema dalam pidato kenegaraan, diteriakkan di jalan-jalan, disematkan dalam dokumen politik, bahkan dijadikan dasar moral dalam berbagai kebijakan publik. Namun, ketika ditelaah secara ketat dalam teks konstitusi, istilah tersebut ternyata tidak pernah disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang diatur, dibentuk, dan diberi legitimasi oleh UUD 1945 bernama Republik Indonesia, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan ini tampak sepele di permukaan, tetapi mengandung persoalan serius dalam ranah hukum tata negara dan politik kedaulatan.
Penyisipan istilah NKRI ke dalam undang-undang, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, bukan sekadar kekeliruan redaksional, melainkan persoalan ontologis mengenai siapa sebenarnya subjek hukum yang sah mewakili negara dalam sistem moneter. Ketika undang-undang menetapkan bahwa Rupiah adalah “mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia,” muncul pertanyaan mendasar: negara yang mana yang dimaksud? Apakah entitas yang disebut “NKRI” tersebut memiliki dasar konstitusional yang sah? Dalam teks UUD 1945, tidak ada satu pun pasal yang menyebut NKRI sebagai badan hukum publik yang dapat bertindak atas nama negara. Dengan demikian, pengesahan uang atas nama “NKRI” menimbulkan ketidaksesuaian antara hukum dasar dan hukum turunan.
Secara hierarkis, norma hukum di Indonesia tunduk pada asas lex superior derogat legi inferiori — bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, UUD 1945 sebagai hukum tertinggi harus menjadi rujukan utama bagi setiap bentuk peraturan perundang-undangan. Maka, ketika sebuah undang-undang mencantumkan istilah yang tidak bersumber dari atau tidak sesuai dengan konstitusi, tindakan tersebut bukan hanya cacat formil, tetapi juga mengandung cacat materiil yang dapat membelokkan arah legitimasi negara.
Penggunaan istilah “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dalam undang-undang dapat ditafsir sebagai bentuk makar konstitusional (constitutional treason). Dalam pengertian klasik, makar adalah upaya menggulingkan pemerintahan yang sah melalui kekerasan. Namun dalam konteks hukum tata negara modern, makar tidak selalu berupa tindakan fisik. Ia dapat mengambil bentuk yang lebih halus: pergeseran kekuasaan melalui rekayasa hukum. Makar konstitusional terjadi ketika substansi atau kehendak UUD diubah secara diam-diam melalui produk hukum yang tampak sah secara prosedural, tetapi sesungguhnya mengalihkan atau menggantikan legitimasi konstitusional kepada entitas lain yang tidak sah.
Dalam kasus ini, NKRI berperan sebagai simbol politik yang diangkat menjadi entitas hukum tanpa legitimasi konstitusional. Dengan demikian, tindakan legislator yang menempatkan NKRI sebagai penerbit Rupiah dapat dipandang sebagai tindakan yang mengubah struktur kedaulatan tanpa melalui mekanisme amandemen konstitusi. Hal ini sejalan dengan pandangan teoretis Carl Schmitt, yang menyatakan bahwa inti dari konstitusi adalah keputusan tentang “siapa yang berdaulat.” Ketika subjek hukum baru diperkenalkan tanpa dasar konstitusional, maka sesungguhnya telah terjadi pengambilalihan otoritas kedaulatan melalui jalur hukum.
Tindakan semacam ini juga berpotensi memperkuat fenomena state capture corruption—yakni kondisi ketika proses politik dan hukum dikendalikan oleh kelompok atau kepentingan tertentu yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik dominan. Dalam konteks kebijakan moneter, penguasaan terhadap otoritas penerbitan uang bukan perkara administratif, melainkan menyangkut kendali terhadap instrumen kedaulatan ekonomi. Jika entitas simbolik seperti NKRI digunakan sebagai justifikasi legal untuk menggantikan subjek hukum yang sah, maka celah tersebut dapat dimanfaatkan untuk meloloskan kebijakan yang tidak dapat diuji secara konstitusional.
Di titik inilah letak bahayanya: konstitusi yang seharusnya menjadi pagar hukum justru dijadikan selubung bagi kekuasaan yang tidak akuntabel. Dalam tradisi demokrasi konstitusional, kedaulatan rakyat hanya dapat dijalankan melalui mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Ketika norma undang-undang menciptakan entitas baru di luar struktur konstitusional, maka terjadi pelanggaran terhadap asas kedaulatan rakyat itu sendiri. Makar konstitusional demikian tidak membutuhkan senjata, cukup dengan perubahan redaksi dalam pasal-pasal strategis, maka seluruh arsitektur kekuasaan dapat digeser tanpa disadari publik.
Secara hukum, langkah korektif terhadap potensi penyimpangan ini dapat dilakukan melalui mekanisme uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memiliki kewenangan untuk menilai apakah norma dalam suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Permohonan uji materiil terhadap pasal-pasal yang menggunakan istilah NKRI dapat diajukan dengan argumentasi bahwa istilah tersebut tidak memiliki dasar konstitusional dan menimbulkan ambiguitas terhadap kewenangan negara. Jika MK menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan UUD, maka pasal itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Namun, persoalan ini tidak hanya berhenti pada ranah hukum. Ia memiliki implikasi politik dan epistemologis yang luas. Pencantuman istilah NKRI dalam undang-undang, termasuk pada uang kertas yang beredar, menciptakan kesan bahwa kedaulatan negara dipegang oleh entitas simbolik yang abstrak, bukan oleh institusi konstitusional yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, rakyat sebagai pemilik kedaulatan kehilangan titik rujukan yang sah kepada siapa mereka menuntut hak atau menagih tanggung jawab negara.
Selain itu, dari perspektif simbolik, uang adalah manifestasi tertinggi dari kedaulatan hukum dan ekonomi. Ia adalah representasi fisik dari janji negara terhadap nilai dan stabilitas. Ketika uang diterbitkan atas nama entitas yang tidak diatur dalam konstitusi, maka nilai simboliknya ikut terdegradasi. Ketidakjelasan tentang siapa penerbit yang sah menciptakan ruang abu-abu dalam sistem moneter. Lebih dari itu, kepercayaan publik terhadap instrumen keuangan dapat terganggu karena legitimasi hukum yang mendasarinya kabur.
Dalam jangka panjang, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan preseden berbahaya: jika istilah simbolik dapat diangkat menjadi dasar hukum tanpa landasan konstitusi, maka bukan tidak mungkin entitas-entitas lain yang bersifat ideologis, kultural, atau bahkan sektarian, dapat mengklaim legitimasi serupa di masa depan. Akibatnya, sistem hukum kehilangan kejelasan hierarkinya, dan konstitusi yang seharusnya menjadi sumber tertinggi hukum negara berubah menjadi dokumen yang dapat ditafsir sekehendak politik.
Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah dan parlemen tidak hanya berhenti pada menjalankan fungsi legislasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap istilah dan konsep dalam undang-undang tunduk pada teks dan semangat konstitusi. Revisi terhadap undang-undang yang mengandung inkonsistensi semacam itu menjadi langkah mendesak untuk mengembalikan supremasi UUD 1945.
Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi perlu memegang peran aktif sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution). Dalam konteks ancaman makar konstitusional, MK tidak boleh sekadar menjadi lembaga pasif yang menunggu permohonan uji materiil, melainkan harus berani mengingatkan pembentuk undang-undang tentang batas-batas konstitusional yang tidak boleh dilanggar.
Kesadaran konstitusional masyarakat juga perlu diperkuat. Selama istilah seperti NKRI terus digunakan secara sembarangan tanpa pemahaman yuridis yang tepat, publik akan terus menganggap bahwa semua hal yang mengandung label NKRI otomatis sah, nasionalis, dan konstitusional. Padahal, dalam negara hukum, legitimasi tidak berasal dari semboyan, melainkan dari teks hukum tertinggi yang disepakati secara nasional.
Dengan demikian, penyisipan istilah NKRI dalam undang-undang, termasuk dalam UU Mata Uang, harus dibaca bukan sebagai kebetulan administratif, melainkan sebagai peringatan tentang bagaimana konstitusi dapat digeser melalui jalur hukum yang tampak sah. Jika dibiarkan, hal ini menjadi bentuk makar konstitusional: pengambilalihan kedaulatan tanpa kekerasan, dilakukan melalui kata-kata yang menipu, bukan senjata.
Pada akhirnya, pertarungan antara hukum dan kekuasaan selalu terjadi dalam bahasa. Ketika hukum ditekuk untuk melayani kepentingan simbolik, maka konstitusi kehilangan maknanya sebagai pagar rasional negara. Karena itu, tugas sejarah generasi ini bukan hanya menjaga batas wilayah, melainkan menjaga batas makna—agar negara tetap berpijak pada hukum, bukan pada semboyan. Dalam kerangka itulah, mempertanyakan istilah NKRI bukan bentuk pengkhianatan, melainkan justru pembelaan paling tulus terhadap Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
Diubah oleh tanmalako091539 Kemarin 13:03
0
60
3
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan