- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Re-Kolonialisasi: Konstruksi Nalar Kolektif dan Hegemoni Simbolik
TS
tanmalako091539
Re-Kolonialisasi: Konstruksi Nalar Kolektif dan Hegemoni Simbolik
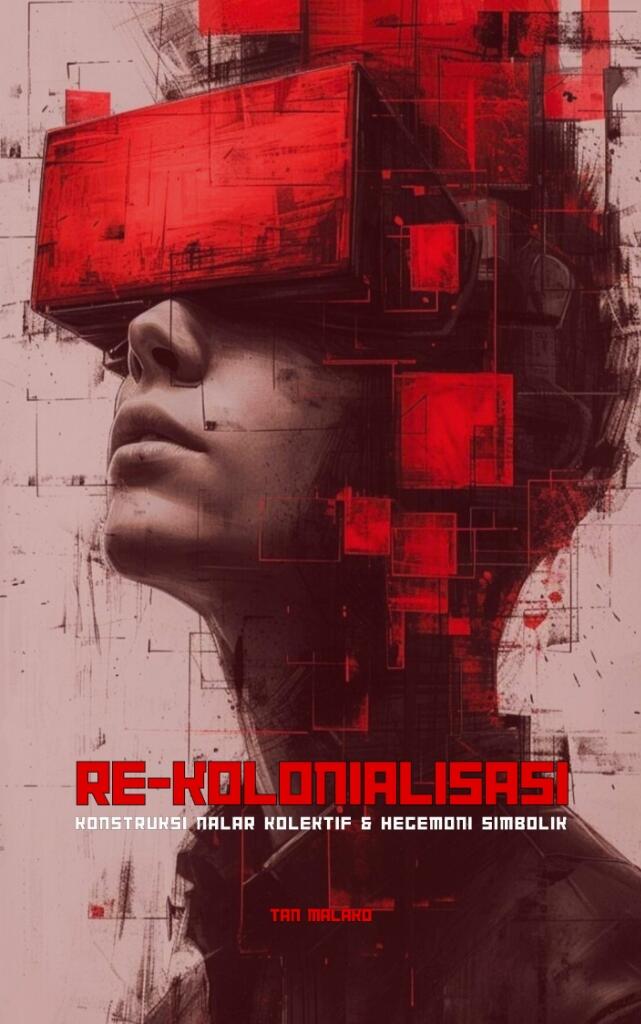
Sejarah tidak pernah mati; ia hanya berganti kulit. Kolonialisme yang dulu hadir dengan meriam, kapal layar, dan bendera kini datang tanpa bunyi. Ia menyusup, merembes, dan berdiam dalam ruang terdalam kesadaran kolektif kita. Di layar kaca, wajah-wajah blasteran menatap kita dengan senyum yang dipuja; di lapangan hijau, kaki-kaki keturunan Belanda berlari dengan kecepatan yang dielu-elukan; di akta kelahiran, nama-nama Eropa menggantikan bunyi lokal yang dulu bergaung sebagai penanda identitas. Semua ini tampak biasa, bahkan membanggakan. Namun, di balik permukaan yang tampak netral, nalar kolektif kita perlahan dibentuk ulang — bukan oleh kekerasan, melainkan oleh rayuan simbolik yang menata ulang cara kita melihat dunia, diri, dan masa depan.
Kolonialisme klasik, sebagaimana dijelaskan Edward Said dalam Culture and Imperialism(1993), tidak pernah benar-benar berakhir. Ia bertransformasi menjadi sistem representasi, menyusup ke bahasa, budaya, bahkan pengetahuan. Sejarah menjadi senjata paling efektif: bukan lagi untuk menaklukkan wilayah, tetapi untuk menundukkan kesadaran. Michel de Certeau, dalam The Writing of History (1975), menegaskan bahwa historiografi selalu merupakan strategi: ia menentukan siapa yang layak diingat dan siapa yang harus dilupakan. Dengan cara ini, kolonialisme menata ulang memori kolektif, menghapus luka, dan menggantinya dengan kisah-kisah kemajuan dan modernitas yang meninabobokan.
Nalar kolektif — atau collective reasoning — bukan sekadar kesadaran bersama, melainkan sebuah mesin tak kasat mata yang memproduksi logika sosial. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai doxa: sistem keyakinan yang diterima tanpa pertanyaan, seolah-olah alami. Ketika wajah blasteran dianggap lebih cantik, ketika pemain keturunan Belanda dirayakan sebagai pahlawan nasional di sepakbola, atau ketika nama Eropa dianggap lebih bergengsi, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil kerja panjang kolonialisme simbolik yang menormalisasi superioritas Barat.
Homi K. Bhabha, dalam The Location of Culture (1994), menawarkan konsep hybridity untuk memahami ambivalensi ini. Kolonialisme tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan ruang ketiga — third space — di mana penaklukan berbaur dengan penerimaan. Dalam ruang ini, tubuh blasteran tidak hanya dilihat sebagai produk kolonial, tetapi juga sebagai janji masa depan. Roland Barthes, lewat Mythologies (1957), menjelaskan bahwa mitos bekerja dengan cara menaturalisasi ideologi, mengubah konstruksi sejarah menjadi sesuatu yang tampak alamiah.
Fenomena naturalisasi pemain sepakbola keturunan Belanda menjadi contoh paling nyata. Proses naturalisasi ini dikemas dengan narasi patriotisme: demi kejayaan sepakbola nasional, darah Belanda dianggap sebagai anugerah. Media menggandakan citra ini, menampilkan tubuh-tubuh tinggi dan atletis sebagai bukti keunggulan “genetik.” Padahal, seperti diungkap Bourdieu dalam Distinction (1979), nilai yang dilekatkan pada tubuh tersebut hanyalah akumulasi symbolic capital — modal simbolik yang dibentuk oleh sejarah panjang relasi kuasa.
Hayden White, dalam Metahistory (1973), mengingatkan bahwa sejarah selalu dibentuk oleh narasi. Narasi naturalisasi menghapus jejak kolonial yang melahirkan genealoginya, dan menggantinya dengan cerita heroik tentang pengabdian nasional. Tubuh blasteran itu tidak lagi dibaca sebagai sisa kolonialisme, tetapi sebagai simbol kemajuan bangsa.
Proses internalisasi ini adalah bentuk hegemoni yang dijelaskan Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks (1929–1935). Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui paksaan, tetapi melalui konsensus: publik menerima dominasi karena ia tampak normal, bahkan diinginkan. Dalam konteks ini, rekolonialisasi tidak membutuhkan perang. Ia cukup hadir melalui simbol, bahasa, dan citra.
Di dunia selebriti, logika yang sama berulang. Nama-nama bernuansa Eropa — seperti Jennifer, Jensen, White, atau van Houten — mendominasi panggung hiburan. Barthes akan melihat fenomena ini sebagai mitos modern: sistem tanda yang mengaitkan nama dengan status, glamor, dan kemajuan. Anak-anak diberi nama Barat bukan semata karena keindahan bunyi, melainkan karena internalisasi simbolik bahwa Eropa adalah standar peradaban.
Nalar kolektif yang sama merasuk ke dunia olahraga. Pencarian pemain keturunan Belanda dilihat sebagai strategi nasional, bukan gejala inferioritas. Tubuh-tubuh blasteran dianggap lebih unggul: lebih tinggi, lebih cepat, lebih tangguh. Slavoj Žižek, dalam The Sublime Object of Ideology (1989), menyebut struktur ini sebagai fantasy frame — kerangka fantasi kolektif yang mengatur hasrat sosial. Kita tidak hanya menginginkan kemenangan, tetapi juga fantasi tentang kedekatan dengan Eropa.
Linda Tuhiwai Smith, dalam Decolonizing Methodologies (1999), menunjukkan bahwa kolonialisme modern bekerja dengan menyingkirkan epistemologi lokal dan menggantinya dengan logika Barat yang dianggap lebih sahih. Dalam konteks ini, tubuh blasteran, nama Barat, dan naturalisasi pemain sepakbola bukan sekadar fenomena sosial, melainkan bagian dari proyek epistemik yang mengatur cara kita berpikir.
Keberhasilan rekolonialisasi terletak pada kemampuannya menciptakan rasa “kenormalan.” Melalui paparan berulang, simbol-simbol kolonial menjadi akrab, bahkan diidamkan. Robert Zajonc (1968) menyebut mekanisme ini sebagai mere exposure effect: sesuatu menjadi lebih disukai hanya karena sering dilihat. Wajah blasteran di televisi, nama Eropa di media sosial, hingga liputan heroik pemain naturalisasi, semua mengukuhkan logika kolonial dalam kesadaran publik.
Achille Mbembe, dalam On the Postcolony (2001), menyebut bentuk kekuasaan ini sebagai kekuasaan cair: ia tidak hadir sebagai dominasi frontal, tetapi sebagai kehadiran yang intim dan natural. Rekolonialisasi bekerja seperti bayangan: tak terlihat, tetapi selalu ada, mengikuti gerak tubuh dan pikiran kita.
Masalah utama terletak pada ketidaksadaran kolektif. Ketika publik merayakan keberhasilan pemain naturalisasi atau memuja selebriti berwajah Eropa tanpa mengkritisi struktur simbolik di baliknya, nalar kolektif telah sepenuhnya dikooptasi. Proses ini bukan sekadar imitasi, melainkan penyerahan diri yang berlangsung tanpa resistensi.
Pembentukan nalar kolektif ini tidak lepas dari peran institusi formal dan informal. Kurikulum pendidikan masih menempatkan Barat sebagai pusat pengetahuan. Media massa terus memproduksi citra yang mengulang superioritas Eropa. Negara, melalui kebijakan naturalisasi dan promosi budaya populer, secara tidak langsung mengafirmasi simbol kolonial. Michel Foucault dalam The Order of Things (1966) menguraikan bagaimana struktur pengetahuan menentukan cara berpikir masyarakat, mengunci imajinasi kolektif dalam kerangka yang telah ditentukan.
Untuk membongkar mekanisme ini, dekonstruksi menjadi langkah epistemik yang tak terhindarkan. Jacques Derrida, dalam Of Grammatology (1967), mengajarkan bahwa setiap sistem tanda memiliki celah — titik rapuh yang memungkinkan pembalikan. Melawan nalar kolektif kolonial berarti mengungkap mekanisme yang menaturalisasi dominasi, sekaligus membangun ruang untuk menulis ulang narasi.
Rekolonialisasi, dengan demikian, bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses panjang yang berlangsung senyap. Ia hidup dalam bahasa, estetika, olahraga, bahkan mimpi kolektif tentang kemajuan. Tanpa kesadaran kritis, kita hanya akan menjadi figuran dalam drama sejarah yang skenarionya sudah lama ditulis — drama di mana kita, dengan sukarela, mengangkat simbol-simbol kolonial sebagai bendera masa depan.
Kolonialisme klasik, sebagaimana dijelaskan Edward Said dalam Culture and Imperialism(1993), tidak pernah benar-benar berakhir. Ia bertransformasi menjadi sistem representasi, menyusup ke bahasa, budaya, bahkan pengetahuan. Sejarah menjadi senjata paling efektif: bukan lagi untuk menaklukkan wilayah, tetapi untuk menundukkan kesadaran. Michel de Certeau, dalam The Writing of History (1975), menegaskan bahwa historiografi selalu merupakan strategi: ia menentukan siapa yang layak diingat dan siapa yang harus dilupakan. Dengan cara ini, kolonialisme menata ulang memori kolektif, menghapus luka, dan menggantinya dengan kisah-kisah kemajuan dan modernitas yang meninabobokan.
Nalar kolektif — atau collective reasoning — bukan sekadar kesadaran bersama, melainkan sebuah mesin tak kasat mata yang memproduksi logika sosial. Pierre Bourdieu menyebutnya sebagai doxa: sistem keyakinan yang diterima tanpa pertanyaan, seolah-olah alami. Ketika wajah blasteran dianggap lebih cantik, ketika pemain keturunan Belanda dirayakan sebagai pahlawan nasional di sepakbola, atau ketika nama Eropa dianggap lebih bergengsi, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil kerja panjang kolonialisme simbolik yang menormalisasi superioritas Barat.
Homi K. Bhabha, dalam The Location of Culture (1994), menawarkan konsep hybridity untuk memahami ambivalensi ini. Kolonialisme tidak hanya menindas, tetapi juga menciptakan ruang ketiga — third space — di mana penaklukan berbaur dengan penerimaan. Dalam ruang ini, tubuh blasteran tidak hanya dilihat sebagai produk kolonial, tetapi juga sebagai janji masa depan. Roland Barthes, lewat Mythologies (1957), menjelaskan bahwa mitos bekerja dengan cara menaturalisasi ideologi, mengubah konstruksi sejarah menjadi sesuatu yang tampak alamiah.
Fenomena naturalisasi pemain sepakbola keturunan Belanda menjadi contoh paling nyata. Proses naturalisasi ini dikemas dengan narasi patriotisme: demi kejayaan sepakbola nasional, darah Belanda dianggap sebagai anugerah. Media menggandakan citra ini, menampilkan tubuh-tubuh tinggi dan atletis sebagai bukti keunggulan “genetik.” Padahal, seperti diungkap Bourdieu dalam Distinction (1979), nilai yang dilekatkan pada tubuh tersebut hanyalah akumulasi symbolic capital — modal simbolik yang dibentuk oleh sejarah panjang relasi kuasa.
Hayden White, dalam Metahistory (1973), mengingatkan bahwa sejarah selalu dibentuk oleh narasi. Narasi naturalisasi menghapus jejak kolonial yang melahirkan genealoginya, dan menggantinya dengan cerita heroik tentang pengabdian nasional. Tubuh blasteran itu tidak lagi dibaca sebagai sisa kolonialisme, tetapi sebagai simbol kemajuan bangsa.
Proses internalisasi ini adalah bentuk hegemoni yang dijelaskan Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks (1929–1935). Kekuasaan tidak lagi bekerja melalui paksaan, tetapi melalui konsensus: publik menerima dominasi karena ia tampak normal, bahkan diinginkan. Dalam konteks ini, rekolonialisasi tidak membutuhkan perang. Ia cukup hadir melalui simbol, bahasa, dan citra.
Di dunia selebriti, logika yang sama berulang. Nama-nama bernuansa Eropa — seperti Jennifer, Jensen, White, atau van Houten — mendominasi panggung hiburan. Barthes akan melihat fenomena ini sebagai mitos modern: sistem tanda yang mengaitkan nama dengan status, glamor, dan kemajuan. Anak-anak diberi nama Barat bukan semata karena keindahan bunyi, melainkan karena internalisasi simbolik bahwa Eropa adalah standar peradaban.
Nalar kolektif yang sama merasuk ke dunia olahraga. Pencarian pemain keturunan Belanda dilihat sebagai strategi nasional, bukan gejala inferioritas. Tubuh-tubuh blasteran dianggap lebih unggul: lebih tinggi, lebih cepat, lebih tangguh. Slavoj Žižek, dalam The Sublime Object of Ideology (1989), menyebut struktur ini sebagai fantasy frame — kerangka fantasi kolektif yang mengatur hasrat sosial. Kita tidak hanya menginginkan kemenangan, tetapi juga fantasi tentang kedekatan dengan Eropa.
Linda Tuhiwai Smith, dalam Decolonizing Methodologies (1999), menunjukkan bahwa kolonialisme modern bekerja dengan menyingkirkan epistemologi lokal dan menggantinya dengan logika Barat yang dianggap lebih sahih. Dalam konteks ini, tubuh blasteran, nama Barat, dan naturalisasi pemain sepakbola bukan sekadar fenomena sosial, melainkan bagian dari proyek epistemik yang mengatur cara kita berpikir.
Keberhasilan rekolonialisasi terletak pada kemampuannya menciptakan rasa “kenormalan.” Melalui paparan berulang, simbol-simbol kolonial menjadi akrab, bahkan diidamkan. Robert Zajonc (1968) menyebut mekanisme ini sebagai mere exposure effect: sesuatu menjadi lebih disukai hanya karena sering dilihat. Wajah blasteran di televisi, nama Eropa di media sosial, hingga liputan heroik pemain naturalisasi, semua mengukuhkan logika kolonial dalam kesadaran publik.
Achille Mbembe, dalam On the Postcolony (2001), menyebut bentuk kekuasaan ini sebagai kekuasaan cair: ia tidak hadir sebagai dominasi frontal, tetapi sebagai kehadiran yang intim dan natural. Rekolonialisasi bekerja seperti bayangan: tak terlihat, tetapi selalu ada, mengikuti gerak tubuh dan pikiran kita.
Masalah utama terletak pada ketidaksadaran kolektif. Ketika publik merayakan keberhasilan pemain naturalisasi atau memuja selebriti berwajah Eropa tanpa mengkritisi struktur simbolik di baliknya, nalar kolektif telah sepenuhnya dikooptasi. Proses ini bukan sekadar imitasi, melainkan penyerahan diri yang berlangsung tanpa resistensi.
Pembentukan nalar kolektif ini tidak lepas dari peran institusi formal dan informal. Kurikulum pendidikan masih menempatkan Barat sebagai pusat pengetahuan. Media massa terus memproduksi citra yang mengulang superioritas Eropa. Negara, melalui kebijakan naturalisasi dan promosi budaya populer, secara tidak langsung mengafirmasi simbol kolonial. Michel Foucault dalam The Order of Things (1966) menguraikan bagaimana struktur pengetahuan menentukan cara berpikir masyarakat, mengunci imajinasi kolektif dalam kerangka yang telah ditentukan.
Untuk membongkar mekanisme ini, dekonstruksi menjadi langkah epistemik yang tak terhindarkan. Jacques Derrida, dalam Of Grammatology (1967), mengajarkan bahwa setiap sistem tanda memiliki celah — titik rapuh yang memungkinkan pembalikan. Melawan nalar kolektif kolonial berarti mengungkap mekanisme yang menaturalisasi dominasi, sekaligus membangun ruang untuk menulis ulang narasi.
Rekolonialisasi, dengan demikian, bukanlah peristiwa tunggal, melainkan proses panjang yang berlangsung senyap. Ia hidup dalam bahasa, estetika, olahraga, bahkan mimpi kolektif tentang kemajuan. Tanpa kesadaran kritis, kita hanya akan menjadi figuran dalam drama sejarah yang skenarionya sudah lama ditulis — drama di mana kita, dengan sukarela, mengangkat simbol-simbol kolonial sebagai bendera masa depan.
0
13
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan