- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Menulis Indonesia tanpa Majapahit: Rekomendasi Penulisan Ulang Sejarah Nasional
TS
tanmalako091539
Menulis Indonesia tanpa Majapahit: Rekomendasi Penulisan Ulang Sejarah Nasional
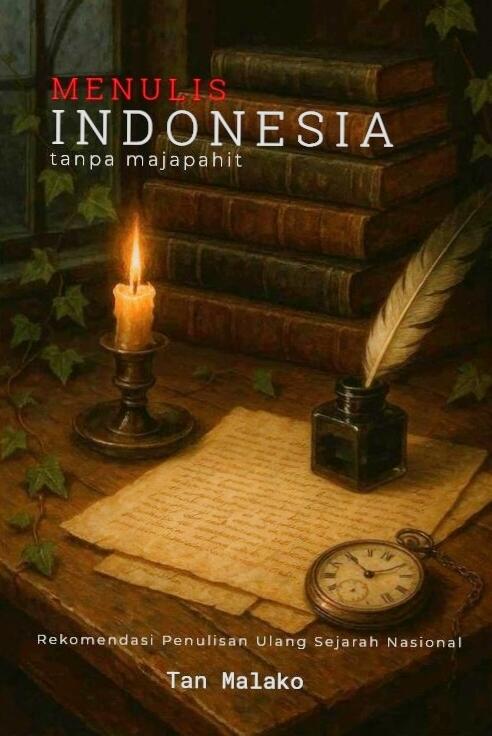
Di tengah kerak bumi historiografi Indonesia, nama Majapahit bersemayam seperti fosil yang dimitoskan sebagai emas. Ia adalah tulang belakang dari sebuah tubuh ideologis yang disebut "Indonesia," bahkan sebelum kata itu ditemukan. Sebuah kerajaan yang katanya menyatukan Nusantara, tapi ironisnya tidak pernah menyatukan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Di atas tulang-tulang rapuh legenda Gajah Mada, para birokrat kolonial membangun mimpi tentang sebuah negeri yang besar, teratur, dan dapat dipetakan dalam garis-garis lurus bernama batas wilayah. Majapahit menjadi atlas yang tidak pernah usai dipelajari, meskipun ia lebih banyak hidup dalam dongeng daripada dokumen.
Kita tentu ingat, atau paling tidak, kita diharuskan untuk mengingat, bahwa ada sumpah suci yang konon diucapkan oleh seorang mahapatih yang lebih mirip Adolf Hitler dari abad 14 ketimbang seorang pejabat agraria. Sumpah itu berbunyi "amukti palapa," yang oleh para juru tafsir nasionalisme ditafsirkan sebagai komitmen suci untuk menaklukkan wilayah yang kini disebut Indonesia. Sebuah interpretasi yang, dalam konteks genealogi kekuasaan, sangatlah menguntungkan bagi proyek negara. Namun Michel Foucault mungkin akan tersenyum getir: kebenaran tidak pernah lahir dari fakta, melainkan dari peredaran diskursif yang dikendalikan oleh siapa yang berhak bicara. Dan para arkeolog kolonial, sejarawan negara, serta pejabat kebudayaan adalah para ventriloquist yang menjadikan Majapahit sebagai boneka bicara mereka.
Majapahit, seperti semua legenda imperium, bekerja bukan karena kebenarannya, melainkan karena repetisi. Ia diulang dalam buku sejarah, diukir di relief candi yang direstorasi secara nasionalistik, dan diperdagangkan dalam upacara-upacara kebudayaan yang dibiayai APBN. Majapahit adalah Disneyland dari masa lalu kita---tidak penting apakah ia benar-benar terjadi, yang penting ia terlihat meyakinkan.
Menulis sejarah Indonesia tanpa Majapahit tentu dianggap sebagai tindakan revolusioner, bahkan mungkin subversif. Ini seperti membayangkan gereja tanpa salib atau konser rock tanpa gitar. Namun justru di sinilah persoalannya: mengapa satu kerajaan yang eksistensinya terbatas dalam ruang-waktu tertentu harus dijadikan poros tunggal dari sebuah narasi nasional yang konon majemuk? Ini adalah pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh mereka yang masih percaya bahwa sejarah adalah warisan, bukan konstruksi. Seperti yang dikatakan oleh Hayden White, sejarah adalah narasi yang diisi oleh pilihan-pilihan retoris, bukan fakta objektif. Maka, ketika Majapahit dipilih sebagai tokoh utama, yang lain otomatis dijadikan figuran.
Dalam narasi sejarah resmi, Majapahit ditempatkan dalam posisi linier: Sriwijaya--Majapahit--Mataram--VOC--Hindia Belanda--Indonesia. Sebuah progresi yang sangat rapi, sangat Eropa, dan sangat kolonial. Dalam kenyataan sejarah, Nusantara bukanlah taman bertingkat yang ditanami satu demi satu oleh benih-benih kerajaan besar. Ia adalah semak belukar interaksi lokal, perdagangan maritim, dan pertukaran budaya yang tidak mengenal pusat. Bila Majapahit adalah pusat, maka sejarah yang lain adalah pinggiran, dan dengan itu, kekuasaan menanamkan hegemoni dalam bentuk kurikulum.
Menghapus Majapahit dari narasi nasional bukan berarti menghapus eksistensinya, tetapi menolak dominasi simboliknya. Ini adalah tindakan dekonstruksi dalam pengertian Derrida: bukan meruntuhkan bangunan, melainkan membuka sendi-sendi asumsi yang menopangnya. Dalam hal ini, asumsi bahwa Indonesia membutuhkan Majapahit sebagai pembenar historis atas nasionalismenya. Tapi mungkinkah kita membayangkan nasionalisme tanpa imperium? Bisakah Indonesia dibayangkan tanpa mitos ekspansionis?
Jawabannya: sangat bisa. Karena sejarah Indonesia yang paling hidup justru berada di luar Majapahit. Di pesisir Makassar yang terhubung ke Istanbul. Di pelabuhan Banten yang menjadi persinggahan para saudagar Gujarat. Di Buton yang memiliki konstitusi tertulis sebelum republik memikirkan Pancasila. Di Minangkabau yang membangun sistem nagari berbasis deliberasi, bukan penaklukan. Semua ini tidak membutuhkan sumpah Gajah Mada. Mereka tidak berangkat dari keinginan untuk menyatukan, tetapi untuk bertahan, berinteraksi, dan membentuk jaringan.
Namun sejarah seperti itu tidak seksi dalam dunia arsitektur politik. Tidak ada monumen yang dapat dibangun atas nama "perdagangan rempah lokal" atau "konsensus adat." Tapi Majapahit menawarkan cerita besar, dan seperti semua cerita besar, ia berguna untuk membenarkan sentralisme, militerisme, dan romantisme nasional. Tak heran bila Orde Baru menjadikan Gajah Mada sebagai simbol disiplin dan integrasi. Tapi sejarawan yang baik tahu bahwa ketika mitos dipelihara oleh tentara, maka ia bukan lagi narasi, melainkan senjata.
Untuk itu, kita perlu menulis ulang sejarah nasional sebagai sejarah konektivitas, bukan dominasi. Bukan siapa yang menaklukkan siapa, tetapi siapa yang berinteraksi dengan siapa. Sejarah bukanlah silsilah raja-raja, tetapi jaringan makna yang dibentuk oleh bahasa, perdagangan, agama, dan perlawanan. Maka alih-alih menjadikan Majapahit sebagai pusat, mengapa tidak menjadikan lautan sebagai ruang utama sejarah Indonesia? Bukankah kita adalah bangsa pelaut, sebagaimana dicemooh oleh penjajah yang takut pada kapal-kapal kecil?
Tentu, ide ini akan ditolak oleh para penjaga kesucian sejarah nasional. Mereka akan bertanya: jika tidak Majapahit, lalu apa? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan kemalasan berpikir. Karena dalam sejarah, tidak perlu satu pusat. Kita bisa memiliki banyak narasi, banyak sumbu, bahkan banyak Indonesia. Sejarah tidak harus seperti peta ibukota, tapi bisa seperti gugusan pulau yang tidak mengklaim pusat.
Dalam kerangka ini, Majapahit tetap bisa hadir, tapi tidak sebagai aktor tunggal. Ia adalah salah satu suara dalam orkestra sejarah, bukan konduktor. Ia bisa dikritik karena ekspansinya, dipertanyakan karena bukti arkeologinya, dan bahkan ditertawakan karena klaim-klaim yang lebih cocok sebagai sinetron kerajaan. Humor adalah cara terbaik untuk menjinakkan mitos, dan dalam hal ini, satire bisa menjadi metode historiografi yang membebaskan.
Bayangkan bila buku sejarah kita menulis: "Pada abad ke-14, sebuah kerajaan bernama Majapahit muncul di Jawa Timur. Ia mengklaim wilayah yang tidak pernah ia kunjungi, menaklukkan pulau-pulau yang tidak tahu bahwa mereka sedang ditaklukkan, dan di kemudian hari, dijadikan pahlawan nasional oleh orang-orang yang hidup enam abad kemudian." Tentu, akan ada yang marah. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, sejarah akan terasa jujur.
Indonesia tanpa Majapahit bukanlah Indonesia tanpa sejarah. Ia adalah Indonesia yang berani mengakui bahwa masa lalu bukanlah sebuah jalan tol yang menuju satu arah. Ia adalah jaringan jalan tikus, pelabuhan-pelabuhan sunyi, dan kesepakatan-kesepakatan lokal yang lebih nyata dari semua ukiran di relief candi. Ia adalah sejarah yang ditulis bukan untuk menyatukan, tapi untuk memahami.
Dan jika nanti ada yang berkata: "Tapi Majapahit adalah kebanggaan kita," maka jawabannya sederhana. Kebanggaan tidak harus dibangun di atas mitos imperium. Ia bisa dibangun dari keragaman, dari kekacauan yang kreatif, dari sejarah-sejarah kecil yang tidak pernah dimasukkan dalam ujian nasional. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang punya satu cerita, tapi bangsa yang berani mendengarkan cerita-cerita yang selama ini dibungkam.
Jadi, mari menulis Indonesia tanpa Majapahit. Bukan karena kita benci, tapi karena kita cinta pada kemungkinan lain yang lebih jujur, lebih egaliter, dan lebih manusiawi. Lagipula, kerajaan besar pun suatu hari bisa pensiun. Kenapa tidak biarkan Majapahit beristirahat dengan tenang, tanpa harus terus diseret ke ruang kelas dan panggung upacara?
Kita tentu ingat, atau paling tidak, kita diharuskan untuk mengingat, bahwa ada sumpah suci yang konon diucapkan oleh seorang mahapatih yang lebih mirip Adolf Hitler dari abad 14 ketimbang seorang pejabat agraria. Sumpah itu berbunyi "amukti palapa," yang oleh para juru tafsir nasionalisme ditafsirkan sebagai komitmen suci untuk menaklukkan wilayah yang kini disebut Indonesia. Sebuah interpretasi yang, dalam konteks genealogi kekuasaan, sangatlah menguntungkan bagi proyek negara. Namun Michel Foucault mungkin akan tersenyum getir: kebenaran tidak pernah lahir dari fakta, melainkan dari peredaran diskursif yang dikendalikan oleh siapa yang berhak bicara. Dan para arkeolog kolonial, sejarawan negara, serta pejabat kebudayaan adalah para ventriloquist yang menjadikan Majapahit sebagai boneka bicara mereka.
Majapahit, seperti semua legenda imperium, bekerja bukan karena kebenarannya, melainkan karena repetisi. Ia diulang dalam buku sejarah, diukir di relief candi yang direstorasi secara nasionalistik, dan diperdagangkan dalam upacara-upacara kebudayaan yang dibiayai APBN. Majapahit adalah Disneyland dari masa lalu kita---tidak penting apakah ia benar-benar terjadi, yang penting ia terlihat meyakinkan.
Menulis sejarah Indonesia tanpa Majapahit tentu dianggap sebagai tindakan revolusioner, bahkan mungkin subversif. Ini seperti membayangkan gereja tanpa salib atau konser rock tanpa gitar. Namun justru di sinilah persoalannya: mengapa satu kerajaan yang eksistensinya terbatas dalam ruang-waktu tertentu harus dijadikan poros tunggal dari sebuah narasi nasional yang konon majemuk? Ini adalah pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh mereka yang masih percaya bahwa sejarah adalah warisan, bukan konstruksi. Seperti yang dikatakan oleh Hayden White, sejarah adalah narasi yang diisi oleh pilihan-pilihan retoris, bukan fakta objektif. Maka, ketika Majapahit dipilih sebagai tokoh utama, yang lain otomatis dijadikan figuran.
Dalam narasi sejarah resmi, Majapahit ditempatkan dalam posisi linier: Sriwijaya--Majapahit--Mataram--VOC--Hindia Belanda--Indonesia. Sebuah progresi yang sangat rapi, sangat Eropa, dan sangat kolonial. Dalam kenyataan sejarah, Nusantara bukanlah taman bertingkat yang ditanami satu demi satu oleh benih-benih kerajaan besar. Ia adalah semak belukar interaksi lokal, perdagangan maritim, dan pertukaran budaya yang tidak mengenal pusat. Bila Majapahit adalah pusat, maka sejarah yang lain adalah pinggiran, dan dengan itu, kekuasaan menanamkan hegemoni dalam bentuk kurikulum.
Menghapus Majapahit dari narasi nasional bukan berarti menghapus eksistensinya, tetapi menolak dominasi simboliknya. Ini adalah tindakan dekonstruksi dalam pengertian Derrida: bukan meruntuhkan bangunan, melainkan membuka sendi-sendi asumsi yang menopangnya. Dalam hal ini, asumsi bahwa Indonesia membutuhkan Majapahit sebagai pembenar historis atas nasionalismenya. Tapi mungkinkah kita membayangkan nasionalisme tanpa imperium? Bisakah Indonesia dibayangkan tanpa mitos ekspansionis?
Jawabannya: sangat bisa. Karena sejarah Indonesia yang paling hidup justru berada di luar Majapahit. Di pesisir Makassar yang terhubung ke Istanbul. Di pelabuhan Banten yang menjadi persinggahan para saudagar Gujarat. Di Buton yang memiliki konstitusi tertulis sebelum republik memikirkan Pancasila. Di Minangkabau yang membangun sistem nagari berbasis deliberasi, bukan penaklukan. Semua ini tidak membutuhkan sumpah Gajah Mada. Mereka tidak berangkat dari keinginan untuk menyatukan, tetapi untuk bertahan, berinteraksi, dan membentuk jaringan.
Namun sejarah seperti itu tidak seksi dalam dunia arsitektur politik. Tidak ada monumen yang dapat dibangun atas nama "perdagangan rempah lokal" atau "konsensus adat." Tapi Majapahit menawarkan cerita besar, dan seperti semua cerita besar, ia berguna untuk membenarkan sentralisme, militerisme, dan romantisme nasional. Tak heran bila Orde Baru menjadikan Gajah Mada sebagai simbol disiplin dan integrasi. Tapi sejarawan yang baik tahu bahwa ketika mitos dipelihara oleh tentara, maka ia bukan lagi narasi, melainkan senjata.
Untuk itu, kita perlu menulis ulang sejarah nasional sebagai sejarah konektivitas, bukan dominasi. Bukan siapa yang menaklukkan siapa, tetapi siapa yang berinteraksi dengan siapa. Sejarah bukanlah silsilah raja-raja, tetapi jaringan makna yang dibentuk oleh bahasa, perdagangan, agama, dan perlawanan. Maka alih-alih menjadikan Majapahit sebagai pusat, mengapa tidak menjadikan lautan sebagai ruang utama sejarah Indonesia? Bukankah kita adalah bangsa pelaut, sebagaimana dicemooh oleh penjajah yang takut pada kapal-kapal kecil?
Tentu, ide ini akan ditolak oleh para penjaga kesucian sejarah nasional. Mereka akan bertanya: jika tidak Majapahit, lalu apa? Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan kemalasan berpikir. Karena dalam sejarah, tidak perlu satu pusat. Kita bisa memiliki banyak narasi, banyak sumbu, bahkan banyak Indonesia. Sejarah tidak harus seperti peta ibukota, tapi bisa seperti gugusan pulau yang tidak mengklaim pusat.
Dalam kerangka ini, Majapahit tetap bisa hadir, tapi tidak sebagai aktor tunggal. Ia adalah salah satu suara dalam orkestra sejarah, bukan konduktor. Ia bisa dikritik karena ekspansinya, dipertanyakan karena bukti arkeologinya, dan bahkan ditertawakan karena klaim-klaim yang lebih cocok sebagai sinetron kerajaan. Humor adalah cara terbaik untuk menjinakkan mitos, dan dalam hal ini, satire bisa menjadi metode historiografi yang membebaskan.
Bayangkan bila buku sejarah kita menulis: "Pada abad ke-14, sebuah kerajaan bernama Majapahit muncul di Jawa Timur. Ia mengklaim wilayah yang tidak pernah ia kunjungi, menaklukkan pulau-pulau yang tidak tahu bahwa mereka sedang ditaklukkan, dan di kemudian hari, dijadikan pahlawan nasional oleh orang-orang yang hidup enam abad kemudian." Tentu, akan ada yang marah. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, sejarah akan terasa jujur.
Indonesia tanpa Majapahit bukanlah Indonesia tanpa sejarah. Ia adalah Indonesia yang berani mengakui bahwa masa lalu bukanlah sebuah jalan tol yang menuju satu arah. Ia adalah jaringan jalan tikus, pelabuhan-pelabuhan sunyi, dan kesepakatan-kesepakatan lokal yang lebih nyata dari semua ukiran di relief candi. Ia adalah sejarah yang ditulis bukan untuk menyatukan, tapi untuk memahami.
Dan jika nanti ada yang berkata: "Tapi Majapahit adalah kebanggaan kita," maka jawabannya sederhana. Kebanggaan tidak harus dibangun di atas mitos imperium. Ia bisa dibangun dari keragaman, dari kekacauan yang kreatif, dari sejarah-sejarah kecil yang tidak pernah dimasukkan dalam ujian nasional. Karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang punya satu cerita, tapi bangsa yang berani mendengarkan cerita-cerita yang selama ini dibungkam.
Jadi, mari menulis Indonesia tanpa Majapahit. Bukan karena kita benci, tapi karena kita cinta pada kemungkinan lain yang lebih jujur, lebih egaliter, dan lebih manusiawi. Lagipula, kerajaan besar pun suatu hari bisa pensiun. Kenapa tidak biarkan Majapahit beristirahat dengan tenang, tanpa harus terus diseret ke ruang kelas dan panggung upacara?
Diubah oleh tanmalako091539 Kemarin 21:32
0
15
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan