- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Dua Rasa Satu Dapur Sejarah: Narasi Kolonial dalam Sejarah Nasional
TS
tanmalako091539
Dua Rasa Satu Dapur Sejarah: Narasi Kolonial dalam Sejarah Nasional
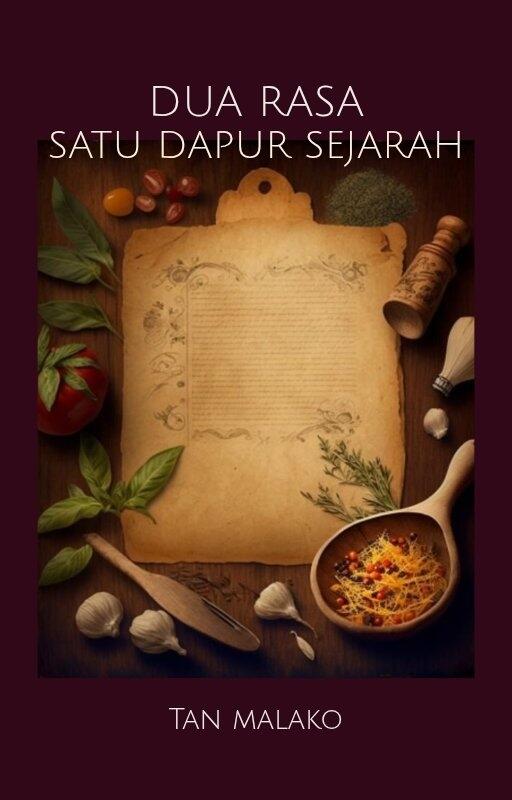
Dalam sejarah resmi yang diajarkan di sekolah-sekolah, Majapahit dan Hindia Belanda tampak seperti dua bab yang dipisahkan oleh jarak ratusan tahun, masing-masing dengan protagonis dan antagonisnya sendiri. Majapahit ditampilkan sebagai mahakarya Nusantara—kerajaan yang mempersatukan wilayah dari Sabang hingga Merauke, sementara Hindia Belanda digambarkan sebagai kekuatan kolonial yang menghisap sumber daya demi kemakmuran negeri kincir angin. Namun, jika kita mengupas lapisan retorika, mengganti baju hero and villain, pahlawan dan penjahat, lalu memeriksa bumbu yang digunakan, kita akan menemukan sesuatu yang menarik: kedua kekuasaan ini beroperasi dengan resep yang sama, hanya kokinya yang berbeda.
Majapahit, menurut narasi populer, adalah kerajaan agraris yang menjelma menjadi kerajaan maritim demi cita-cita politik besar—Nusantara bersatu. Hindia Belanda, di sisi lain, adalah perusahaan dagang yang berkembang menjadi negara kolonial. Tetapi di balik semua variasi kemasan itu, keduanya adalah imperium rempah-rempah. Dalam istilah ekonomi-politik global, mereka adalah pengatur alur komoditas bernilai tinggi yang menghubungkan produsen di wilayah Nusantara dengan konsumen di pusat kekuasaan jauh di luar zona produksi. Majapahit mengirim rempah ke istana-istana Asia, Hindia Belanda mengirimnya ke meja makan bangsawan Eropa. Di antara keduanya, bumbu tetap bumbu; perbedaannya hanya pada siapa yang memonopoli sendok sayur.

Baik Majapahit maupun Hindia Belanda sama-sama memiliki pusat kekuasaan yang jauh dari sumber rempah. Trowulan, dengan tanah liatnya yang hangat dan jarak ribuan kilometer dari Kepulauan Maluku, tidak lebih dekat ke pala daripada Batavia dengan kanal-kanalnya yang penuh nyamuk. Jarak ini, yang dalam teori longue durée Fernand Braudel adalah faktor geografis yang membentuk sejarah selama berabad-abad, memaksa keduanya membangun sistem kontrol maritim: armada, aliansi politik, dan jaringan tribut yang memastikan rempah mengalir ke pusat tanpa terganggu “gangguan” seperti kedaulatan lokal atau harga pasar bebas.
Keduanya pun mengandalkan narasi kejayaan untuk membenarkan penguasaan jalur perdagangan. Majapahit memiliki Sumpah Palapa yang dikutip di buku teks seperti wahyu politik—janji Gajah Mada untuk tidak bersenang-senang sebelum menguasai seluruh Nusantara. Hindia Belanda memiliki laporan tahunan VOC yang penuh istilah akuntansi, tetapi sama-sama dibalut euforia tentang “memastikan kestabilan perdagangan” demi kepentingan bersama (tentu saja “bersama” di sini dimaksudkan untuk dewan direksi atau raja di negeri jauh). Perbedaan bahasanya jelas—satu memakai sanskerta politik, satunya bahasa dagang Belanda—namun intinya sama: rempah adalah alasan dan tujuan.
Di tingkat operasional, keduanya menunjukkan kemiripan yang membuat kita bertanya-tanya apakah sejarah Nusantara adalah produksi ulang dengan pemeran baru. Majapahit memperluas pengaruhnya ke Maluku, Ternate, dan Banda melalui kombinasi ekspedisi militer dan diplomasi tribut. Hindia Belanda berbuat hal yang sama, meski dengan istilah yang lebih korporat: “mengamankan jalur perdagangan”, “menegakkan monopoli”, dan “perjanjian eksklusif”. Dalam bahasa teori politik, keduanya menguasai choke points—titik-titik vital yang mengendalikan arus barang, dalam hal ini rempah yang lebih berharga daripada emas di pasar dunia abad pertengahan dan awal modern.
Bahkan masa berkuasa mereka pun hampir sejajar dalam panjangnya, sekitar tiga abad. Majapahit berdiri tegak (setidaknya dalam imajinasi sejarah) dari akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-16, sementara Hindia Belanda bertahan dari awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Tiga abad adalah waktu yang cukup lama untuk mengubah lanskap ekonomi, bahasa, dan pola pikir masyarakat, tapi juga cukup untuk menciptakan kejenuhan dan celah bagi kekuatan baru untuk mengambil alih. Seperti kata Braudel, struktur jangka panjang yang menopang kekuasaan akhirnya runtuh ketika ekonomi-monde bergeser: rempah bukan lagi primadona, dan jalur perdagangan menemukan komoditas baru.
Majapahit runtuh ketika kekuatan maritim Islam seperti Demak, Malaka, dan Makassar merebut pangsa pasar rempah, memotong jalur distribusi yang sebelumnya terkonsentrasi di bawah kendalinya. Hindia Belanda mengalami nasib serupa ketika monopoli VOC hancur oleh kebangkrutan, kompetisi kolonial lain, dan pergeseran pasar dunia ke kopi, gula, dan timah. Jika diibaratkan restoran, keduanya bangkrut karena pelanggan menemukan menu baru, sementara dapur terlalu sibuk menghitung stok bumbu lama.
Yang membuat perbandingan ini semakin menarik adalah cara keduanya membungkus kekuasaan dalam narasi moral dan kultural. Majapahit dikisahkan dalam kakimpoi dan kronik sebagai pemersatu, pembawa ketertiban, dan pelindung perdagangan. Hindia Belanda membungkus monopoli dalam bahasa “peradaban” dan “modernisasi”. Dua baju retorika ini, meskipun berbeda motif kainnya, memiliki potongan pola yang sama: kekuasaan perlu dilegitimasi bukan hanya dengan kekuatan militer, tetapi juga dengan kisah yang membuatnya terlihat perlu.
Dalam kerangka analisis pascakolonial, seperti yang diuraikan Edward Said dalam Orientalism, kedua entitas ini memproduksi citra tentang wilayah yang mereka kuasai—baik untuk konsumsi internal maupun eksternal. Majapahit memproduksi citra Nusantara sebagai satu kesatuan yang patut ditaklukkan demi ketertiban kosmik, Hindia Belanda memproduksi citra Nusantara sebagai wilayah eksotik yang perlu dikelola oleh tangan modern Eropa. Dalam kedua kasus, citra itu tidak sepenuhnya mencerminkan realitas, melainkan konstruksi ideologis yang berfungsi menjaga arus rempah dan stabilitas kekuasaan.
Jika kita mau sedikit nakal membayangkan, Majapahit dan Hindia Belanda seolah dua musim dari satu serial televisi sejarah: lokasi syuting sama, alur besar sama, hanya kostum dan pemerannya yang berganti. Musim pertama: seorang patih bersumpah demi rempah. Musim kedua: seorang gubernur jenderal menandatangani kontrak monopoli. Penonton—yakni masyarakat yang hidup di bawahnya—tetap menjadi figuran yang menanam, memanen, dan mengirimkan bumbu ke pusat kekuasaan. Perubahan terbesar mungkin hanya pada bahasa perintah dan bentuk pajak.
Jika kita meminjam kacamata Braudel, kita bisa melihat rempah sebagai “struktur dalam” sejarah Nusantara, yang lebih abadi daripada dinasti atau bendera. Rempah menjadi poros ekonomi-monde yang mengatur ritme politik, diplomasi, dan peperangan. Dalam jangka panjang, yang berganti hanyalah operatornya—hari ini raja, besok gubernur, lusa mungkin direktur perusahaan multinasional. Tetapi rempah, sebagai komoditas dan simbol, tetap menuntut jaringan kontrol, kekuatan maritim, dan narasi pembenaran.
Di titik ini, sulit untuk tidak tersenyum pahit ketika membaca narasi resmi yang memisahkan Majapahit dan Hindia Belanda secara total. Dalam logika formal, mereka memang berbeda: yang satu kerajaan pribumi, yang satu koloni asing. Tetapi dalam logika material, keduanya adalah variasi dari model yang sama: pusat kekuasaan yang memonopoli komoditas strategis melalui penguasaan jalur distribusi dan produksi. Bagi petani pala di Banda atau nelayan di Ambon abad ke-15 dan ke-18, mungkin perbedaan itu tidak terasa. Pajak tetap dipungut, rempah tetap dikirim, dan kapal perang tetap singgah di pelabuhan.
Ironi terbesar adalah bagaimana narasi Majapahit kini dipakai untuk membangun legitimasi nasional—seringkali dengan bahasa yang sama otoriternya seperti retorika kolonial—sementara narasi Hindia Belanda dikecam habis-habisan sebagai imperialisme. Padahal, jika kita mau jujur, yang satu adalah imperialisme berbasis mitos sejarah, yang lain imperialisme berbasis kontrak dagang. Keduanya sama-sama menggunakan rempah sebagai alasan untuk mengatur hidup orang lain.
Akhirnya, membandingkan Majapahit dan Hindia Belanda bukan untuk menyamakan derajat keduanya dalam sejarah nasional, melainkan untuk menyadarkan kita bahwa bentuk kekuasaan sering kali lebih ditentukan oleh struktur ekonomi dan geografi daripada oleh niat baik atau jahat para penguasanya. Dalam dunia yang dikendalikan oleh bumbu, siapa pun yang memegang kunci dapur akan berperilaku seperti chef yang menentukan menu—entah ia mengenakan kain batik atau mantel wol Eropa.
Sejarah Nusantara, dalam pandangan ini, adalah sejarah pergantian koki di dapur rempah yang sama. Kita, para penikmat dan pekerja dapur, sebaiknya mulai bertanya: kapan kita belajar memasak untuk diri sendiri?
0
9
0
Komentar yang asik ya
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan