- Beranda
- Komunitas
- Story
- Stories from the Heart
Bagaimana Kalau Aku Mencintai Kekasihmu?
TS
Astri.zee
Bagaimana Kalau Aku Mencintai Kekasihmu?
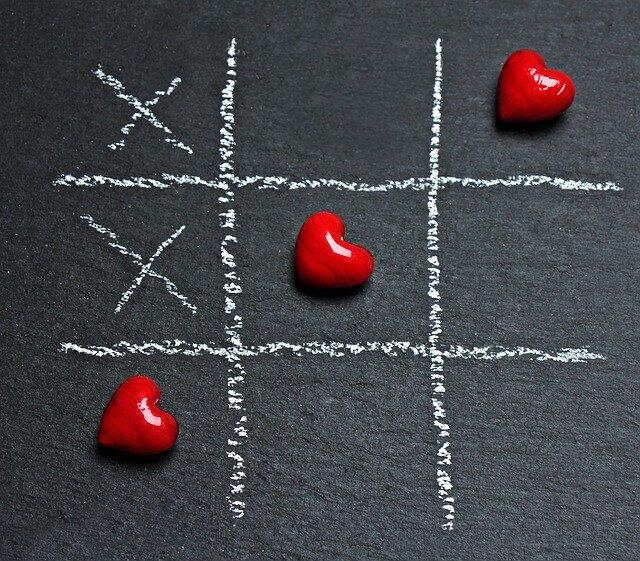
“Bagaimana kalau aku mencintai kekasihmu?”
Telingaku berdenging karena suara itu. Apa tadi yang dia ucapkan? Cinta? Cinta siapa? Kekasih? Kekasih siapa?
Aku mengerjap, melihat dia yang juga tengah menatapku. Lantas suaranya kembali terngiang, “Bagiamana kalau aku mencintai kekasihmu?”
Tawaku mengudara karenanya. Sebelah tanganku memukul pelan lengannya. “Becandanya boleh juga,” ujarku masih diselingi tawa.
Namun, tidak demikian dengan dia. Perempuan bersurai hitam sebahu itu tidak tertawa selayaknya orang yang baru saja melempar canda. Tidak tergelak lantas berucap, “Kena kamu,” seperti orang nge-prank pada umumnya. Wajahnya masih seserius itu. Tatapannya bahkan lebih intens. Seolah menegaskan bahwa dia tidak sedang bercanda.
“Aku gak lagi becandain kamu.” Dan semua itu diperkuat dengan kalimat penjelas darinya.
Tawaku lenyap, berganti perasaan tak karuan. Jantungku mulai berpacu di atas normal. Tanganku mendingin. Lantas beberapa adegan yang sempat tertangkap netra terputar satu per satu.
Pernah satu kali aku jumpai dia tengah berjalan dengan kekasihku. Aku pikir sekadar jalan biasa, sesama teman. Namun, ada satu hal ganjil di sana. Tangan mereka saling bertaut. Bodohnya aku justru berpikir jika itu gandengan tangan biasa. Sesama teman. Mungkin kekasihku takut dia ketinggalan jejak. Maklum mereka berteman sejak lama.
Lain waktu, aku dapati keduanya asyik mengomentari sesuatu di layar ponsel. Entah tentang apa. Lantas kekasihku menepuk pelan puncak kepalanya. Hal yang jarang sekali dilakukan padaku. Namun, aku masih berpikiran positif. Karena bagi kekasihku, dia layaknya adik yang kadang manja dan perlu dilindungi.
Pernah satu kali aku bertanya tentang itu pada kekasihku. Tentang kedekatan mereka.
“Kami sudah saling mengenal sejak masih mengompol, jadi, yah ... seperti itulah kedekatan kami,” jawab kekasihku sembari mengedikkan bahu. Yang anehnya, aku terima begitu saja.
Namun, sekarang aku mulai menemukan titik terang. Gandengan tangan itu bukan sentuhan antar teman biasa. Tepukan di kepala itu, bukan selayaknya perlakuan kakak pada adiknya. Kedikkan bahu yang kekasihku tunjukan adalah penegas semuanya. Bahwa benar mereka memang sedekat itu. Iya, ada sesuatu antara kedua insan paling dekat denganku itu.
Secepat kesimpulan itu muncul, secepat itu pula telapak tanganku mendarat di pipinya. Kaget! Bukan hanya dia yang terkejut, tapi aku juga. Aku seperti kehilangan kendali pada tangan sendiri. Gemetar jemariku setelahnya. Terlebih saat melihat bekas merah di pipi putihnya.
Menelan ludah, aku lantas berujar, “Kamu pantes dapet itu, supaya kamu sadar. Dia kekasihku.” Suaraku bergetar. Bahkan di kalimat terakhir seperti tercekik. Seakan lidahku sendiri ragu dengan status kekasih itu. Benarkah dia benar-benar kekasihku?
Di luar dugaan, dia justru tertawa. Awalnya pelan, lalu berubah kencang. Kepalanya tergeleng berulang sembari menyebut namaku. Seperti menertawakanku. “Kamu tu bego banget, ya!” ucapnya kemudian dengan penekanan pada kata bego. Hal yang baru pertama kali dia lakukan padaku. Selama ini sikapnya sungguh manis, layaknya sahabat yang tidak pernah menyakiti sahabatnya sendiri.
“Kamu gak nyadar kayak apa sikap dia ke kamu selama ini?” ujarnya lagi, masih setegas tadi. “Kamu pura-pura gak ngerasa atau emang gak peka? Hm?” imbuhnya dengan pandangan menghunjam.
Ironisnya, aku tak bisa menjawab. Detak jantungku bekerja lebih cepat. Tremor di tanganku semakin kentara.
Sikapnya? Aku mengulang pertanyaan itu dalam hati. Kekasihku, dia ... lebih memperlakukanku layaknya majikan yang harus dituruti segala perintahnya. Nyaris tidak ada pertengkaran dalam hubungan kami. Dia selalu mengiyakan apa mauku.
Lalu ... netraku mengarah pada benda berkilau di jari manis. Cincin pertunangan yang aku minta darinya.
Alisku berjengit, senyumku sedikit terbit. Merasa telah menemukan jawaban yang benar. “Ini!” Aku mengangkat tanganku di depan dada, mempertontonkan cincin bertakhta berlian itu. “Kamu lupa kami udah tunangan? Itu artinya dia emang kekasihku.” Aku mencoba mengangkat dagu saat mengatakan itu. Tak ingin terintimidasi lagi.
Namun, lagi-lagi dia tertawa. Lagi-lagi menggeleng sembari menyebutkan namaku. “Itu cuma balas budi tau gak? Dia gak mungkin nolak permintaan orang yang udah berjasa buat hidupnya.”
Alisku bertaut. “Maksudnya?”
“Bokapmu yang minta dia ngelamar kamu. Kamu pikir apa yang bisa dia lakukan sama orang yang udah biayain kuliah dan ngasih kerjaan?”
Bagai sambaran petir di siang bolong, aku terlalu syok mendengar semua itu. Benar, Ayah yang telah membiayai pendidikan kekasihku. Benar, Ayah juga yang memberi posisi bergengsi di perusahaan. Namun, apa benar kekasihku sepicik itu?
“Gak mungkin.” Kali ini kepalaku yang tergeleng.
Dia mengangkat bahu sekilas. “Serah kamu sih, mau percaya atau gak. Tapi saran aku, tanyain langsung sama dia!”
“Tapi kenapa?” sahutku cepat. “Kenapa kamu tega nglakuin itu? Kenapa kamu tega ngehianatain temen sendiri?” Mataku memanas, pandanganku mengabur, tertutup selapis cairan yang mungkin sebentar lagi jebol.
“Bukan aku! Bukan aku yang ngerebut dia dari kamu! Tapi kamu! Kamu yang udah ngelakuin itu!” Telunjuknya mengarah padaku. Tak jauh beda denganku, suaranya pun mulai parau. “Kamu yang udah ngambil dia dari aku ....” Kali ini suaranya pelan, tapi terdengar sarat kepedihan.
“Maksud kamu apa?”
Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. Jawaban yang membuat duniaku seakan berhenti berputar.
“Kami udah backstreet lama. Bukan karena gak berani go public, tapi karena dia ingin orang-orang tau pas dia bener-bener udah serius. Pas kami siap melangkah ke jenjang lebih tinggi.” Pandangannya menerawang saat mengatakan itu. Pun bisa aku lihat tarikan-tarikan di sudut bibirnya meski tipis.
Namun, semua ekspresi itu segera berganti saat kalimat berikutnya terucap, “Tapi tiba-tiba kamu ngrusak semuanya! Si anak manja yang manfaatin kekuasaan bapaknya buat dapetin dia.”
Leleh. Air mataku meleleh karena ucapannya. Berderai-derai menuruni pipi. Membekap mulut dengan kepalan tangan, aku mencegah isak tangis keluar. Meski yang terjadi tenggorokanku sakit sekali.
“Plis ....” dia kembali berucap. Kali ini dengan nada penuh permohonan. “Balikin dia sama aku. Aku gak bisa liat kalian bersama. Aku mohon.” Sama sepertiku, air matanya juga tumpah. Entah kesakitan macam apa yang telah dia rasakan. Yang jelas dari sorot matanya, aku tahu ada rindu yang coba dia pendam. Ada hasrat yang berusaha dia tahan-tahan.
Hingga mungkin kini dia berada di titik terendahnya. Tak mampu lagi menahan segala impitan beban. Dan memutuskan membongkar semuanya.
Lalu ... bagaimana denganku? Apa dia tidak memikirkan perasaanku? Aku juga mencintainya. Aku juga menginginkan lelaki itu.
***
Ini sulit. Teramat sulit. Untuk sampai di hadapannya dan mengatakan semuanya tidak mudah. Aku harus berulang kali berperang dengan logika dan hati.
Sisi teregoisku memerintahkan agar tidak perlu meminta klarifikasi darinya. Membiarkan semuanya berjalan seperti sedia kala. Seolah dua hari lalu aku tidak mendengar apa-apa. Lantas beranggapan bahwa dia benar-benar tulus padaku.
Namun, sisi yang lain mencegah itu. Mengatakan bahwa akan sangat egois jika aku membunuh dengan paksa perasaan dua insan yang saling mencinta. Lagi pula akan jadi apa rumah tanggaku kelak jika apa yang perempuan itu sampaikan kemarin adalah kebenaran?
Maka, di sinilah aku berada. Di hadapan seorang pria yang masih sangat kukagumi. Masih sangat kusayangi.
“Apa kamu tulus mencintaiku?”
Itu kalimat yang aku ajukan padanya dua menit lalu. Harusnya, tidak butuh jawaban lama untuk menjawab, kan? Jika dia benar-benar merasakannya. Namun, lelaki itu bungkam beberapa saat lamanya. Seolah pertanyaanku adalah soal ujian yang butuh rumus untuk mengerjakannya.
“Tentu saja,” jawabnya.
Tidak. Bukan ekspresi seperti itu yang ingin aku lihat. Harusnya dia tepat menatapku saat mengatakan itu. Bukan malah sembari tersenyum seperti ada hal lucu.
“Apa ada perempuan lain yang kamu cintai?”
Aku melihatnya, meski sekilas dia tampak terkejut. Namun, segera dia tutupi dengan kekehan. “Kamu ngomong apa, sih?”
“Aku serius!” sahutku segera. Pun dengan tatapan menghunjam. “Katakan sejujurnya, plis!” suaraku tercekat. Padahal dia belum mengatakan apa-apa, tapi entah kenapa rasa takut sudah lebih dulu menjalari diri. Takut jika jawabannya nanti akan lebih melukaiku.
Dia menunduk, masih belum menjawab. Embusan napasnya terdengar lebih berat. Sepanjang mengenalnya tak pernah aku lihat dia segamang itu.
“Kalau aku bilang iya, apa kamu marah?” Kepalanya kembali terangkat. Dia menatapku sendu.
“Siapa?” Bukannya menjawab, aku justru bertanya balik. Ingin segera tahu siapa perempuan itu.
Lantas dia menyebutkan nama itu. Orang yang begitu dekat dengan kami. Orang yang aku kira hanya berstatus sahabatnya. Perempuan yang mengaku padaku dua hari lalu.
Iya, itu benar, mereka memang memiliki hubungan spesial.
Aku memalingkan wajah. Menyembunyikan tetes demi tetes air mata yang tumpah.
Lantas aku dengar gerakan di seberang meja. Dia bangkit, menghampiriku dan berlutut di depanku. “Hei ... sory ...,” ucapnya lemah.
Entah dia minta maaf untuk apa. Untuk kebohongan yang dia lakukan atau untuk kejujurannya barusan.
Menelan ludah kelat, aku menyeka kasar pipi dengan jemari. “Jadi benar, apa yang dia bilang?” Asumsiku perempuan itu telah lebih dulu bercerita padanya. Tentang pembicaraan kami dua hari lalu.
Lagi dia menunduk. Tidak menjawab. Dan bukankah diam berarti iya? Pun menjelaskan jika asumsiku benar.
Menggigit bibir bawah, aku mencoba menahan gemetarnya. Menahan isak yang lagi-lagi memaksa keluar. Sudah berapa kali aku menangis sejak kemarin? Kenapa jadi cengeng begini?
Dia panik, berulang kali menyebut namaku sembari meminta maaf. Tangan yang coba menyeka air mataku itu, aku tepis kasar.
“Aku beneran minta maaf,” ujarnya, entah untuk ke berapa kali.
“Kamu pikir hanya dengan minta maaf semua selesai?” tanyaku dengan suara bindeng. Air mataku sudah tak lagi membanjir. Menyisakan sensasi tak nyaman di kelopak. Sepertinya bengkak. Lagi.
“Jika aku gak tau ini, apa kamu akan tetap menyembunyikannya? Lantas bermain api di belakangku, begitu? Menikah denganku tapi menaruh hatimu pada perempuan lain, begitu?” cecarku.
“Aku bakalan pilih kamu. Aku janji mulai sekarang akan benar-benar nglupain dia. Aku janji.”
Tawaku pecah. Bagiku apa yang dia janjikan adalah lawakan paling lucu. Seperti janji-janji calon wakil rakyat saat berorasi meminta suara. Tahu, kan, bagaimana mereka? Setelah terpilih, wush! Janji-janji itu terbang bersama angin. Terlupakan, tertimbun harta dan jabatan yang didapatkan.
Sama seperti omongan lelaki ini.
“Kenapa baru sekarang berjanji? Kenapa gak kamu lakuin itu sejak dulu? Kenapa harus bersandiwara di depanku?” lagi, aku mencecarnya. Kali ini lebih lantang. Sehingga suaraku menggema di ruangan ini.
Dia tampak gelagapan. Seperti kesusahan mencari jawaban. Mungkin dia pikir aku akan luluh. Mudah dibodohi, seperti yang sudah-sudah. Namun, dia salah. Karena setiap orang akan selalu belajar dari kesalahan. Karena setiap orang akan mengambil hikmah dari pengalaman yang pernah dilalui.
“Itu karena ... dia terus membuntutiku. Perempuan itu yang terus menghubungiku.”
Aku mendengkus kasar mendengar jawaban itu. Apa yang coba dia lalukan? Playing victim? Seolah dia adalah korban? Padahal siapa pun tahu siapa korban sebenarnya di sini.
“Lihat ini!” Dia mengeluarkan ponsel, membuka kontak dan menunjuk satu nama. Perempuan itu. “Aku bakalan hapus nomornya. Dan gak akan lagi berhubungan dengannya. Aku janji.”
Memandangnya datar, aku sama sekali tidak tersentuh dengan tingkahnya. Meski dia benar-benar menghapus kontak itu. Aku melipat tangan di dada, menunggu dengan malas apa pun yang coba dia lalukan. Seperti menghapus foto-foto mereka. Lantas menunjukkan padaku jika ponselnya bersih dari segala yang berkaitan dengan perempuan itu.
“Kamu liat, kan? Aku benar-benar serius. Cuma kamu yang aku cintai.”
Jika saja kalimat terakhir itu dia ucapkan beberapa hari lalu, tentu aku akan sangat bahagia. Tentu hati ini akan berbunga-bunga. Namun, tidak kali ini. Sekarang apa yang dia ucapkan terdengar memuakkan. Membosankan.
“Bagus!” ucapku datar. Anehnya dia tetap mengukir senyum, seakan buta dengan ekspresi muak yang aku pertontonkan.
“Sekarang ....” Aku berdiri. “Silakan keluar dari sini!”
“Mak-maksudnya?” Dia ikut bangkit. Lantas menghampiriku yang berdiri di depan dinding kaca lebar di ruangan ini. Ruang manajer perusahaan milik ayahku.
Sebelum aku menjawab, pintu terbuka. Dua orang lelaki berpakaian hitam dan berbadan kekar memasuki ruangan. Mereka bodyguard Papa.
“Heh! Siapa suruh kalian masuk! Lan—”
“Aku yang menyuruh mereka.”
Kata-kataku praktis membungkam mulutnya. Membuat sumpah serapahnya teredam. Pun mencipta tatapan tak percaya darinya, kekasihku. Ah, masih pantaskah aku sebut dia kekasih? Atau perlu aku tambahi embel-embel mantan di depan kata itu, mantan kekasih.
Tidak! Aku rasa julukan itu pun tidak cocok. Mari kita sebut saja dia pecundang. Orang yang tidak berani mengakui perasaannya. Orang yang memilih bersandiwara demi tercapainya sebuah misi. Manusia serakah yang berhasrat memiliki segalanya.
“Tapi untuk apa?” tanyanya. Masih tak menangkap maksudku.
“Kamu bakalan dimutasi ke pelosok Kalimantan.”
Dahinya berkerut dalam. “Setauku gak ada cabang baru di sana.”
“Memang gak ada,” sahutku cepat. “Kamu bakalan jadi buruh di sana. Bantuin mereka menambang batu bara.”
“A-apa?”
Tawaku meledak. Bukan karena mendengar jawabannya, tapi karena tampang lucunya. Tampang orang yang sebentar lagi kehilangan hartanya.
“Kamu pasti bercanda, kan?”
“Bercanda?” ulangku kaku. “Bercanda itu ....” Aku sengaja mengerutkan kening, bersikap seolah tengah berpikir. Lantas kembali berujar, “Kayak kamu waktu ngejar-ngejar aku, dulu, iya? Itu yang disebut bercanda, kan?”
Dia menyugar rambut, tampak frustrasi. “Plis ... aku beneran menyesal, Yang.”
Aku muak dengan panggilan itu. Rasanya ingin muntah.
“Aku terima penyesalannya. Sekarang ....” Aku menggerakkan kepala, memberi isyarat pada dua bodyguard yang sedari tadi diam untuk menjalankan aksinya. Membawa pergi si pecundang.
Dia berontak, tidak mau diajak. Tapi tentu saja tenaganya kalah. Lalu dia meracau, meminta maaf sekaligus meminta bantuanku.
“Tunggu!” kataku saat mereka sampai di ambang pintu.
Senyumku tersungging melihatnya yang seolah menaruh harap begitu besar. Mungkin dia mengira aku membatalkan perintah itu. Padahal tidak.
Aku mengambil ponsel di tangannya. “Ini ... buatku ya?”
“Tentu, Sayang. Anything for you,” ujarnya antusias.
Tersenyum sinis, aku lantas melempar benda pipih itu hingga pecah berhamburan. Lantas aku mengibas tangan, seperti mengusir debu di telapaknya. “Oke, bawa dia! Ah, satu lagi ....” Aku menatapnya lekat. “Perempuan itu juga gak jauh beda sama kamu. Sekarang mungkin dia udah sampai di Papua atau pulau antah berantah.” Aku mengedikkan bahu. “So, selamat berjuang buat kalian.”
“Kamu gila!” umpatnya.
Lagi tawaku berderai. “Dan kalian udah salah berurusan sama orang gila ini.”
Kalimat makian selanjutnya tak lagi aku gubris karena dia yang digelandang pergi. Pun aku yang memalingkan kepala. Lebih tepatnya menyembunyikan setetes bening yang diam-diam menuruni pipi.
Lantas sebuah suara terngiang, “Bagaimana kalau aku mencintai kekasihmu?”
Jawabanku adalah ... jika aku tidak bisa memilikinya, maka tak seorang pun berhak atasnya.
Tamat
Sumber gambar: pixabay
husnamutia dan 7 lainnya memberi reputasi
8
1.7K
23
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan