- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
Benarkah Kamu Merindukan Ramadan?
TS
nohopemiracle
Benarkah Kamu Merindukan Ramadan?
Quote:
Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
 Sebelumnya, ane mohon untuk:
Sebelumnya, ane mohon untuk:





 Terima Kasih Kaskuser
Terima Kasih Kaskuser


 Sebelumnya, ane mohon untuk:
Sebelumnya, ane mohon untuk:





 Terima Kasih Kaskuser
Terima Kasih Kaskuser

Spoiler for Sumber.:
Serial "Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya”. Naskah yang ditulis Rusdi Mathariini mulanya dimuat di situs web Mojok.co sebagai serial Ramadhan dua tahun berturut-turut, yakni 2015-2016, dengan keterbacaan total mencapai enam ratus ribu kali baca.
Spoiler for Cek Repost.:

Quote:

Gambar : Mojok.co
Dalam pengalaman membaca, ketika ada rangkaian kalimat yang berdenting begitu telak, kadang kita bisa berhenti sejenak, untuk merenung dan berefleksi. Momen-momen itu sebagai penanda, pembatas karya yang selamanya tersimpan dalam cerita, sekaligus menjadi bukti bahwa sebuah rangkaian kalimat tak peduli sependek atau sesederhana apa pun, ia sanggup meninggalkan makna yang mendalam bagi kita.
Di thread kali ini ane bakal share cuplikan kisah terbaik dari "Kisah Sufi Dari Madura" karya Rusdi Mathari, ane share kembali disini karena banyak sekali pokok-pokok obrolan mengenai substansi ibadahyang dikupas dari perspektif yang menarik, dan sayang banget untuk dilewatkan. Penghargaan sebesar-besarnya untuk Alm. Rusdi Mathari.
Di thread kali ini ane bakal share cuplikan kisah terbaik dari "Kisah Sufi Dari Madura" karya Rusdi Mathari, ane share kembali disini karena banyak sekali pokok-pokok obrolan mengenai substansi ibadahyang dikupas dari perspektif yang menarik, dan sayang banget untuk dilewatkan. Penghargaan sebesar-besarnya untuk Alm. Rusdi Mathari.

Quote:
1.Merindukan Ramadan.

“Apa benar kamu merindukan Ramadan, Mat?”
“Ya benar, Cak.”
“Kamu senang berpuasa?”
“Senang, Cak.”
“Benar kamu senang puasa?”
“Maksudnya, Cak?”
“Menurutmu, kenapa orang Islam diwajibkan berpuasa?”
“Supaya bertakwa, Cak.”
“Itu tujuannya, Mat.”
“Jadi kenapa ada kewajiban, Cak?”
“Menurutmu kenapa ada hukum puasa? Kenapa kewajiban puasa diturunkan oleh Allah?”
“Lah, saya kan yang bertanya, Cak?”
“Mat, sesuatu yang diwajibkan adalah sesuatu yang manusia tidak suka mengerjakannya. Kalau manusia suka melakukannya, untuk apa diwajibkan, Mat?”
“Ya… tapi kan tetap wajib berpuasa, Cak?”
“Tentu saja, Mat. Masalahnya: benar kamu suka puasa?”
“Insya Allah benar, Cak.”
“Kalau begitu, ayo kita usulkan pada Allah agar puasa Ramadan tidak diwajibkan, apalagi hanya sebulan sekali dalam setahun, sebab manusia termasuk kamu sudah suka.”
“Ya ndak gitu juga kali, Cak.”
“Lah terus gimana? Kamu suka atau tak suka puasa?” Aslinya loh ya, Mat?”
“Sebetulnya sih agak tidak suka, Cak…”
“Terus salat, apa kamu juga suka salat? Lima kali sehari suka? Nanti malam ada tarawih, benar kamu suka mengerjakannya?”
“Iya sih, agak tidak suka juga…”
“Agak tidak suka atau tidak suka, Mat?”
“Agak…agak tidak… tidak suka, Cak.”
“Lalu kenapa kamu berpura-pura merindukaan Ramadan?”
“Ya gimana lagi, Cak, setiap tahunnya memang begitu.”
“Dan kamu ikut-ikutan, padahal kamu tidak suka puasa, tidak suka salat?”
“Siapa juga yang berani, Cak…”
“Itulah masalahmu. Mestinya kamu berterus terang pada Allah bahwa kamu tidak suka salat dan tidak suka puasa, tapi kamu siap dan ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu sehingga derajatmu tinggi di hadapan Allah. Kalau kamu suka, ya tidak tinggi derajatmu, Mat.”
“Waduh, Cak…”
“Waduh kenapa? Aku tanya ke kamu: orang suka, orang senang, terus melakukan atau menjalani yang disenangi atau disukai, apa hebatnya?”
“Ya ndak ada, Cak Biasa saja.”
“Jadi, benar kamu suka puasa?”
“Ya sudah, saya akan berterus terang pada Allah bahwa saya tidak suka, tapi saya akan menaati perintahnya dan akan melakukannya dengan ikhlas.”
“Begitu dong. Jangan pura-pura terus.”
“Sampeyan besok puasa kan, Cak?”
“Apa aku harus bilang dan pamer padamu kalau aku akan berpuasa?”
“Ya…salah lagi… Saya mau melanjutkan menyapu dulu ya, Cak….”
Spoiler for Merindukan Ramadan.:

“Apa benar kamu merindukan Ramadan, Mat?”
“Ya benar, Cak.”
“Kamu senang berpuasa?”
“Senang, Cak.”
“Benar kamu senang puasa?”
“Maksudnya, Cak?”
“Menurutmu, kenapa orang Islam diwajibkan berpuasa?”
“Supaya bertakwa, Cak.”
“Itu tujuannya, Mat.”
“Jadi kenapa ada kewajiban, Cak?”
“Menurutmu kenapa ada hukum puasa? Kenapa kewajiban puasa diturunkan oleh Allah?”
“Lah, saya kan yang bertanya, Cak?”
“Mat, sesuatu yang diwajibkan adalah sesuatu yang manusia tidak suka mengerjakannya. Kalau manusia suka melakukannya, untuk apa diwajibkan, Mat?”
“Ya… tapi kan tetap wajib berpuasa, Cak?”
“Tentu saja, Mat. Masalahnya: benar kamu suka puasa?”
“Insya Allah benar, Cak.”
“Kalau begitu, ayo kita usulkan pada Allah agar puasa Ramadan tidak diwajibkan, apalagi hanya sebulan sekali dalam setahun, sebab manusia termasuk kamu sudah suka.”
“Ya ndak gitu juga kali, Cak.”
“Lah terus gimana? Kamu suka atau tak suka puasa?” Aslinya loh ya, Mat?”
“Sebetulnya sih agak tidak suka, Cak…”
“Terus salat, apa kamu juga suka salat? Lima kali sehari suka? Nanti malam ada tarawih, benar kamu suka mengerjakannya?”
“Iya sih, agak tidak suka juga…”
“Agak tidak suka atau tidak suka, Mat?”
“Agak…agak tidak… tidak suka, Cak.”
“Lalu kenapa kamu berpura-pura merindukaan Ramadan?”
“Ya gimana lagi, Cak, setiap tahunnya memang begitu.”
“Dan kamu ikut-ikutan, padahal kamu tidak suka puasa, tidak suka salat?”
“Siapa juga yang berani, Cak…”
“Itulah masalahmu. Mestinya kamu berterus terang pada Allah bahwa kamu tidak suka salat dan tidak suka puasa, tapi kamu siap dan ikhlas melakukan sesuatu yang kamu tidak suka itu sehingga derajatmu tinggi di hadapan Allah. Kalau kamu suka, ya tidak tinggi derajatmu, Mat.”
“Waduh, Cak…”
“Waduh kenapa? Aku tanya ke kamu: orang suka, orang senang, terus melakukan atau menjalani yang disenangi atau disukai, apa hebatnya?”
“Ya ndak ada, Cak Biasa saja.”
“Jadi, benar kamu suka puasa?”
“Ya sudah, saya akan berterus terang pada Allah bahwa saya tidak suka, tapi saya akan menaati perintahnya dan akan melakukannya dengan ikhlas.”
“Begitu dong. Jangan pura-pura terus.”
“Sampeyan besok puasa kan, Cak?”
“Apa aku harus bilang dan pamer padamu kalau aku akan berpuasa?”
“Ya…salah lagi… Saya mau melanjutkan menyapu dulu ya, Cak….”
Quote:
2.Menghitung Berak Dan Kencing.
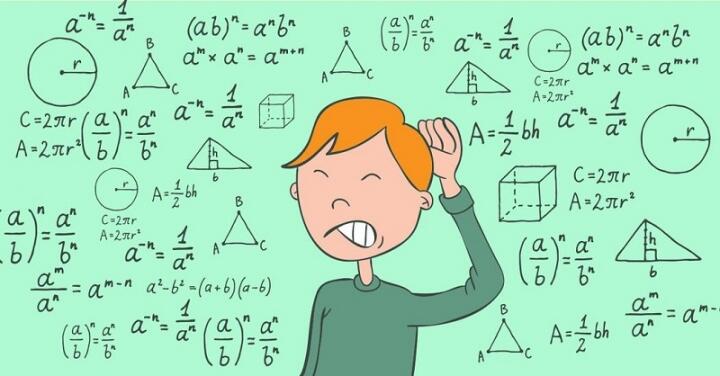
“Assalamualaikum, Cak.”
“Waalaikumsalam. Eh, Mat… enak betul rawonmu ini.”
“Romlah yang masak, Cak.”
“Gadis itu memang pintar masak, Mat. Kamu pandai membesarkan anak.”
“Iya, Cak, saya tahu, tapi saya mau tanya, maksud sampeyan bilang saya harus ikhlas itu apa ya?”
“Tadi kamu ngasih apa aja ya, Mat?”
“Bubur kacang ijo, rawon serantang lengkap dengan nasi, telur asin, kerupuk udang, sambal taoge. Ada teh hangat juga.”
“Wuih, ingat banget kamu, Mat?”
“Saya melihat sendiri Romlah memasukkannya ke rantang, jadi saya ingat, Cak.”
“Terima kasih ya, mat. Seminggu lalu kalau tak salah kamu juga ngasih aku… apa ya?”
“Oh yang itu, beras dua kilo, Cak. Dua minggu sebelumnya, saya ngasih sampean sarung. Sebulan yang lalu saya ngasih sampeyan peci.”
“Iya ya… Tapi, kamu pasti ikhlas kan, Mat?”
“Ya ikhlaslah, Cak. Masak ndak. Maka itu saya mau tanya, maksud sampean soal ikhlas itu apa?”
“Ikhlas kok ditanya, Mat.”
“Saya hanya ingin tahu…”
“Lah menurutmu ikhlas itu apa?”
“Berbuat atau melakukan sesuatu karena Allah, dengan Allah, hanya untuk Allah, Cak.”
“Semua untuk Allah itu apa?”
“Ya kalau begini terus sampeyan saja deh yang ngasih tahu: ikhlas itu apa?”
“Sebelum ke sini, kamu kencing dulu ndak, Mat?”
“Loh sampeyan kok malah nanya soal kencing, Cak?”
“Kan kita sama, Cuma tanya.”
“Iya, tapi apa hubungannya kencing dengan ikhlas, Cak?”
“Aku tanya kamu tanya. Kamu jawab saja. Kalau ndak mau, ya ndak apa-apa juga.”
“Sebelum ke rumah sampeyan, saya tidak kencing. Sudah? Itu saja?”
“Kalau hari ini, kamu kencing dan berak berapa kali, Mat?”
“Sehari ini saya belum berak, Cak. Kencing mungkin tiga atau empat kali.”
“Kemarin?”
“Berak sekali. Kencing…? Ya… kira-kira samalah, Cak, dengan hari ini, tiga atau empat kali…”
“Seminggu yang lalu?”
“Ya ndak ingat, Cak…”
“Sebulan yang lalu? Setahun yang lalu? Sejak mulai kamu lahir kamu ingat, berapa kali kamu berak dan kencing?”
“Sampeyan juga ndak ingat toh, Cak?”
“Seperti itulah ikhlas.”
“Maksudnya?”
“Amal perbuatanmu yang tidak pernah diingat-ingat.”
“Kencing dan berak itu amal toh, Cak?”
“Menurutmu apa?”
“Kan saya yang ditanya, kenapa ditanya?”
“Kencing dan berak itu amalmu, Mat. Kamu mengeluarkan sesuatu dari badanmu dengan tidak menahan-nahannya dan segera melupakannya. Tidak mengingat-ingat bau, warna, dan bentuknya seperti apa. Kamu menganggap kencing dan berak tidak penting, meskipun mengeluarkan sesuatu yang sangat penting bagi lambung atau ginjalmu. Buat peredaran darahmu. Untuk kesehatanmu.”
“Jadi kalau masih ingat, berarti ndak ikhlas, Cak?”
“Hanya Allah yang tahu.”
“Astaghfirullah… maafkan saya, Cak…”
“Kenapa minta maaf ke aku, Mat?”
“Saya mau pamit dulu…”
“Kok buru-buru?”
“Sudah kebelet, Cak…”
Spoiler for Menghitung Berak Dan Kencing.:
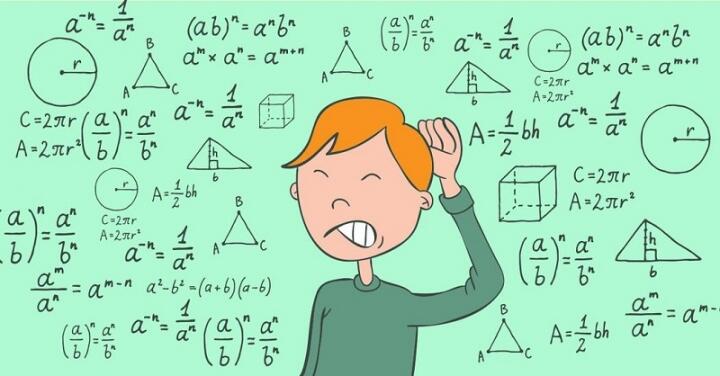
“Assalamualaikum, Cak.”
“Waalaikumsalam. Eh, Mat… enak betul rawonmu ini.”
“Romlah yang masak, Cak.”
“Gadis itu memang pintar masak, Mat. Kamu pandai membesarkan anak.”
“Iya, Cak, saya tahu, tapi saya mau tanya, maksud sampeyan bilang saya harus ikhlas itu apa ya?”
“Tadi kamu ngasih apa aja ya, Mat?”
“Bubur kacang ijo, rawon serantang lengkap dengan nasi, telur asin, kerupuk udang, sambal taoge. Ada teh hangat juga.”
“Wuih, ingat banget kamu, Mat?”
“Saya melihat sendiri Romlah memasukkannya ke rantang, jadi saya ingat, Cak.”
“Terima kasih ya, mat. Seminggu lalu kalau tak salah kamu juga ngasih aku… apa ya?”
“Oh yang itu, beras dua kilo, Cak. Dua minggu sebelumnya, saya ngasih sampean sarung. Sebulan yang lalu saya ngasih sampeyan peci.”
“Iya ya… Tapi, kamu pasti ikhlas kan, Mat?”
“Ya ikhlaslah, Cak. Masak ndak. Maka itu saya mau tanya, maksud sampean soal ikhlas itu apa?”
“Ikhlas kok ditanya, Mat.”
“Saya hanya ingin tahu…”
“Lah menurutmu ikhlas itu apa?”
“Berbuat atau melakukan sesuatu karena Allah, dengan Allah, hanya untuk Allah, Cak.”
“Semua untuk Allah itu apa?”
“Ya kalau begini terus sampeyan saja deh yang ngasih tahu: ikhlas itu apa?”
“Sebelum ke sini, kamu kencing dulu ndak, Mat?”
“Loh sampeyan kok malah nanya soal kencing, Cak?”
“Kan kita sama, Cuma tanya.”
“Iya, tapi apa hubungannya kencing dengan ikhlas, Cak?”
“Aku tanya kamu tanya. Kamu jawab saja. Kalau ndak mau, ya ndak apa-apa juga.”
“Sebelum ke rumah sampeyan, saya tidak kencing. Sudah? Itu saja?”
“Kalau hari ini, kamu kencing dan berak berapa kali, Mat?”
“Sehari ini saya belum berak, Cak. Kencing mungkin tiga atau empat kali.”
“Kemarin?”
“Berak sekali. Kencing…? Ya… kira-kira samalah, Cak, dengan hari ini, tiga atau empat kali…”
“Seminggu yang lalu?”
“Ya ndak ingat, Cak…”
“Sebulan yang lalu? Setahun yang lalu? Sejak mulai kamu lahir kamu ingat, berapa kali kamu berak dan kencing?”
“Sampeyan juga ndak ingat toh, Cak?”
“Seperti itulah ikhlas.”
“Maksudnya?”
“Amal perbuatanmu yang tidak pernah diingat-ingat.”
“Kencing dan berak itu amal toh, Cak?”
“Menurutmu apa?”
“Kan saya yang ditanya, kenapa ditanya?”
“Kencing dan berak itu amalmu, Mat. Kamu mengeluarkan sesuatu dari badanmu dengan tidak menahan-nahannya dan segera melupakannya. Tidak mengingat-ingat bau, warna, dan bentuknya seperti apa. Kamu menganggap kencing dan berak tidak penting, meskipun mengeluarkan sesuatu yang sangat penting bagi lambung atau ginjalmu. Buat peredaran darahmu. Untuk kesehatanmu.”
“Jadi kalau masih ingat, berarti ndak ikhlas, Cak?”
“Hanya Allah yang tahu.”
“Astaghfirullah… maafkan saya, Cak…”
“Kenapa minta maaf ke aku, Mat?”
“Saya mau pamit dulu…”
“Kok buru-buru?”
“Sudah kebelet, Cak…”
Quote:
3.Zakat Dan Sekantong Taek.

“Saya diminta panitia agar mengundang sampean, Cak…”
“Untuk apa ya, Mat?”
“Ceramah lima menit, Cak.”
“Aku mau tiga menit saja.”
Mengawali dengan puji-pujian, Cak Dlahom selanjutnya mempersilakan semua yang hadir untuk bertanya. Orang-orang bingung. Penceramah yang lain mestinya sudah berbusa-busa memberi tausiah, tapi Cak Dlahom malah meminta Jemaah bertanya.
“Silahkan bertanya. Tentang apa saja.”
“Menurut sampean, zakat itu apa, Cak?” Seorang anak muda yang duduk dekat pintu masjid mencoba memulai.
“Zakat itu kewajiban dari syariat.”
“Saya tahu, Cak. Maksud saya, apa zakat itu?”
“Zakat itu kotoran. Sama dengan sedekah, infak, dan sebagainya. Kita semua harus membuangnya. Jangan eman-eman.”
“Maksudnya, Cak?”
“Zakat wajib dikeluarkan. Untuk membersihkan harta. Mmebersihkan hati kita.”
“Kalau zakat seperti zakat fitrah kan ada ketentuannya, Cak.”
“Iya tentu. Orang-orang mengeluarkan zakat minimal harus sesuai dengan yang sudah ditentukan, tapi itulah tabiat orang kikir. Mereka hanya mau yang minimal.”
“Kalau kemampuannya hanya sebatas yang ditentukan bagaimana, Cak?”
“Tidak apa-apa, tapi zakat, sedekah, dan sebagainya adalah kotoran. Pernah berak? Pernah kencing?”
“Pernah, Cak…”
“Pernah eman-eman mencicil berak dan kencing? Membuangnya sedikit-sedikit?”
“Ya ndak, Cak. Kalau kotoran disimpan malah jadi penyakit…”
“Kamu mulai pintar. Itulah berderma. Manusia begitu sayang untuk berzakat, bersedekah, membayar infak. Kalau pun dilakukan, dikeluarkannya sedikit. Memberi sesuatu dihitung-hitung. Atau dipilih dan diambilnya yang jelek-jelek. Yang sudah tidak terpakai atau yang paling minimalis. Disayang-sayang hartanya. Padahal semua itu adalah kotoran yang bisa membuat sakit.”
“Pilihannya apa, Cak?” Seorang ibu menimpali.
“Pilihannya: menyimpan terus kotoran atau membuangnya tanpa takut. Tidakkah mustahil kita menyimpan dan hidup dengan kotoran?”
“Baiklah, Cak. Kami insya Allah sudah mengerti penjelasan sampean, tapi saya kok merasa sampean itu sombong, Cak? Selalu merasa lebih tahu dan pintar dari kami?” Terdengar suara berat seorang laki-laki. Dialah Pak lurah.
“Yang merasa itu kan sampean, Pak lurah, bukan saya? Jadi itu urusan sampean, bukan urusan saya. Tapi kita semua termasuk sampean sebetulnya hanya sekantong taek.”
“Loh, loh, hati-hati kalau ngomong, Cak…”
“Di usus sampean, di lambung sampean ada apa, Pak Lurah, selain taek? Sama dengan yang tersimpan di perut manusia lain. Tak ada bedanya. Kita semua yang mengaku ganteng atau cantik setiap hari ya diganduli sekantong taek. Yang miskin dan yang kaya juga membawa sekantong taek. Kita semua Cuma sekantong taek. Lalu apa yang mau disombongkan, lah wong kita ini hanya taek?”
“Bagaimana sampean tahu kita ini hanya taek…?”
“Pak Lurah masuklah ke WC. Pandangi diri sampean saat buang hajat di sana. Lihatlah, Sebagian dari yang sampean puja-puji sebagai milik sampean, yang sampean sayang-sayang, ternyata hanya taek. Bau. Membuat jijik.”
Spoiler for Zakat Dan Sekantong Taek.:

“Saya diminta panitia agar mengundang sampean, Cak…”
“Untuk apa ya, Mat?”
“Ceramah lima menit, Cak.”
“Aku mau tiga menit saja.”
Mengawali dengan puji-pujian, Cak Dlahom selanjutnya mempersilakan semua yang hadir untuk bertanya. Orang-orang bingung. Penceramah yang lain mestinya sudah berbusa-busa memberi tausiah, tapi Cak Dlahom malah meminta Jemaah bertanya.
“Silahkan bertanya. Tentang apa saja.”
“Menurut sampean, zakat itu apa, Cak?” Seorang anak muda yang duduk dekat pintu masjid mencoba memulai.
“Zakat itu kewajiban dari syariat.”
“Saya tahu, Cak. Maksud saya, apa zakat itu?”
“Zakat itu kotoran. Sama dengan sedekah, infak, dan sebagainya. Kita semua harus membuangnya. Jangan eman-eman.”
“Maksudnya, Cak?”
“Zakat wajib dikeluarkan. Untuk membersihkan harta. Mmebersihkan hati kita.”
“Kalau zakat seperti zakat fitrah kan ada ketentuannya, Cak.”
“Iya tentu. Orang-orang mengeluarkan zakat minimal harus sesuai dengan yang sudah ditentukan, tapi itulah tabiat orang kikir. Mereka hanya mau yang minimal.”
“Kalau kemampuannya hanya sebatas yang ditentukan bagaimana, Cak?”
“Tidak apa-apa, tapi zakat, sedekah, dan sebagainya adalah kotoran. Pernah berak? Pernah kencing?”
“Pernah, Cak…”
“Pernah eman-eman mencicil berak dan kencing? Membuangnya sedikit-sedikit?”
“Ya ndak, Cak. Kalau kotoran disimpan malah jadi penyakit…”
“Kamu mulai pintar. Itulah berderma. Manusia begitu sayang untuk berzakat, bersedekah, membayar infak. Kalau pun dilakukan, dikeluarkannya sedikit. Memberi sesuatu dihitung-hitung. Atau dipilih dan diambilnya yang jelek-jelek. Yang sudah tidak terpakai atau yang paling minimalis. Disayang-sayang hartanya. Padahal semua itu adalah kotoran yang bisa membuat sakit.”
“Pilihannya apa, Cak?” Seorang ibu menimpali.
“Pilihannya: menyimpan terus kotoran atau membuangnya tanpa takut. Tidakkah mustahil kita menyimpan dan hidup dengan kotoran?”
“Baiklah, Cak. Kami insya Allah sudah mengerti penjelasan sampean, tapi saya kok merasa sampean itu sombong, Cak? Selalu merasa lebih tahu dan pintar dari kami?” Terdengar suara berat seorang laki-laki. Dialah Pak lurah.
“Yang merasa itu kan sampean, Pak lurah, bukan saya? Jadi itu urusan sampean, bukan urusan saya. Tapi kita semua termasuk sampean sebetulnya hanya sekantong taek.”
“Loh, loh, hati-hati kalau ngomong, Cak…”
“Di usus sampean, di lambung sampean ada apa, Pak Lurah, selain taek? Sama dengan yang tersimpan di perut manusia lain. Tak ada bedanya. Kita semua yang mengaku ganteng atau cantik setiap hari ya diganduli sekantong taek. Yang miskin dan yang kaya juga membawa sekantong taek. Kita semua Cuma sekantong taek. Lalu apa yang mau disombongkan, lah wong kita ini hanya taek?”
“Bagaimana sampean tahu kita ini hanya taek…?”
“Pak Lurah masuklah ke WC. Pandangi diri sampean saat buang hajat di sana. Lihatlah, Sebagian dari yang sampean puja-puji sebagai milik sampean, yang sampean sayang-sayang, ternyata hanya taek. Bau. Membuat jijik.”
Quote:
4.Kata Siapa Kamu Muslim?

Dan percakapan keduanya tentang spanduk Ramadan di masjid itu belum selesai Ketika seorang laki-laki mendatangi mereka. Dilihat dari pakaian dan penampilannya , laki-laki itu tampaknya petugas dari kantor desa. Dan benar, laki-laki itu adalah Marja yang tinggal di kampung sebelah.
Orang-orang mengenalnya sebagai penceramah, selain bekerja di kantor desa. Dia sering diundang untuk berceramah di masjid-masjid atau pengajian-pengajian. Marja memang jebolan pesantren. Pak RT mempersilakan Marja duduk di teras masjid.
“Tumben, Pak Marja, ada apa?”
“Mau antar surat dari kantor desa, Pak RT.”
“Surat apa?”
“Pemberitahuan, Pak RT, agar masjid berhati-hati mengundang penceramah selama Ramadan.”
“Waduh kok keadaan desa kita seperti gawat?”
“Memang gawat, Pak RT. Sekarang ini banyak aliran-aliran yang menyesatkan…”
Sedang Pak RT dan Marja bercakap-cakap dan orang-orang mendengarkan percakapan mereka. Cak Dlahom tiba-tiba cekikikan. Orang-orang menoleh ke arah Cak Dlahom. Mat Piti juga menoleh, tapi dia segera mencoba menenangkan.
“Ada apa , Cak? Kenapa?”
“Ndak apa-apa, mat. Hanya heran, urusan ceramah di masjid kok menjadi urusan kantor desa.”
“Ya kita harus memberikan pencerahan yang benar pada umat, Cak. Agar umat tidak mudah dihasut. Tidak mudah diadu domba.” Marja mencoba berargumen. Wajahnya serius. Dia petugas yang serius tampaknya.
“Marja…Marja…”
“Di mana salahnya, Cak?”
“Tak ada yang salah, Marja.”
“Kenapa sampean menganggap remeh soal aliran-aliran itu?”
“Apa kamu mengira umat itu lebih bodoh, lalu pemerintah dan penceramah sepertimu lebih pintar?”
“Bukan begitu, Cak. Ini kan pencegahan. Agar berhati-hati saja. Agar waspada.”
“Sebagai penceramah, apa kamu merasa tidak beraliran? Tidak berkelompok-kelompok dan merasa kelompok dan aliranmu yang paling benar? Yang paling rahmatan lil alamin?”
“Waduh, sampean jangan sembarangan, Cak…”
“Aku memang sembarangan, Marja, sebab banyak penceramah sepertimu sering berceramah agar berhati-hati terhadap penceramah yang isi ceramahnya sesat-menyesatkan, berhati-hati dengan aliran ini dan aliran itu, lalu merasa diri mereka tidak sesat. Merasa paling benar. Merasa tidak mengagungkan kelompoknya.”
“Ini imbauan dari kantor desa, Cak. Bukan dari saya. Dan kalau sampean tak paham ilmu agama, ndak usah nyeramahin orang soal agama.”
“Hahaha…” Tawa Cak Dlahom pecah. Orang-orang terkejut mendengar tawa keras itu. Baru kali ini Cak Dlahom ngakak. Dia biasanya hanya cekikikan. Mat Piti mulai salah tingkah. Angin sore terasa hangat.
“Marja, jangan lagi ilmu agama yang aku punya, mengaku muslim pun aku tidak berani.”
“Maksud sampean gimana, Cak?”
“Benar kamu muslim, Marja?”
“Saya muslim…”
“Muslim kata siapa, Marja?”
“Loh saya memang muslim. Ndak tahu kalau sampean…”
“Itu kan katamu, Marja. Pengakuanmu. Padahal muslim atau tidak diriku atau dirimu, hanya Allah yang tahu dan berhak menilai. Bukan manusia. Bukan diaku-aku oleh manusia.”
Orang-orang semakin diam. Sebagian menunduk. Sebagian hanya tolah-toleh. Wajah Marja memerah. Pak RT kebingungan. Sore menjelang senja.
“Saya membaca syahadat, mendirikan salat…”
“Ya bagus, tapi untuk apa kamu salat, Marja?”
“Agar saya tidak sesat…”
“Dan kamu tahu siapa yang kamu sembah dalam salatmu?”
“ya saya menyembah Allah…”
“Bagaimana kamu tahu kamu menyembah Allah? Bagaimana kalau yang kamu sembah dalam salat ternyata hanya dirimu? Hanya kesombonganmu? Hanya nafsumu?”
“Maksudnya apa nih, Cak?”
“Kamu tahu yang aku maksudkan, Marja: jangan salat kalau tidak tahu siapa yang disembah.”
“Waduh, benar kata orang-orang, sampean memang tidak benar. Hati-hati, Cak, sampean bisa dicap sesat.”
“Yang begini ini, Pak RT, termasuk yang harus diwaspadai…”
Pak RT semakin kebingungan. Dia berinisiatif menengahi.
“Begini, Pak Marja, Cak Dlahom, kita ngobrol-ngobrol yang ringan saja. Sudah menjelang buka…”
“Ndak apa-apa, Pak RT. Benar Marja, saya memang sesat. Karena itu Allah mewajibkan saya untuk selalu membaca ‘tunjukkanlah aku jalan yang lurus’ setiap kali saya salat. Tujuh belas kali sehari semalam."
Orang-orang tetap diam, kecuali Busairi. Dia segera berdiri sambal cekikikan bergumam “Hehehe, Cak Dlahom salat…”
Spoiler for Kata Siapa Kamu Muslim?:

Dan percakapan keduanya tentang spanduk Ramadan di masjid itu belum selesai Ketika seorang laki-laki mendatangi mereka. Dilihat dari pakaian dan penampilannya , laki-laki itu tampaknya petugas dari kantor desa. Dan benar, laki-laki itu adalah Marja yang tinggal di kampung sebelah.
Orang-orang mengenalnya sebagai penceramah, selain bekerja di kantor desa. Dia sering diundang untuk berceramah di masjid-masjid atau pengajian-pengajian. Marja memang jebolan pesantren. Pak RT mempersilakan Marja duduk di teras masjid.
“Tumben, Pak Marja, ada apa?”
“Mau antar surat dari kantor desa, Pak RT.”
“Surat apa?”
“Pemberitahuan, Pak RT, agar masjid berhati-hati mengundang penceramah selama Ramadan.”
“Waduh kok keadaan desa kita seperti gawat?”
“Memang gawat, Pak RT. Sekarang ini banyak aliran-aliran yang menyesatkan…”
Sedang Pak RT dan Marja bercakap-cakap dan orang-orang mendengarkan percakapan mereka. Cak Dlahom tiba-tiba cekikikan. Orang-orang menoleh ke arah Cak Dlahom. Mat Piti juga menoleh, tapi dia segera mencoba menenangkan.
“Ada apa , Cak? Kenapa?”
“Ndak apa-apa, mat. Hanya heran, urusan ceramah di masjid kok menjadi urusan kantor desa.”
“Ya kita harus memberikan pencerahan yang benar pada umat, Cak. Agar umat tidak mudah dihasut. Tidak mudah diadu domba.” Marja mencoba berargumen. Wajahnya serius. Dia petugas yang serius tampaknya.
“Marja…Marja…”
“Di mana salahnya, Cak?”
“Tak ada yang salah, Marja.”
“Kenapa sampean menganggap remeh soal aliran-aliran itu?”
“Apa kamu mengira umat itu lebih bodoh, lalu pemerintah dan penceramah sepertimu lebih pintar?”
“Bukan begitu, Cak. Ini kan pencegahan. Agar berhati-hati saja. Agar waspada.”
“Sebagai penceramah, apa kamu merasa tidak beraliran? Tidak berkelompok-kelompok dan merasa kelompok dan aliranmu yang paling benar? Yang paling rahmatan lil alamin?”
“Waduh, sampean jangan sembarangan, Cak…”
“Aku memang sembarangan, Marja, sebab banyak penceramah sepertimu sering berceramah agar berhati-hati terhadap penceramah yang isi ceramahnya sesat-menyesatkan, berhati-hati dengan aliran ini dan aliran itu, lalu merasa diri mereka tidak sesat. Merasa paling benar. Merasa tidak mengagungkan kelompoknya.”
“Ini imbauan dari kantor desa, Cak. Bukan dari saya. Dan kalau sampean tak paham ilmu agama, ndak usah nyeramahin orang soal agama.”
“Hahaha…” Tawa Cak Dlahom pecah. Orang-orang terkejut mendengar tawa keras itu. Baru kali ini Cak Dlahom ngakak. Dia biasanya hanya cekikikan. Mat Piti mulai salah tingkah. Angin sore terasa hangat.
“Marja, jangan lagi ilmu agama yang aku punya, mengaku muslim pun aku tidak berani.”
“Maksud sampean gimana, Cak?”
“Benar kamu muslim, Marja?”
“Saya muslim…”
“Muslim kata siapa, Marja?”
“Loh saya memang muslim. Ndak tahu kalau sampean…”
“Itu kan katamu, Marja. Pengakuanmu. Padahal muslim atau tidak diriku atau dirimu, hanya Allah yang tahu dan berhak menilai. Bukan manusia. Bukan diaku-aku oleh manusia.”
Orang-orang semakin diam. Sebagian menunduk. Sebagian hanya tolah-toleh. Wajah Marja memerah. Pak RT kebingungan. Sore menjelang senja.
“Saya membaca syahadat, mendirikan salat…”
“Ya bagus, tapi untuk apa kamu salat, Marja?”
“Agar saya tidak sesat…”
“Dan kamu tahu siapa yang kamu sembah dalam salatmu?”
“ya saya menyembah Allah…”
“Bagaimana kamu tahu kamu menyembah Allah? Bagaimana kalau yang kamu sembah dalam salat ternyata hanya dirimu? Hanya kesombonganmu? Hanya nafsumu?”
“Maksudnya apa nih, Cak?”
“Kamu tahu yang aku maksudkan, Marja: jangan salat kalau tidak tahu siapa yang disembah.”
“Waduh, benar kata orang-orang, sampean memang tidak benar. Hati-hati, Cak, sampean bisa dicap sesat.”
“Yang begini ini, Pak RT, termasuk yang harus diwaspadai…”
Pak RT semakin kebingungan. Dia berinisiatif menengahi.
“Begini, Pak Marja, Cak Dlahom, kita ngobrol-ngobrol yang ringan saja. Sudah menjelang buka…”
“Ndak apa-apa, Pak RT. Benar Marja, saya memang sesat. Karena itu Allah mewajibkan saya untuk selalu membaca ‘tunjukkanlah aku jalan yang lurus’ setiap kali saya salat. Tujuh belas kali sehari semalam."
Orang-orang tetap diam, kecuali Busairi. Dia segera berdiri sambal cekikikan bergumam “Hehehe, Cak Dlahom salat…”
Quote:
5.Disengat Tawon.

“Kenapa tawon-tawon itu bisa mengeroyok sampean, Cak?”
Mat Piti membuka pembicaraan. Gus Mut menyuap kolak. Nody dan Romlah ikut bergabung ke teras belakang. Cak Dlahom menyalakan kreteknya.
“Mereka ingin jalan-jalan, Mat.”
“Sampean ada-ada saja, Cak. Tawon kok ingin jalan-jalan?”
“Loh kamu kira hanya manusia yang ingin jalan-jalan?”
“Maksud saya, bagaimana sampean tahu tawon-tawon itu ingin -jalan-jalan?”
“Aku tidak tahu, Mat. Aku hanya tahu mereka mengikutiku. Itu saja.”
“Lalu kenapa sampean menolak ditolong?”
“Mat, tawon-tawon itu tidak menggangguku dan aku tidak mengganggu mereka.”
“Iya, Cak, tapi tawon-tawon itu berbahaya. Bisa mematikan. Orang-orang itu mau menolong sampean.”
“Mat, banyak orang ketika melihat orang susah, melihat orang melarat, melihat orang menderita, lalu ingin menolong. Ingin membantu.”
“Itu kewajiban manusia, Cak.”
“Betul, Mat. Aku menghargai mereka. Masalahnya, bagaimana mereka mau menolong sementara mereka tidak mampu menolong diri mereka.”
“Maksudnya bagaimana, Cak?”
“Banyak dari mereka yang ingin menolong bukan karena benar ingin menolong. Mereka menolong hanya karena rasa iba. Rasa tidak enak. Rasa ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, tapi alpa melihat ke dalam diri mereka. Sibuk menilai orang lain dan lupa menilai kekurangan diri sendiri. Orang-orang semacam itulah yang mestinya perlu ditolong.”
Mat Piti manggut-manggut. Gus Mut meneruskan menyuap kolak. Romlah mengelus-elus perutnya. Nody menyeruput kopi. Cak Dlahom meneruskan penjelasannya.
“Kasih sayang Allah itu untuk seluruh alam. Untuk seluruh makhluk, tapi manusia sering mengingkarinya. Ketika mereka sakit, mereka berdoa meminta untuk disembuhkan. Ketika mereka melarat, mereka berdoa agar diberi kesejahteraan. Ketika kemarau mereka berdoa meminta hujan. Ketika hujan mereka lari menghindar. Doa mereka penuh nafsu. Mereka berdoa karena nafsu.”
“Padahal Ketika mereka sakit, Ketika mereka melarat, Ketika diberi kemarau, Ketika diberi hujan, boleh jadi itulah waktu dan kesempatan bagi mereka untuk mendekatkan diri mereka pada Allah. Tapi, mereka tidak paham. Mereka menganggap musibah sebagai cobaan. Mereka tidak menyadari, musibah sebagai anugerah.”
Cak Dlahom mengisap dalam-dalam kreteknya. “Anugerah, Cak? Mat Piti membuka suara.
“Iya, Mat, musibah itu anugerah bagi orang-orang yang mengerti. Ujian dan cobaan yang paling berat adalah Ketika kamu berlimpah nikmat dan diberi kecukupan dalam segala urusan dunia. Bukan pada saat kamu diuji dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan…”
“Seperti saya ini ya, Cak?”
Gus Mut memotong. Mat Piti agak kaget. Nody juga terheran-heran.
“Maksudmu, Gus?”
“Mulut saya kan terus menganga, Cak. Jadi saya harus bersyukur karena diberi anugerah mulut yang terus menganga. Begitu, kan, maksudnya?”
Cak Dlahom cekikikan. Romlah mesam-mesem.
“Ya ya, semacam itu, Gus. Hidup ini hanya harus dijalani. Kalau kita takut pada ujian dan cobaan, menghindar dari persoalan, kita mestinya tak perlu hidup. Musibah atau ujian apa pun mestinya bisa mengantar seseorang menjadi semakin dekat dengan penciptanya. Lewat musibah, mereka seharusnya menyadari, diri mereka fakir. Tidak punya apa-apa. Tidak punya daya kekuatan apa pun di hadapan Allah.”
“Mereka mungkin punya kekayaan di dunia ini, tapi mereka fakir. Mereka mungkin bisa beribadah tapi fakir. Mereka mungkin punya kekuasaan tapi daif. Mereka semua tidak punya apa-apa dan tak mampu melakukan apa-apa di hadapan Allah.”
“Jadi kita semua ini fakir ya, Cak?” Gus Mut Kembali menyahut.
“Betul, Gus. Tak satupun dari kita yang lebih unggul dari yang lainnya. Tak seorang pun. Karena itu jangan sombong. Jangan takabur. Jangan jemawa merasa diri lebih dari yang lain.”
“Tapi, saya merasa punya keunggulan, Cak.”
Mat Piti geleng-geleng mendengar Gus Mut terus menyahut. Cak Dlahom cekikikan.
“Kok sampai tertawa, Cak?”
“Kira-kira aku tahu yang kamu maksud, Gus.”
“Apa keunggulan saya, Cak?’
“Bentuk mulutmu.”
Mat Piti dan Nody tertawa. Romlah yang semula hanya mesam-mesem kali ini tak kuasa untuk tidak ikut tertawa.
Spoiler for Disengat Tawon.:

“Kenapa tawon-tawon itu bisa mengeroyok sampean, Cak?”
Mat Piti membuka pembicaraan. Gus Mut menyuap kolak. Nody dan Romlah ikut bergabung ke teras belakang. Cak Dlahom menyalakan kreteknya.
“Mereka ingin jalan-jalan, Mat.”
“Sampean ada-ada saja, Cak. Tawon kok ingin jalan-jalan?”
“Loh kamu kira hanya manusia yang ingin jalan-jalan?”
“Maksud saya, bagaimana sampean tahu tawon-tawon itu ingin -jalan-jalan?”
“Aku tidak tahu, Mat. Aku hanya tahu mereka mengikutiku. Itu saja.”
“Lalu kenapa sampean menolak ditolong?”
“Mat, tawon-tawon itu tidak menggangguku dan aku tidak mengganggu mereka.”
“Iya, Cak, tapi tawon-tawon itu berbahaya. Bisa mematikan. Orang-orang itu mau menolong sampean.”
“Mat, banyak orang ketika melihat orang susah, melihat orang melarat, melihat orang menderita, lalu ingin menolong. Ingin membantu.”
“Itu kewajiban manusia, Cak.”
“Betul, Mat. Aku menghargai mereka. Masalahnya, bagaimana mereka mau menolong sementara mereka tidak mampu menolong diri mereka.”
“Maksudnya bagaimana, Cak?”
“Banyak dari mereka yang ingin menolong bukan karena benar ingin menolong. Mereka menolong hanya karena rasa iba. Rasa tidak enak. Rasa ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, tapi alpa melihat ke dalam diri mereka. Sibuk menilai orang lain dan lupa menilai kekurangan diri sendiri. Orang-orang semacam itulah yang mestinya perlu ditolong.”
Mat Piti manggut-manggut. Gus Mut meneruskan menyuap kolak. Romlah mengelus-elus perutnya. Nody menyeruput kopi. Cak Dlahom meneruskan penjelasannya.
“Kasih sayang Allah itu untuk seluruh alam. Untuk seluruh makhluk, tapi manusia sering mengingkarinya. Ketika mereka sakit, mereka berdoa meminta untuk disembuhkan. Ketika mereka melarat, mereka berdoa agar diberi kesejahteraan. Ketika kemarau mereka berdoa meminta hujan. Ketika hujan mereka lari menghindar. Doa mereka penuh nafsu. Mereka berdoa karena nafsu.”
“Padahal Ketika mereka sakit, Ketika mereka melarat, Ketika diberi kemarau, Ketika diberi hujan, boleh jadi itulah waktu dan kesempatan bagi mereka untuk mendekatkan diri mereka pada Allah. Tapi, mereka tidak paham. Mereka menganggap musibah sebagai cobaan. Mereka tidak menyadari, musibah sebagai anugerah.”
Cak Dlahom mengisap dalam-dalam kreteknya. “Anugerah, Cak? Mat Piti membuka suara.
“Iya, Mat, musibah itu anugerah bagi orang-orang yang mengerti. Ujian dan cobaan yang paling berat adalah Ketika kamu berlimpah nikmat dan diberi kecukupan dalam segala urusan dunia. Bukan pada saat kamu diuji dengan berbagai kesulitan dan keterbatasan…”
“Seperti saya ini ya, Cak?”
Gus Mut memotong. Mat Piti agak kaget. Nody juga terheran-heran.
“Maksudmu, Gus?”
“Mulut saya kan terus menganga, Cak. Jadi saya harus bersyukur karena diberi anugerah mulut yang terus menganga. Begitu, kan, maksudnya?”
Cak Dlahom cekikikan. Romlah mesam-mesem.
“Ya ya, semacam itu, Gus. Hidup ini hanya harus dijalani. Kalau kita takut pada ujian dan cobaan, menghindar dari persoalan, kita mestinya tak perlu hidup. Musibah atau ujian apa pun mestinya bisa mengantar seseorang menjadi semakin dekat dengan penciptanya. Lewat musibah, mereka seharusnya menyadari, diri mereka fakir. Tidak punya apa-apa. Tidak punya daya kekuatan apa pun di hadapan Allah.”
“Mereka mungkin punya kekayaan di dunia ini, tapi mereka fakir. Mereka mungkin bisa beribadah tapi fakir. Mereka mungkin punya kekuasaan tapi daif. Mereka semua tidak punya apa-apa dan tak mampu melakukan apa-apa di hadapan Allah.”
“Jadi kita semua ini fakir ya, Cak?” Gus Mut Kembali menyahut.
“Betul, Gus. Tak satupun dari kita yang lebih unggul dari yang lainnya. Tak seorang pun. Karena itu jangan sombong. Jangan takabur. Jangan jemawa merasa diri lebih dari yang lain.”
“Tapi, saya merasa punya keunggulan, Cak.”
Mat Piti geleng-geleng mendengar Gus Mut terus menyahut. Cak Dlahom cekikikan.
“Kok sampai tertawa, Cak?”
“Kira-kira aku tahu yang kamu maksud, Gus.”
“Apa keunggulan saya, Cak?’
“Bentuk mulutmu.”
Mat Piti dan Nody tertawa. Romlah yang semula hanya mesam-mesem kali ini tak kuasa untuk tidak ikut tertawa.
Quote:
Sekian dari TS, semoga Thread sederhana ane ini bisa jadi Inpirasi dan bermanfaat bagi agan2 semua ya, ane tunggu banget komengtarnya gan , salam dari ane gan.
, salam dari ane gan.
Akhir Kata:

 , salam dari ane gan.
, salam dari ane gan.Akhir Kata:

Diubah oleh nohopemiracle 29-04-2020 21:39
d0dittt dan 233 lainnya memberi reputasi
234
5.1K
Kutip
223
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan