- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- The Lounge
aku bukan orang INDONESIA tapi aku cinta INDONESIA
TS
rckbty
aku bukan orang INDONESIA tapi aku cinta INDONESIA
terima kasih buat agan agan semuanya sama mimin dan momod
Sebelum di baca mohon di

Dan jika berkenang ane minta

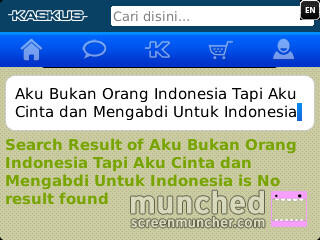

Sedih rasanya jika kita membaca judul di atas tersebut termasuk saya sendiri sangat sedih
Saya mengambil satu kutipan dari presiden pertama kita bapak presiden ir.soekarno
"Jangan tanya apa yang negara ini bisa berikan padamu?, tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan pada negara ini? Seberapa besar cinta kita pada Indonesia? Apa yang sudah kita berikan pada Ibu Pertiwi? jawabanya ada pada diri kita masing-masing, dari sekian banyak orang yang tanpa pamrih mengabdikan dirinya untuk negeri ini, inilah di antara mereka, mereka bukan orang Indonesia tapi Cinta dan pengabdiannya di sebagian hidupnya untuk Indonesia. Orang-orang inilah yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi kita sebagai warga indonesia.

Nama aslinya Andre Graff, tetapi masyarakat Sumba memanggilnya "Andre Sumur". Warga di tempat tinggalnya, Lamboya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menyapa dia Amaenudu, orang yang baik hati. Ini karena perjuangannya mengadakan sumur gali bagi warga Sumba dan Sabu Raijua.
Padahal, latar belakang Graff adalah pilot balon udara. Selama puluhan tahun ia juga memimpin perusahaan balon udara di Perancis untuk pariwisata. Dia suka menerbangkan balon udara melewati Pegunungan Alpen.
"Menjadi pilot balon udara tidak mudah, kita harus mengikuti arah angin. Terkadang kita sudah sampai di tempat tujuan, tetapi tiba-tiba dibawa angin kembali ke tempat lain. Di sini diperlukan pengetahuan aerologi, meteorologi, dan klimatologi," kata Graff di Desa Patijala Bawa, Kecamatan Lamboya, Sumba Barat, 30 kilometer (km) sebelah utara Waikabubak.
Tahun 1990 dan 2004, Graff mengunjungi Bali sebagai turis. Dari Bali dia menyewa perahu layar dan bersama tujuh wisatawan asing dari sejumlah negara menjelajahi beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Sabu Raijua, Sumba, Solor, Lembata, Alor, dan Kepulauan Riung.
"Teman-teman turis itu latar belakangnya beragam, ada yang dokter bedah, ahli planologi, dan ahli pertanian," katanya. Sejumlah aktivitas masyarakat, budaya, dan tradisi lokal pun menjadi obyek foto mereka.
Saat itu Graff berjanji akan mengirimkan foto yang mereka buat kepada warga setempat. Jumlahnya mencapai 3.547 lembar, seberat 25 kilogram. Agustus 2004, ia memutuskan mengantar sendiri foto tersebut kepada sejumlah warga di NTT.
Juni 2005, dia singgah di Sabu Raijua dan menetap di kampung adat Ledetadu. Warga di kampung itu kesulitan air bersih. Setiap hari mereka harus berjalan 2 kilometer untuk mengambil air sumur di dataran rendah.
"Saya prihatin,Saya lalu bertemu Pastor Frans Lakner, Sj yang sudah 40 tahun mengabdi di Sabu. Dia mengajari saya bagaimana mencari air tanah, menggali sumur, dan membuat gorong-gorong dari beton agar air tak terkontaminasi lumpur. Gorong-gorong itu bertahan sampai bertahun-tahun kemudian," katanya.
Graff pun membuat satu unit sumur bagi 127 keluarga di Ledetadu. Merasa puas atas hasilnya, dia lalu menggali sumur dan memasang gorong-gorong beton lain bagi warga seekitar Ledetadu.
Pada 2005-2007, dia berhasil membuat 25 sumur gali bagi 1.250 keluarga yang tersebar di tiga desa. Graff juga mengajarkan warga setempat untuk mencari air, menggali, dan membuat gorong-gorong yang berkualitas. Pengetahuan itu terus dia tularkan kepada desa-desa di sekitar Ledetadu dan Namata.
Berkat air sumur, warga bisa menanam sayur, jagung, buah, dan umbi-umbian di sekitar rumah. Mereka bisa menjual hasil kebunnya ke pasar untuk membeli beras dan kebutuhan lain.
Akhir 2007, ia memutuskan pindah ke Lamboya, Sumba Barat, setelah warga Sabu Raijua bisa membuat sumur sendiri. Ia tinggal dengan Rato (Kepala Suku) Kampung Waru Wora, Desa Patijala Bawa, Lamboya. Di sini ia membentuk kelompok pemuda beranggotakan sembilan orang untuk membuat gorong-gorong yang disebut GGWW (Gorong-gorong Waru Wora).
Melihat kualitas dan fungsi gorong-gorong itu, warga kampung dan desa lain di sekitar Patijala pun memesan gorong-gorong kepada GGWW dengan harga Rp 300.000 per potong (sekitar 1m x 1m).
Pada 2007-2011, sebanyak 35 sumur berhasil dikerjakan Graff bersama GGWW. Mereka melakukan pencarian air dengan kemampuan khusus yang dimiliki para rato dalam menentukan lokasi sumber air tanah.
"Orang kampung tak memakai alas kaki. Telapak kaki mereka langsung langsung kontak dengan tanah dan mampu merasakan lokasi di mana ada air," kata Graff.
Permukiman warga di Sumba dan Sabu umumnya berada di dataran tinggi dengan jarak tempuh ke lembah yang ada sumber airnya 1 km hingga 3 km.
"Setiap pagi, kaum perempuan menghabiskan 2-3 jam untuk mengambil air 20 liter. Air untuk memasak, mencuci alat dapur, dan memberi minum ternak. Anak-anak ke sekolah tak mandi. Warga kampung pun buang hajat di sembarang tempat. Ini membuat sanitasi jadi buruk," katanya.
Graff mencari solusi tanpa mengotori lingkungan dengan mesin diesel berbahan bakar minyak. Energi matahari diupayakannya untuk menaikkan air dari lembah ke perkampungan. Ia menemui seorang ahli tenaga matahari di Denpasar.
Mereka mengevaluasi masalah air sumur dan permukiman warga Sumba, lalu terbentuklah Pilot Project Waru Wora (PPWW) berupa sinar sel.
Graff kekurangan modal. Namun, ia berhasil mendapat bantuan Rp 330 juta dari Rotary Club Belanda. Dana itu belum cukup untuk mewujudkan proyek tersebut.Masih dibutuhkan dana sekitar Rp 500 juta.
Salah satu upaya yang dilakukannya adalah mengadakan pameran foto tentang Sumba dan Sabu Raijua di Jakarta dan Denpasar.
"Sayang, foto-fotonya tak laku. Orang hanya kagum , tetapi tak membeli. Namun, saya bertemu orang dari Shimizu yang bersedia emmbantu pompa, pipa, tanki air, dan bahan lain. Ada pula teman yang membantu Rp 50 juta, tetapi kesulitan belum teratasi," kata Graff yang juga mendapat bantuan dari Bupati Sumba Barat sebesar Rp 65 juta.
Menurut dia, komponen termahal proyek ini adalah solar sel berukuran 6meter x 6meter untuk menampung energi matahari guna menaikkan air dengan ketinggian 1.300 meter ke permukiman warga yang berjarak 110 meter.
Apabila proyek ini terwujud, 11 kampung di Desa Patijala Bawa atau sekitar 1.600 jiwa bisa menikmati air bersih. Sampai kini baru 600 jiwa atau tujuh kampung yang terlayani.
"Saya bukan orang LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang (sebagian) asal kerja. Saya punya pilot project. Orang bisa belajar di sini karena proyek dengan sinar matahari guna 'menarik' air ini merupakan (salah satu) terbesar di Indonesia. Ke depan, wilayah ini bisa menjadi pusat wisata," katanya.
Jika proyek itu terwujud, Graff sudah punya program lain, yakni melakukan filtrasi (penjernihan) air, program pengadaan rumah mandi untuk kelompok masyarakat di setiap kampung, dan program pertanian pekarangan rumah atau lahan terbatas.

Burung-burung liar bersenandung sembari mencecap kesejukan embun yang tersisa, berkejaran di antara daun pakis yang berjuntaian ke tanah, sejenak mematuki serangga, kemudian hinggap di atas sebuah tenda yang dihuni Aurelien Brule.
"Saya memutuskan tinggal di hutan ini untuk mengamati dan mempelajari kehidupan owa-owa (Hylobates muelleri) di habitat yang sesungguhnya," kata lelaki kelahiran Frejus, Prancis, 2 Juli 1979 ini.
Owa adalah sejenis kera kecil dan hewan paling langka di dunia.
Menyelami kehidupan di hutan, beraktivitas dengan berbagai satwa, membuat lelaki yang menamatkan sekolah menengah atas di Saint Raphael, Distrik Var, Prancis, ini makin memahami karakter dan kebutuhan hidup owa-owa.
Tak terhenti menjadi 'orang hutan' di belantara Myanmar, Aurelien Brule melanjutkan penelitian menuju Thailand. Begitu intensifnya lelaki ini menelusup dalam kehidupan owa-owa, penduduk lokal pun memberi nama 'Chanee' pada Aurelien Brule. Chanee adalah sebutan untuk owa-owa dalam bahasa Thailand.
Tepat pada Mei 1998, Chanee tiba di Indonesia. Saat itu, kerusuhan tengah terjadi di Indonesia, aksi massa merebak di berbagai wilayah, namun tak membuat Chanee surut langkah.
"Di dunia ini, terdapat 17 jenis owa. Tujuh jenis di antaranya berada di Indonesia. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk meninggalkan Prancis dan mantap bertolak ke Indonesia," kata Chanee, yang fasih berbahasa Indonesia.
Dalam kondisi situasi politik yang tidak menentu, Chanee pergi ke Kalimantan Tengah. Pilihannya itu dilandasi pemikiran bahwa kawasan hutan di Kalimantan Tengah masih terbilang luas. Setiba di Kalimantan, ia memulai mengobservasi kehidupan owa-owa.
Tiga bulan kemudian, Chanee berangkat ke Dinas Kehutanan di Jakarta, untuk mengajak bekerja sama dengan Yayasan Kalaweit dalam mengonservasi owa-owa di habitatnya. Tawaran itu bersambut baik.
"Kalaweit itu istilah Suku Dayak untuk menyebut owa-owa. Sekarang yayasan kami sudah bisa intensif melaksanakan tiga program," kata Chanee.
Program pertama adalah menerima satwa hasil dari perdagangan ilegal atau dari masyarakat, untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke alam bebas. Kedua, bersama-sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), semaksimal mungkin mengamankan area konservasi agar tidak tergusur menjagi lahan perkebunan. Ketiga, menyampaikan pesan kepada masyarakat luas tentang pelestarian satwa liar melalui siaran radio Kalaweit FM.
Berkat penyiaran lewat radio, tak disangka respons masyarakat sangat baik. Dengan kesadaran sendiri, satu demi satu masyarakat tergerak hatinya dan menyerahkan owa-owa atau hewan liar peliharaannya kepada Yayasan Kalaweit, yang kemudian dilepasliarkan kembali di hutan.
"Ketika datang ke Indonesia, saya memiliki mimpi untuk melepaskan satwa-satwa dari kandang. Namun dalam realitasnya, mimpi ini sulit sekali kami diwujudkan," kata suami dari Nurpradawati ini.
Kesulitan mewujudkan mimpi, terutama karena wilayah hutan di Kalimantan kian hari makin terdesak oleh langkah sejumlah perusahaan yang begitu agresif membuka areal perkebunan kelapa sawit seluas-luasnya. Akibatnya, ruang gerak owa-owa dan beragam satwa lain menjadi terbatas.
Bagi Chanee, dirinya tidak melarang keberadaan perkebunan kelapa sawit, namun jangan sampai mengorbankan dan memusnahkah wilayah hutan agar satwa tetap memiliki habitat untuk berkembang biak, serta menikmati kehidupan dalam keramahan alam.
"Sekarang, lahan hutan sudah dikepung perusahaan. Ibaratnya, lahan konservasi adalah pulau hutan di tengah-tengah perusahaan. Kalau begini kondisinya, di mana lagi satwa bisa hidup sewajarnya?" ucap Chanee dengan nada menyimpan kecewa.
Berkat kerja keras dan sumbangan dari berbagai donatur, Yayasan Kalaweit berhasil membeli lahan seluas 8 hektare di wilayah Kalimantan Tengah untuk lahan konservasi satwa. Selain itu, bersama
BKSDA, Yayasan Kalaweit senantiasa bahu-membahu untuk menjaga Cagar Alam Pararawen di Barito Utara, Kalimantan Tengah seluas 6.000 hektare agar tetap lestari.
Sementara itu, di Sumatera Barat, Yayasan Kalaweit mendirikan tempat perlindungan owa-owa di Kabupaten Solok, di atas lahan seluas 140 hektare.
"Yang jelas, sampai kapan pun, kami akan berjuang untuk mempertahankan hutan. Seharusnya ada UU yang mengatur agar hutan dicagaralamkan sehingga lingkungan hidup dan satwa itu terlindungi," ucap ayah dari Andrew Ananda Brule dan Enzo Gandola Brule itu, dengan nada tegas.
Ketegasan sikap Chanee ternyata banyak mendatangkan intimidasi kepada dirinya dan keluarganya. Beberapa tahun lalu, rumah Chanee pernah didatangi beberapa orang yang membawa pisau dan mengancamnya.
"Bukan hanya itu. Dulu kami tinggal di sebuah kapal, yang diformat menjadi rumah. Tapi mendadak kapal itu ditenggelamkan oleh orang-orang tidak dikenal, dicurigai ada hubungan dengan penebang yang memang mengincar kawasan owa-owa. Tapi, sudah 16 tahun kami berjuang agar owa-owa dan satwa liar mempunyai hutan untuk hidup, jadi kami tidak akan mudah menyerah begitu saja," kata Chanee.
Ketertarikan Chanee pada owa-owa, memiliki perjalanan sejarah tersendiri. Pada 1992, saat berusia 12 tahun, dia diajak ibunya berpiknik ke kebun binatang di Prancis. Beberapa primata diamatinya dengan kekaguman tersendiri, karena terlihat ceria dan gembira bersama teman-temannya.
Begitu sampai di kandang owa-owa, dia tertegun sejenak. Dilihatnya owa-owa terlihat merana dan sendirian. Ekspresi wajahnya begitu sedih dan mengambarkan rasa kesepian mendalam. Pengalaman ini membuatnya penasaran, hingga saat libur sekolah berikutnya, dia kembali minta diantarkan keluarganya ke kebun binatang.
"Setiap Rabu pagi, saat libur sekolah, saya datang ke kebun binatang khusus untuk mengamati owa-owa. Mencoba mempelajari ekologi dan kepribadiannya. Saat kebun binatang tutup, baru saya pulang," katanya.
Kegiatan mempelajari karakter owa-owa ini begitu membekas di hari Chanee, hingga ia memberanikan diri untuk menghadap pimpinan kebun binatang, terkait minatnya yang besar pada owa-owa. Saat itu, Chanee menawarkan diri untuk menjodohkan owa-owa.
Ide Chanee diapreasi dengan baik. Sejak itu, dia sering berkeliling ke berbagai kebun binatang di Perancis untuk menjodohkan owa-owa.
"Saya rela membuka biro jodoh untuk owa-owa, agar satwa ini tidak sampai punah," ucap lelaki ini sembari tertawa.
Minatnya yang besar terhadap owa-owa, membuat Chanee tertarik menuliskan berbagai pengalamannya selama mengamati perilaku dan karakter satwa itu. Semula dia berpikir tulisannya hanya akan diminati kalangan terbatas saja.
Namun, begitu ditawarkan kepada penerbit, ternyata mendapatkan perhatian yang mengejutkan. Editor penerbit menyatakan jika naskah Chanee sangat layak untuk diterbitkan. Usia Chanee yang ketika itu baru 16 tahun, tapi sudah mampu mengerjakan buku yang begitu intens tentang mengupas kehidupan detil owa-owa, menjadi poin plus tersendiri.
Begitu buku berjudul 'Le gibbon a mains blanches' itu diterbitkan dan muncul di pasaran, ternyata memang cukup menarik perhatian masyarakat. Bahkan, usai membaca buku itu, seorang artis Muriel Robin seketika berminat untuk bertemu dengan Chanee.
"Ketika bertemu, Muriel Robin menawarkan dukungan dana agar saya dapat pergi ke Thailand untuk melihat owa-owa langsung di kehidupan aslinya. Itu makanya saya bisa pergi ke perbatasan Myanmar dan Thailand, berkat sokongan dana tersebut," ujar dia.
Perjalanan ke berbagai negara, menumbuhkan rasa cinta yang kian dalam pada diri Chanee terhadap owa-owa. Luapan perasaannya makin bertumbuh tatkala sejak 2012, dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI), setelah bertahun-tahun tiada lelah memperjuangkan diri agar bisa mendapat kewarganegaraan itu.
"Dulu, saya merasa menjadi tamu saja, seperti menjadi saksi mata. Sekarang, setelah saya menjadi WNI, rasanya luar biasa sekali karena merasa apa yang saya perjuangkan untuk owa-owa, itu saya lakukan di negeri saya sendiri," kata Chanee, dengan nada terharu.
Sampai kapan pun, Chanee memang bertekad tidak akan berhenti untuk memperjuangkan owa-owa agar mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak terikat rantai atau terkurung di kandang. Melalui Kalaweit FM, Chanee terus berusaha mengajak masyarakat luas, termasuk generasi muda, agar peduli kepada satwa liar.
Bagi Chanee, memperjuangkan satwa liar seolah menjadi napas dalam kesehariannya, makanya tidak jarang hatinya terasa teriris tatkala melihat owa-owa atau binatang lain jika mengalami kondisi buruk dari manusia.
Di sisi lain, hatinya serasa memberontak melihat perkebunan kelapa sawit berkembang demikian cepat, hingga ruang gerak satwa makin terbatas dan terus menyusut.
"Perasaan saya campur aduk. Sangat sedih melihat kondisi satwa liar makin terancam. Misalnya, saya berhasil menyelamatkan satu ekor satwa, namun di tempat lain ada 100 binatang yang dimusnahkah. Ini menyakitkan sekali. Makanya saya tidak pernah lelah berjuang," ujar Chane dengan suara penuh kesedihan.
Perjuangan Chanee agar satwa kembali ke habitatnya juga disebabkan agar owa-owa tidak mengalami tekanan hidup atau stres. Misalnya, owa-owa, jika hidup di alam liar, usianya bisa mencapai 30-35 tahun. Namun, jika dipelihara manusia, usianya maksimal hanya mencapai 10 tahun.
Biasanya, dalam masa pemeliharaan manusia, begitu menginjak umur tujuh tahun, owa-owa sudah terdera penyakit, karena memang satwa ini sangat sensitif terhadap stres. Salah satu penyebab stres apabila owa-owa dibelenggu menggunakan ikat pinggang. Lama-lama, dengan kondisinya ini, mengakibatkan owa-owa stres, gila dan disusul kematian segera merenggutnya.
Begitu kuat keinginan Chanee ingin melindungi owa-owa dan satwa liar lain, sampai-sampai dirinya tidak tergerak ingin membuka 'ecotourism', apalagi jika bertujuan komersial.

Gavin Birch itulah namanya dulu. Tapi ketika ia mulai menetap di Lombok ia lebih dikenal dengan nama Husin Abdullah. Dilahirkan di Selandia Baru dan dibesarkan di Perth, Australia. Dia sering mengunjungi Pantai Senggigi di Lombok. Orang-orang disana sering menyebutnya sebafai “turis gila”. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang selalu bergumul dengan sampah setiap ia mengunjungi pantai Senggigi.
Namun, Husin seakan tidak perduli dengan gelar yang disematkan warga sekitar padanya. Ia hanya bertekad untuk mengajak orang banyak untuk bisa hidup bersih. Karena baginya Indonesia itu harus bersih dan hijau.
Tentu timbul pertanyaan, kenapa ia bisa tiba-tiba menjadi seorang pemungut sampah di Senggigi. Ketika itu pada tahun 1986 ia untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Pulau Lombok sebagai seorang turis. Dan pada saat itu ia kecewa karena banyaknya tumpukan sampah di pantai-pantai yang ada di sana. Niatnya untuk berlibur dan menikmati keindahan alam di Lombok pun tidak menjadi seperti impian awalnya. Bahkan pantai Ampenan yang menyimpan potensi wisata pun penuh dengan kotoran manusia.
Tapi, uniknya ia tidak langsung pergi beranjak menjauh ketika itu. Ia yakin, ketika itu jika masyarakat sekitar peduli dengan kebersihan maka pantai tersebut pasti akan indah dilihat.
Sejak itulah ia mulai bergerak sendiri. Memungut sampah di sekitar pantai dan mengumpulkannya. Berbagai komentar mulai diterimanya. Ada yang simpati, tapi ada juga yang memandang sebelah mata. Salah satu dari masyarakat yang simpati yaitu lurah kampung Melayu Ampenan, Haji Hairi Asmuni memintanya untuk menetap di Lombok sebagai bentu apresiasinya.
Lalu, ketika sejak itu ia mulai menerapkan “program indonesia bersih dan hijau” yang diadopsi dari program kebersihan di Australia. Bahkan, Husin juga sempat menawarkannya kepada pemerintah di sana. Namun, sayang hal ini tidak disambut baik karena ketiadaan dana. Karena itulah ia mulai bergerak sendiri dengan menggunakan uang dari koceknya sendiri. Husin tetap tidak mengeluh, katanya ini sebagian dari bentuk amal.
Perjuangannya selama 24 tahun pun ternyata tidak berakhir sia-sia. Kini di kawasan Jalan Raya Senggigi bersih dari sampah. Meski kini ia telah tiada pada tanggal 18 Agustus 2010 lalu. Tapi banyak hal yang telah ditinggalkannya dan sangat bermanfaat untuk orang sekitarnya. Sekedar renungan, mana yang lebih gila, turis asing yang rela menghabiskan sisa hidupnya untuk membersihkan lingkungan atau anak negeri sendiri yang suka membuang sampah di halaman rumahnya?
Sebelum di baca mohon di


Dan jika berkenang ane minta


Spoiler for semoga no repost:
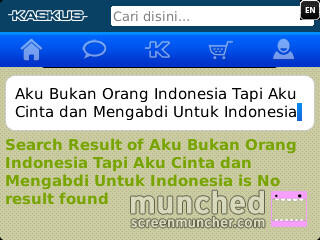

Sedih rasanya jika kita membaca judul di atas tersebut termasuk saya sendiri sangat sedih
Saya mengambil satu kutipan dari presiden pertama kita bapak presiden ir.soekarno
"Jangan tanya apa yang negara ini bisa berikan padamu?, tapi tanyalah apa yang bisa kamu berikan pada negara ini? Seberapa besar cinta kita pada Indonesia? Apa yang sudah kita berikan pada Ibu Pertiwi? jawabanya ada pada diri kita masing-masing, dari sekian banyak orang yang tanpa pamrih mengabdikan dirinya untuk negeri ini, inilah di antara mereka, mereka bukan orang Indonesia tapi Cinta dan pengabdiannya di sebagian hidupnya untuk Indonesia. Orang-orang inilah yang seharusnya bisa menjadi contoh bagi kita sebagai warga indonesia.
Spoiler for Andre Graff "Penggali Sumur":

Nama aslinya Andre Graff, tetapi masyarakat Sumba memanggilnya "Andre Sumur". Warga di tempat tinggalnya, Lamboya, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, menyapa dia Amaenudu, orang yang baik hati. Ini karena perjuangannya mengadakan sumur gali bagi warga Sumba dan Sabu Raijua.
Padahal, latar belakang Graff adalah pilot balon udara. Selama puluhan tahun ia juga memimpin perusahaan balon udara di Perancis untuk pariwisata. Dia suka menerbangkan balon udara melewati Pegunungan Alpen.
"Menjadi pilot balon udara tidak mudah, kita harus mengikuti arah angin. Terkadang kita sudah sampai di tempat tujuan, tetapi tiba-tiba dibawa angin kembali ke tempat lain. Di sini diperlukan pengetahuan aerologi, meteorologi, dan klimatologi," kata Graff di Desa Patijala Bawa, Kecamatan Lamboya, Sumba Barat, 30 kilometer (km) sebelah utara Waikabubak.
Tahun 1990 dan 2004, Graff mengunjungi Bali sebagai turis. Dari Bali dia menyewa perahu layar dan bersama tujuh wisatawan asing dari sejumlah negara menjelajahi beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur (NTT), seperti Sabu Raijua, Sumba, Solor, Lembata, Alor, dan Kepulauan Riung.
"Teman-teman turis itu latar belakangnya beragam, ada yang dokter bedah, ahli planologi, dan ahli pertanian," katanya. Sejumlah aktivitas masyarakat, budaya, dan tradisi lokal pun menjadi obyek foto mereka.
Saat itu Graff berjanji akan mengirimkan foto yang mereka buat kepada warga setempat. Jumlahnya mencapai 3.547 lembar, seberat 25 kilogram. Agustus 2004, ia memutuskan mengantar sendiri foto tersebut kepada sejumlah warga di NTT.
Juni 2005, dia singgah di Sabu Raijua dan menetap di kampung adat Ledetadu. Warga di kampung itu kesulitan air bersih. Setiap hari mereka harus berjalan 2 kilometer untuk mengambil air sumur di dataran rendah.
"Saya prihatin,Saya lalu bertemu Pastor Frans Lakner, Sj yang sudah 40 tahun mengabdi di Sabu. Dia mengajari saya bagaimana mencari air tanah, menggali sumur, dan membuat gorong-gorong dari beton agar air tak terkontaminasi lumpur. Gorong-gorong itu bertahan sampai bertahun-tahun kemudian," katanya.
Graff pun membuat satu unit sumur bagi 127 keluarga di Ledetadu. Merasa puas atas hasilnya, dia lalu menggali sumur dan memasang gorong-gorong beton lain bagi warga seekitar Ledetadu.
Pada 2005-2007, dia berhasil membuat 25 sumur gali bagi 1.250 keluarga yang tersebar di tiga desa. Graff juga mengajarkan warga setempat untuk mencari air, menggali, dan membuat gorong-gorong yang berkualitas. Pengetahuan itu terus dia tularkan kepada desa-desa di sekitar Ledetadu dan Namata.
Berkat air sumur, warga bisa menanam sayur, jagung, buah, dan umbi-umbian di sekitar rumah. Mereka bisa menjual hasil kebunnya ke pasar untuk membeli beras dan kebutuhan lain.
Akhir 2007, ia memutuskan pindah ke Lamboya, Sumba Barat, setelah warga Sabu Raijua bisa membuat sumur sendiri. Ia tinggal dengan Rato (Kepala Suku) Kampung Waru Wora, Desa Patijala Bawa, Lamboya. Di sini ia membentuk kelompok pemuda beranggotakan sembilan orang untuk membuat gorong-gorong yang disebut GGWW (Gorong-gorong Waru Wora).
Melihat kualitas dan fungsi gorong-gorong itu, warga kampung dan desa lain di sekitar Patijala pun memesan gorong-gorong kepada GGWW dengan harga Rp 300.000 per potong (sekitar 1m x 1m).
Pada 2007-2011, sebanyak 35 sumur berhasil dikerjakan Graff bersama GGWW. Mereka melakukan pencarian air dengan kemampuan khusus yang dimiliki para rato dalam menentukan lokasi sumber air tanah.
"Orang kampung tak memakai alas kaki. Telapak kaki mereka langsung langsung kontak dengan tanah dan mampu merasakan lokasi di mana ada air," kata Graff.
Permukiman warga di Sumba dan Sabu umumnya berada di dataran tinggi dengan jarak tempuh ke lembah yang ada sumber airnya 1 km hingga 3 km.
"Setiap pagi, kaum perempuan menghabiskan 2-3 jam untuk mengambil air 20 liter. Air untuk memasak, mencuci alat dapur, dan memberi minum ternak. Anak-anak ke sekolah tak mandi. Warga kampung pun buang hajat di sembarang tempat. Ini membuat sanitasi jadi buruk," katanya.
Graff mencari solusi tanpa mengotori lingkungan dengan mesin diesel berbahan bakar minyak. Energi matahari diupayakannya untuk menaikkan air dari lembah ke perkampungan. Ia menemui seorang ahli tenaga matahari di Denpasar.
Mereka mengevaluasi masalah air sumur dan permukiman warga Sumba, lalu terbentuklah Pilot Project Waru Wora (PPWW) berupa sinar sel.
Graff kekurangan modal. Namun, ia berhasil mendapat bantuan Rp 330 juta dari Rotary Club Belanda. Dana itu belum cukup untuk mewujudkan proyek tersebut.Masih dibutuhkan dana sekitar Rp 500 juta.
Salah satu upaya yang dilakukannya adalah mengadakan pameran foto tentang Sumba dan Sabu Raijua di Jakarta dan Denpasar.
"Sayang, foto-fotonya tak laku. Orang hanya kagum , tetapi tak membeli. Namun, saya bertemu orang dari Shimizu yang bersedia emmbantu pompa, pipa, tanki air, dan bahan lain. Ada pula teman yang membantu Rp 50 juta, tetapi kesulitan belum teratasi," kata Graff yang juga mendapat bantuan dari Bupati Sumba Barat sebesar Rp 65 juta.
Menurut dia, komponen termahal proyek ini adalah solar sel berukuran 6meter x 6meter untuk menampung energi matahari guna menaikkan air dengan ketinggian 1.300 meter ke permukiman warga yang berjarak 110 meter.
Apabila proyek ini terwujud, 11 kampung di Desa Patijala Bawa atau sekitar 1.600 jiwa bisa menikmati air bersih. Sampai kini baru 600 jiwa atau tujuh kampung yang terlayani.
"Saya bukan orang LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang (sebagian) asal kerja. Saya punya pilot project. Orang bisa belajar di sini karena proyek dengan sinar matahari guna 'menarik' air ini merupakan (salah satu) terbesar di Indonesia. Ke depan, wilayah ini bisa menjadi pusat wisata," katanya.
Jika proyek itu terwujud, Graff sudah punya program lain, yakni melakukan filtrasi (penjernihan) air, program pengadaan rumah mandi untuk kelompok masyarakat di setiap kampung, dan program pertanian pekarangan rumah atau lahan terbatas.
Spoiler for Aurelien Brule:

Burung-burung liar bersenandung sembari mencecap kesejukan embun yang tersisa, berkejaran di antara daun pakis yang berjuntaian ke tanah, sejenak mematuki serangga, kemudian hinggap di atas sebuah tenda yang dihuni Aurelien Brule.
"Saya memutuskan tinggal di hutan ini untuk mengamati dan mempelajari kehidupan owa-owa (Hylobates muelleri) di habitat yang sesungguhnya," kata lelaki kelahiran Frejus, Prancis, 2 Juli 1979 ini.
Owa adalah sejenis kera kecil dan hewan paling langka di dunia.
Menyelami kehidupan di hutan, beraktivitas dengan berbagai satwa, membuat lelaki yang menamatkan sekolah menengah atas di Saint Raphael, Distrik Var, Prancis, ini makin memahami karakter dan kebutuhan hidup owa-owa.
Tak terhenti menjadi 'orang hutan' di belantara Myanmar, Aurelien Brule melanjutkan penelitian menuju Thailand. Begitu intensifnya lelaki ini menelusup dalam kehidupan owa-owa, penduduk lokal pun memberi nama 'Chanee' pada Aurelien Brule. Chanee adalah sebutan untuk owa-owa dalam bahasa Thailand.
Tepat pada Mei 1998, Chanee tiba di Indonesia. Saat itu, kerusuhan tengah terjadi di Indonesia, aksi massa merebak di berbagai wilayah, namun tak membuat Chanee surut langkah.
"Di dunia ini, terdapat 17 jenis owa. Tujuh jenis di antaranya berada di Indonesia. Inilah yang membuat saya memutuskan untuk meninggalkan Prancis dan mantap bertolak ke Indonesia," kata Chanee, yang fasih berbahasa Indonesia.
Dalam kondisi situasi politik yang tidak menentu, Chanee pergi ke Kalimantan Tengah. Pilihannya itu dilandasi pemikiran bahwa kawasan hutan di Kalimantan Tengah masih terbilang luas. Setiba di Kalimantan, ia memulai mengobservasi kehidupan owa-owa.
Tiga bulan kemudian, Chanee berangkat ke Dinas Kehutanan di Jakarta, untuk mengajak bekerja sama dengan Yayasan Kalaweit dalam mengonservasi owa-owa di habitatnya. Tawaran itu bersambut baik.
"Kalaweit itu istilah Suku Dayak untuk menyebut owa-owa. Sekarang yayasan kami sudah bisa intensif melaksanakan tiga program," kata Chanee.
Program pertama adalah menerima satwa hasil dari perdagangan ilegal atau dari masyarakat, untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke alam bebas. Kedua, bersama-sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), semaksimal mungkin mengamankan area konservasi agar tidak tergusur menjagi lahan perkebunan. Ketiga, menyampaikan pesan kepada masyarakat luas tentang pelestarian satwa liar melalui siaran radio Kalaweit FM.
Berkat penyiaran lewat radio, tak disangka respons masyarakat sangat baik. Dengan kesadaran sendiri, satu demi satu masyarakat tergerak hatinya dan menyerahkan owa-owa atau hewan liar peliharaannya kepada Yayasan Kalaweit, yang kemudian dilepasliarkan kembali di hutan.
"Ketika datang ke Indonesia, saya memiliki mimpi untuk melepaskan satwa-satwa dari kandang. Namun dalam realitasnya, mimpi ini sulit sekali kami diwujudkan," kata suami dari Nurpradawati ini.
Kesulitan mewujudkan mimpi, terutama karena wilayah hutan di Kalimantan kian hari makin terdesak oleh langkah sejumlah perusahaan yang begitu agresif membuka areal perkebunan kelapa sawit seluas-luasnya. Akibatnya, ruang gerak owa-owa dan beragam satwa lain menjadi terbatas.
Bagi Chanee, dirinya tidak melarang keberadaan perkebunan kelapa sawit, namun jangan sampai mengorbankan dan memusnahkah wilayah hutan agar satwa tetap memiliki habitat untuk berkembang biak, serta menikmati kehidupan dalam keramahan alam.
"Sekarang, lahan hutan sudah dikepung perusahaan. Ibaratnya, lahan konservasi adalah pulau hutan di tengah-tengah perusahaan. Kalau begini kondisinya, di mana lagi satwa bisa hidup sewajarnya?" ucap Chanee dengan nada menyimpan kecewa.
Berkat kerja keras dan sumbangan dari berbagai donatur, Yayasan Kalaweit berhasil membeli lahan seluas 8 hektare di wilayah Kalimantan Tengah untuk lahan konservasi satwa. Selain itu, bersama
BKSDA, Yayasan Kalaweit senantiasa bahu-membahu untuk menjaga Cagar Alam Pararawen di Barito Utara, Kalimantan Tengah seluas 6.000 hektare agar tetap lestari.
Sementara itu, di Sumatera Barat, Yayasan Kalaweit mendirikan tempat perlindungan owa-owa di Kabupaten Solok, di atas lahan seluas 140 hektare.
"Yang jelas, sampai kapan pun, kami akan berjuang untuk mempertahankan hutan. Seharusnya ada UU yang mengatur agar hutan dicagaralamkan sehingga lingkungan hidup dan satwa itu terlindungi," ucap ayah dari Andrew Ananda Brule dan Enzo Gandola Brule itu, dengan nada tegas.
Ketegasan sikap Chanee ternyata banyak mendatangkan intimidasi kepada dirinya dan keluarganya. Beberapa tahun lalu, rumah Chanee pernah didatangi beberapa orang yang membawa pisau dan mengancamnya.
"Bukan hanya itu. Dulu kami tinggal di sebuah kapal, yang diformat menjadi rumah. Tapi mendadak kapal itu ditenggelamkan oleh orang-orang tidak dikenal, dicurigai ada hubungan dengan penebang yang memang mengincar kawasan owa-owa. Tapi, sudah 16 tahun kami berjuang agar owa-owa dan satwa liar mempunyai hutan untuk hidup, jadi kami tidak akan mudah menyerah begitu saja," kata Chanee.
Ketertarikan Chanee pada owa-owa, memiliki perjalanan sejarah tersendiri. Pada 1992, saat berusia 12 tahun, dia diajak ibunya berpiknik ke kebun binatang di Prancis. Beberapa primata diamatinya dengan kekaguman tersendiri, karena terlihat ceria dan gembira bersama teman-temannya.
Begitu sampai di kandang owa-owa, dia tertegun sejenak. Dilihatnya owa-owa terlihat merana dan sendirian. Ekspresi wajahnya begitu sedih dan mengambarkan rasa kesepian mendalam. Pengalaman ini membuatnya penasaran, hingga saat libur sekolah berikutnya, dia kembali minta diantarkan keluarganya ke kebun binatang.
"Setiap Rabu pagi, saat libur sekolah, saya datang ke kebun binatang khusus untuk mengamati owa-owa. Mencoba mempelajari ekologi dan kepribadiannya. Saat kebun binatang tutup, baru saya pulang," katanya.
Kegiatan mempelajari karakter owa-owa ini begitu membekas di hari Chanee, hingga ia memberanikan diri untuk menghadap pimpinan kebun binatang, terkait minatnya yang besar pada owa-owa. Saat itu, Chanee menawarkan diri untuk menjodohkan owa-owa.
Ide Chanee diapreasi dengan baik. Sejak itu, dia sering berkeliling ke berbagai kebun binatang di Perancis untuk menjodohkan owa-owa.
"Saya rela membuka biro jodoh untuk owa-owa, agar satwa ini tidak sampai punah," ucap lelaki ini sembari tertawa.
Minatnya yang besar terhadap owa-owa, membuat Chanee tertarik menuliskan berbagai pengalamannya selama mengamati perilaku dan karakter satwa itu. Semula dia berpikir tulisannya hanya akan diminati kalangan terbatas saja.
Namun, begitu ditawarkan kepada penerbit, ternyata mendapatkan perhatian yang mengejutkan. Editor penerbit menyatakan jika naskah Chanee sangat layak untuk diterbitkan. Usia Chanee yang ketika itu baru 16 tahun, tapi sudah mampu mengerjakan buku yang begitu intens tentang mengupas kehidupan detil owa-owa, menjadi poin plus tersendiri.
Begitu buku berjudul 'Le gibbon a mains blanches' itu diterbitkan dan muncul di pasaran, ternyata memang cukup menarik perhatian masyarakat. Bahkan, usai membaca buku itu, seorang artis Muriel Robin seketika berminat untuk bertemu dengan Chanee.
"Ketika bertemu, Muriel Robin menawarkan dukungan dana agar saya dapat pergi ke Thailand untuk melihat owa-owa langsung di kehidupan aslinya. Itu makanya saya bisa pergi ke perbatasan Myanmar dan Thailand, berkat sokongan dana tersebut," ujar dia.
Perjalanan ke berbagai negara, menumbuhkan rasa cinta yang kian dalam pada diri Chanee terhadap owa-owa. Luapan perasaannya makin bertumbuh tatkala sejak 2012, dirinya resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI), setelah bertahun-tahun tiada lelah memperjuangkan diri agar bisa mendapat kewarganegaraan itu.
"Dulu, saya merasa menjadi tamu saja, seperti menjadi saksi mata. Sekarang, setelah saya menjadi WNI, rasanya luar biasa sekali karena merasa apa yang saya perjuangkan untuk owa-owa, itu saya lakukan di negeri saya sendiri," kata Chanee, dengan nada terharu.
Sampai kapan pun, Chanee memang bertekad tidak akan berhenti untuk memperjuangkan owa-owa agar mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak terikat rantai atau terkurung di kandang. Melalui Kalaweit FM, Chanee terus berusaha mengajak masyarakat luas, termasuk generasi muda, agar peduli kepada satwa liar.
Bagi Chanee, memperjuangkan satwa liar seolah menjadi napas dalam kesehariannya, makanya tidak jarang hatinya terasa teriris tatkala melihat owa-owa atau binatang lain jika mengalami kondisi buruk dari manusia.
Di sisi lain, hatinya serasa memberontak melihat perkebunan kelapa sawit berkembang demikian cepat, hingga ruang gerak satwa makin terbatas dan terus menyusut.
"Perasaan saya campur aduk. Sangat sedih melihat kondisi satwa liar makin terancam. Misalnya, saya berhasil menyelamatkan satu ekor satwa, namun di tempat lain ada 100 binatang yang dimusnahkah. Ini menyakitkan sekali. Makanya saya tidak pernah lelah berjuang," ujar Chane dengan suara penuh kesedihan.
Perjuangan Chanee agar satwa kembali ke habitatnya juga disebabkan agar owa-owa tidak mengalami tekanan hidup atau stres. Misalnya, owa-owa, jika hidup di alam liar, usianya bisa mencapai 30-35 tahun. Namun, jika dipelihara manusia, usianya maksimal hanya mencapai 10 tahun.
Biasanya, dalam masa pemeliharaan manusia, begitu menginjak umur tujuh tahun, owa-owa sudah terdera penyakit, karena memang satwa ini sangat sensitif terhadap stres. Salah satu penyebab stres apabila owa-owa dibelenggu menggunakan ikat pinggang. Lama-lama, dengan kondisinya ini, mengakibatkan owa-owa stres, gila dan disusul kematian segera merenggutnya.
Begitu kuat keinginan Chanee ingin melindungi owa-owa dan satwa liar lain, sampai-sampai dirinya tidak tergerak ingin membuka 'ecotourism', apalagi jika bertujuan komersial.
Spoiler for Gavin Brich:

Gavin Birch itulah namanya dulu. Tapi ketika ia mulai menetap di Lombok ia lebih dikenal dengan nama Husin Abdullah. Dilahirkan di Selandia Baru dan dibesarkan di Perth, Australia. Dia sering mengunjungi Pantai Senggigi di Lombok. Orang-orang disana sering menyebutnya sebafai “turis gila”. Hal ini dikarenakan pekerjaannya yang selalu bergumul dengan sampah setiap ia mengunjungi pantai Senggigi.
Namun, Husin seakan tidak perduli dengan gelar yang disematkan warga sekitar padanya. Ia hanya bertekad untuk mengajak orang banyak untuk bisa hidup bersih. Karena baginya Indonesia itu harus bersih dan hijau.
Tentu timbul pertanyaan, kenapa ia bisa tiba-tiba menjadi seorang pemungut sampah di Senggigi. Ketika itu pada tahun 1986 ia untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Pulau Lombok sebagai seorang turis. Dan pada saat itu ia kecewa karena banyaknya tumpukan sampah di pantai-pantai yang ada di sana. Niatnya untuk berlibur dan menikmati keindahan alam di Lombok pun tidak menjadi seperti impian awalnya. Bahkan pantai Ampenan yang menyimpan potensi wisata pun penuh dengan kotoran manusia.
Tapi, uniknya ia tidak langsung pergi beranjak menjauh ketika itu. Ia yakin, ketika itu jika masyarakat sekitar peduli dengan kebersihan maka pantai tersebut pasti akan indah dilihat.
Sejak itulah ia mulai bergerak sendiri. Memungut sampah di sekitar pantai dan mengumpulkannya. Berbagai komentar mulai diterimanya. Ada yang simpati, tapi ada juga yang memandang sebelah mata. Salah satu dari masyarakat yang simpati yaitu lurah kampung Melayu Ampenan, Haji Hairi Asmuni memintanya untuk menetap di Lombok sebagai bentu apresiasinya.
Lalu, ketika sejak itu ia mulai menerapkan “program indonesia bersih dan hijau” yang diadopsi dari program kebersihan di Australia. Bahkan, Husin juga sempat menawarkannya kepada pemerintah di sana. Namun, sayang hal ini tidak disambut baik karena ketiadaan dana. Karena itulah ia mulai bergerak sendiri dengan menggunakan uang dari koceknya sendiri. Husin tetap tidak mengeluh, katanya ini sebagian dari bentuk amal.
Perjuangannya selama 24 tahun pun ternyata tidak berakhir sia-sia. Kini di kawasan Jalan Raya Senggigi bersih dari sampah. Meski kini ia telah tiada pada tanggal 18 Agustus 2010 lalu. Tapi banyak hal yang telah ditinggalkannya dan sangat bermanfaat untuk orang sekitarnya. Sekedar renungan, mana yang lebih gila, turis asing yang rela menghabiskan sisa hidupnya untuk membersihkan lingkungan atau anak negeri sendiri yang suka membuang sampah di halaman rumahnya?
Diubah oleh rckbty 22-05-2014 09:08
0
5.2K
Kutip
30
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan