- Beranda
- Komunitas
- Entertainment
- Kekoreaan
Taman Penis & Kisah Legenda Perawan yang Tenggelam di Korea
TS
aseli.kompeni
Taman Penis & Kisah Legenda Perawan yang Tenggelam di Korea
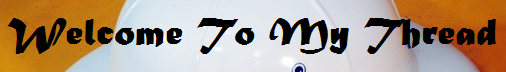
Nubi Bikin Thread

 Sebelum Baca DiBatain Segambreng dulu juga boleh gan
Sebelum Baca DiBatain Segambreng dulu juga boleh gan 


Quote:
Inilah kelakuan unik ato kelebihan kreatif orang korea yaitu membuat taman penis, nyok simak beritanya gan




Spoiler for Atur Penafasan dulu yah gan sebelum buka:
Quote:




Quote:
Cerita Dulunya :
Samcheok - Haesindang Park di Samcheok, Korsel mungkin bakal membuat dahi Anda mengerenyit. Inilah taman yang di dalamnya terdapat 100 patung penis. Tapi tunggu dulu, rupanya patung-patung penis di sana ada kaitannya dengan legenda perawan yang tenggelam.
Tiap negara di dunia punya aneka legenda yang menarik untuk ditelusuri. Di Korea Selatan misalnya, di sana ada Haesindang Park yang punya legenda terkenal. Masyarakat setempat pun masih mempercayai legendanya sampai sekarang.
Dari situs Visit Korea yang dikunjungi detikTravel, Kamis (7/11/2013) Haesindang Park berada di Samcheok, provinsi Gangwon. Lokasinya berada di bagian pantai timur Korea. Sebuah legenda yang terkenal di sana adalah Auebawi dan Haesindang.
Dikisahkan, ada sepasang kekasih yang tinggal di sana. Suatu hari, sang pria ingin berlayar ke laut mencari ikan dan kekasih wanitanya yang masih perawan setia menanti di pinggir pantai. Lalu tiba-tiba, terjadilah badai dahsyat berupa angin dan gelombang lautan. Sang wanita pun langsung terhempas dan tenggelam ke laut, serta prianya tak mampu menyelamatkannya.
Sejak saat itulah, para nelayan setempat rupanya tidak bisa menangkap ikan dengan jumlah banyak. Mereka sungguh kesulitan untuk mencari ikan. Kemudian, mereka percaya bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan wanita perawan yang tewas tenggelam.
Lantas, masyarakat setempat membuat patung-patung dan ukiran penis dari kayu. Hal tersebut bertujuan untuk 'menghibur' sang wanita yang tenggelam tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengadakan upacara keagamaan di kuil kecil yang bernama Haesindang.
Sejak saat itu, masyarakat setempat kembali dapat menjaring ikan dengan jumlah yang banyak. Kehidupan para nelayannya pun kembali baik seperti sedia kala. Uniknya, upacara keagamaan di Kuil Haesindang masih dilakukan dua kali dalam setahun sampai sekarang. Turis yang datang pun bisa menyaksikan upacara ini. Bahkan, upacara keagamaannya pun sudah menjadi upacara adat masyarakat setempat.
Sampai saat ini, keberadaan patung dan ukiran kayu berbentuk penis masih ada di Haesindang Park. Traveler pun bisa dengan bebas masuk ke dalam Haesindang Park dan melihat taman penis di dalamnya.
Tiket masuknya adalah 3.000 Won atau sekitar Rp 32 ribu untuk pengunjung dewasa. Untuk remaja, harga tikernya 2.000 atau sekitar Rp 21 ribu Won dan 1.500 Won atau sekitar Rp 16 ribu untuk anak-anak.
Haesindang Park buka dari bulan Maret–Oktober, sejak pukul 09.00-18.00 waktu setempat. Pada bulan November-Februari, tutupnya lebih awal yakni pukul 17.00 sore waktu setempat.
Untuk mencapai Haesindang Park, Anda bisa naik bus nomor 24 dari Terminal Bus Antarkota Samcheok. Silakan mengelilingi Haesindang Park dan melihat aneka patung penis serta mengenali lebih dekat legendanya. Sst! Bahkan ada patung penis yang berbentuk meriam di sana.
Quote:
Samcheok - Haesindang Park di Samcheok, Korsel mungkin bakal membuat dahi Anda mengerenyit. Inilah taman yang di dalamnya terdapat 100 patung penis. Tapi tunggu dulu, rupanya patung-patung penis di sana ada kaitannya dengan legenda perawan yang tenggelam.
Tiap negara di dunia punya aneka legenda yang menarik untuk ditelusuri. Di Korea Selatan misalnya, di sana ada Haesindang Park yang punya legenda terkenal. Masyarakat setempat pun masih mempercayai legendanya sampai sekarang.
Dari situs Visit Korea yang dikunjungi detikTravel, Kamis (7/11/2013) Haesindang Park berada di Samcheok, provinsi Gangwon. Lokasinya berada di bagian pantai timur Korea. Sebuah legenda yang terkenal di sana adalah Auebawi dan Haesindang.
Dikisahkan, ada sepasang kekasih yang tinggal di sana. Suatu hari, sang pria ingin berlayar ke laut mencari ikan dan kekasih wanitanya yang masih perawan setia menanti di pinggir pantai. Lalu tiba-tiba, terjadilah badai dahsyat berupa angin dan gelombang lautan. Sang wanita pun langsung terhempas dan tenggelam ke laut, serta prianya tak mampu menyelamatkannya.
Sejak saat itulah, para nelayan setempat rupanya tidak bisa menangkap ikan dengan jumlah banyak. Mereka sungguh kesulitan untuk mencari ikan. Kemudian, mereka percaya bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan wanita perawan yang tewas tenggelam.
Lantas, masyarakat setempat membuat patung-patung dan ukiran penis dari kayu. Hal tersebut bertujuan untuk 'menghibur' sang wanita yang tenggelam tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengadakan upacara keagamaan di kuil kecil yang bernama Haesindang.
Sejak saat itu, masyarakat setempat kembali dapat menjaring ikan dengan jumlah yang banyak. Kehidupan para nelayannya pun kembali baik seperti sedia kala. Uniknya, upacara keagamaan di Kuil Haesindang masih dilakukan dua kali dalam setahun sampai sekarang. Turis yang datang pun bisa menyaksikan upacara ini. Bahkan, upacara keagamaannya pun sudah menjadi upacara adat masyarakat setempat.
Sampai saat ini, keberadaan patung dan ukiran kayu berbentuk penis masih ada di Haesindang Park. Traveler pun bisa dengan bebas masuk ke dalam Haesindang Park dan melihat taman penis di dalamnya.
Tiket masuknya adalah 3.000 Won atau sekitar Rp 32 ribu untuk pengunjung dewasa. Untuk remaja, harga tikernya 2.000 atau sekitar Rp 21 ribu Won dan 1.500 Won atau sekitar Rp 16 ribu untuk anak-anak.
Haesindang Park buka dari bulan Maret–Oktober, sejak pukul 09.00-18.00 waktu setempat. Pada bulan November-Februari, tutupnya lebih awal yakni pukul 17.00 sore waktu setempat.
Untuk mencapai Haesindang Park, Anda bisa naik bus nomor 24 dari Terminal Bus Antarkota Samcheok. Silakan mengelilingi Haesindang Park dan melihat aneka patung penis serta mengenali lebih dekat legendanya. Sst! Bahkan ada patung penis yang berbentuk meriam di sana.
Quote:
Original Posted By abdul731►di candi CETHO karanganyar jateng jg ada gan,
Setelah
 Telusuri dan Tanya Mbah gugel biar ga tersesat Ternyata Benar di Indonesia juga ada Namanya Candi Sukuh dan Candi Ceto, Karang Anyar, Jawa Tengah tapi dengan sejarah berbeda dengan yang di atas gan.. nyok simak gan
Telusuri dan Tanya Mbah gugel biar ga tersesat Ternyata Benar di Indonesia juga ada Namanya Candi Sukuh dan Candi Ceto, Karang Anyar, Jawa Tengah tapi dengan sejarah berbeda dengan yang di atas gan.. nyok simak gan



Spoiler for Jangan lupa minum aer putihya dulu gan:
Quote:


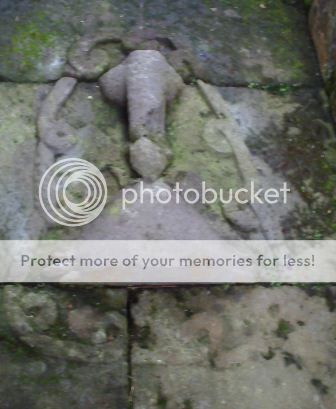



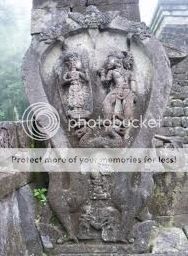
Quote:
Cerita Dulunya Candi Sukuh :
Candi Sukuh berada tepatnya di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Di antara pepohonan, sosok candi tersebut terlihat begitu gagah, sekaligus lembut dan menenangkan. Berbeda bentuk dengan candi-candi lainnya di sekitar Yogyakarta maupun Jawa Tengah, Candi Sukuh mirip sekali dengan bentuk kuil peninggalan Suka Maya berupa piramida (punden berundak). Meski tak ada dari kami yang pernah ke piramida-piramida di Peru, Chili, atau pun Meksiko, tapi kami berani jamin bahwa Candi Sukuh tak kalah indahnya dengan candi-candi yang ada, bahkan dengan piramida di belahan dunia lain.
Selain bentuknya yang mengesankan, Candi Sukuh juga dihiasi dengan berbagai arca dan relief yang dipahat langsung pada dinding-dinding candi. Pahatannya memang tidak sehalus pada Candi Prambanan atau Borobudur, tetapi lebih dalam (relief lebih menonjol) dan sosok-sosok pada relief candi mirip dengan sosok pada candi-candi di Jawa Timur, seperti Candi Jago. Berdiri di gapura pertama, adalah titik terbaik dan tepat untuk menyaksikan keindahan Kota Solo dan kawasan pemukiman dan perkebunan yang hijau dari ketinggian 910 m di atas permukaan laut. Rasanya seperti sedang berada di atas awan melihat hamparan kota dan bukit di bawah sana. Melewati gapura kedua yang lebih tinggi, hingga gapura dan teras ketiga di mana candi induk berupa piramid berada, kami begitu takjub melihat simbol-simbol binatang, burung garuda, dan kelamin perempuan maupun laki-laki.
Candi Sukuh diprediksi sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-14 sampai 15 atau menurut kalender Jawa bertahun 1359 Saka atau 1437 Masehi (“Gapuro Bhuto Anguntal Jalmo” yang setiap kata masing-masing mewakili huruf 9-5-3-1). Sebagai candi yang berorientasi pada Siwa Buddha Tantrayana, lambang kelamin memiliki makna yang sakral atau kekuatan keseimbangan Tantrayana (penyatuan lingga/kelamin laki-laki dan yoni/kelamin perempuan). Salah satu ajaran Tantrayana adalah mengenai penjelasan tentang Bhuana Alit (mikrokosmos) dan Bhuana Agung (makrokosmos) atau dalam Hindu berupa Purusa-Pradana yang dilambangkan dengan perkimpoian Bhatara Siwa (sacred masculine/penis) dan Betari Durga (sacred feminine/vagina dan rahim). Keduanya tak bisa dipisahkan layaknya mikrokosmos sebagai bagian kecil dari makrokosmos (semesta atau “Tuhan”). Tantrayana mengajarkan bahwa tubuh manusia (mikrokosmos) merupakan miniatur alam semesta (makrokosmos). Denah candi pun mewakili kesatuan lingga-yoni. Candi induk berupa piramid yang menonjol di bagian atas adalah representasi falus, sementara pembagian ruang dengan tiga teras dan gapura dengan lorong yang menyempit begitu mirip vagina, rahim, dan saluran kelamin perempuan. Maka, candi dikaitkan sebagai jembatan antara mikrokosmos (tubuh manusia) dan makrokosmos (semesta/Tuhan).
Keterkaitan simbol lingga-yoni dan pencapaian manusia (moksa) sangat erat ditampilkan pada candi ini. Tiga teras dan gapura juga memiliki arti sebagai Dunia Bawah (Nisat Mandala/Njaba) ditandai dengan relief Bima Suci; Dunia Tengah (Madya Mandala/Njaba Tengah) dengan relief Ramayana, Garudeya, dan Sudhamala; dan Dunia Atas (Utama Mandala/Njeroan) melalui relief Swargarohanaparwa (Nirwana). Tiga dunia juga merupakan tahapan kehidupan manusia: lahir, hidup, dan mati/moksa/penyatuan yang sangat erat hubungannya terhadap seks maupun seksualitas tanpa prasangka terhadap identitas maupun preferensi seksual atau stigma tabu terhadap seks/kelamin.
Dari bentuk dan ornamennya (denah, relief, dan arca) menegaskan bagaimana struktur tubuh manusia (alat kelamin) memiliki makna yang dalam dan sakral sebagai bagian mikro dari semesta atau proses menuju Sang Maha Esa. Candi Sukuh adalah simbol penyempurnaan manusia menuju tahapan selanjutnya atau tertinggi. Orang Jawa menyebutnya dengan ruwat atau (upacara) ruwatan di mana manusia ditasbihkan untuk “naik” atau penyembuhan/pembebasan dari segala dosa. Sampai saat ini, masyarakat yang beragama Hindu maupun orang-orang Jawa yang masih mempercayai dan melakukan tradisi kuno, masih berdoa di candi sebagai sarana komunikasi kepada Tuhan untuk pengampunan atau pembersihan diri.
Kisah dan Penokohan
Tak hanya memiliki sosok relief dinding yang mirip dengan candi di Jawa Timur, Candi Sukuh ternyata juga memiliki kisah yang serupa, salah satunya adalah kisah tentang Dewi Kadru yang beranak Naga dan Dewi Winata yang beranak Garuda terkait pencarian air kehidupan (Tirta Amerta). Mitologi tersebut mungkin terasa tak masuk akal, namun memiliki makna simbol dan metafor yang dekat dengan sains tentang proses penciptaan bumi. Bentuk piramid yang menyerupai Gunung Mandara, adalah pasak dengan lilitan ekor Naga Basuki yang menjadi goncangan sirkular untuk memulai pengadukan “lautan susu” mencari air kehidupan di mana tiga kura-kura berperan sebagai penyangga gunung. Selain memberikan pemahaman proses penciptaan semesta, pada relief lain yang menunjukkan balai/rumah di mana terdapat seorang ibu tengah berjongkok dan adanya orang tarik-menarik, menurut tafsiran Suro Gedeng, penulis buku kecil tentang Candi Sukuh yang bisa didapatkan pada loket atau pos informasi candi, merupakan penggambaran seorang manusia yang tinggal pada rahim dan pemeliharaan ibu, hingga kelak sang embrio menjadi manusia yang tarik-menarik dengan karma baik (Subakarma) dan karma buruk (Asubakarma).
Ada pula relief “Sangkan Paraning Dumadi” yang mensejajarkan Dewa Siwa dan Bima yang manusia berdiri dalam lingkup tapal kuda dengan ornamen naga berkepala dua dan Kala, dapat dimaknai sebagai pencapaian manusia yang berasal dari Sang Tunggal terhadap suatu kesadaran (wujud fisik sebagai wadah belaka). Penyatuan tersebut merupakan pelepasan ego manusia (keduniawian/fisik).
Tafsiran pada relief dan patung di Candi Sukuh juga menjadi tafsir kitab Jawa Kuno Sudamala. Kisahnya bisa sangat mirip dengan tafsir agama monoteisme (Samawi) tentang bagaimana manusia turun ke bumi. Dikisahkan bahwa Dewi Uma (Parwati) yang berkhianat dari “suami”-nya Sang Batara Guru (Dewa Siwa), diusir dan dikutuk menjadi Durga. Untuk bisa kembali ke Swargaloka, Durga memerlukan Pandawa (bernama Sadewa) yang bersedia meruwatnya. Namun Sadewa yang menolaknya, diikatnya pada pohon randu, hingga terjadi perkelahian dan penyerahan (ruwat/kembalinya kemuliaan Durga sebagai Dewi). Kisah tak berhenti sampai situ, namun berlanjut hingga Sadewa meminang kekasih dan pertempuran Bima membinasakan Kalantaka dan Kalanjaya.
Yang menarik dari relief Candi Sukuh, yaitu kemunculan tokoh Semar pada banyak adegan penting. Kyai Lurah Semar Inanabhadra adalah sosok yang sakral pada kitab Jawa dan pewayangan, serta menjadi teman atau bapak (pendamping sakti) bagi para Pandawa. Kata “Semar” sendiri dalam bahasa Jawa, dapat diartikan “samar” atau berasal dari kata “sar” (imbuhan “-am”) yang bermakna cahaya atau menjadi kata kerja “nyamar.” Ia muncul dengan mimik yang ekspresif (manusiawi) dengan perangai lucu, jenaka, kadang canda-tawa, tapi kadang bisa menangis. Meski begitu, Semar memunculkan banyak kebijaksanaan dalam tingkah lakunya. Ia pun dianggap sebagai jelmaan dari dewa (Sang Hyang Ismoyo) yang me-“manusia”-kan dirinya.
Keruntuhan Majapahit memunculkan peradaban agama baru di Jawa. Candi Sukuh saat ini mungkin hanya dilihat sebagai atraksi pariwisata bagi penduduk desa ketimbang tempat sakral. Namun cerita para orang-orang tua yang menitipkan pesan kepada generasi selanjutnya, memunculkan banyak interpretasi tentang hal-hal gaib, sehingga candi masih dihormati, dirawat, dan tak ada yang berani mencuri potongan relief maupun patung meski candi hanya dipagari seadanya.
Keberadaan candi pada lereng gunung yang dikelilingi hutan pinus ini sebetulnya telah diketahui sejak dulu. Tahun 1815, Johnson sudah melaporkannya kepada Pemerintah Britania Raya, dilanjutkan oleh arkeolog Belanda Van der Vlis yang kemudian memugar candi pertama kali tahun 1928. Tahun 1995, Candi Sukuh didaftarkan ke UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia. Walaupun belum juga mendapat pengakuan dunia, kemegahan dan sakralitas Candi Sukuh tetap menarik bagi para spiritualis, arkeolog, serta para traveler dari seluruh dunia yang mencari petualangan jiwa di lokasi yang bagai Nirwana di dataran tinggi Kabupaten Karanganyar.
Ada yang berani ga yah aganwati :
Pada teras ketiga ini terdapat pelataran besar dengan candi induk dan beberapa relief di sebelah kiri serta patung-patung di sebelah kanan. Jika para pengunjung ingin mendatangi candi induk yang suci ini, maka batuan berundak yang relatif lebih tinggi daripada batu berundak sebelumnya harus dilalui. Selain itu lorongnya juga sempit. Konon arsitektur ini sengaja dibuat demikian. Sebab candi induk yang mirip dengan bentuk vagina ini, menurut beberapa pakar memang dibuat untuk mengetes keperawanan para gadis. Menurut cerita, Jika seorang gadis yang masih perawan mendakinya, maka selaput daranya akan robek dan berdarah. Namun apabila ia tidak perawan lagi, maka ketika melangkahi batu undak ini, kain yang dipakainya akan robek dan terlepas.
Cerita Dulunya Candi Cetho :
Candi Cetho (ejaan bahasa Jawa: cethå) merupakan sebuah candi bercorak agama Hindu peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit (abad ke-15). Laporan ilmiah pertama mengenainya dibuat oleh Van de Vlies pada 1842. A.J. Bernet Kempers juga melakukan penelitian mengenainya. Ekskavasi (penggalian) untuk kepentingan rekonstruksi dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Berdasarkan keadaannya ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini memiliki usia yang tidak jauh dengan Candi Sukuh. Lokasi candi berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, pada ketinggian 1400m di atas permukaan laut.
Sampai saat ini, komplek candi digunakan oleh penduduk setempat yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan dan populer sebagai tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa/Kejawen.
Susunan bangunan
Ketika ditemukan keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada empat belas dataran bertingkat, memanjang dari barat (paling rendah) ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras, dan pemugaran dilakukan pada sembilan teras saja. Strukturnya yang berteras-teras membuat munculnya dugaan akan kebangkitan kembali kultur asli ("punden berundak") pada masa itu, yang disintesis dengan agama Hindu. Dugaan ini diperkuat dengan bentuk tubuh pada relief seperti wayang kulit, yang mirip dengan penggambaran di Candi Sukuh.
Pemugaran yang dilakukan oleh Humardani, asisten pribadi Suharto, pada akhir 1970-an mengubah banyak struktur asli candi, meskipun konsep punden berundak tetap dipertahankan. Pemugaran ini banyak dikritik oleh pakar arkeologi, mengingat bahwa pemugaran situs purbakala tidak dapat dilakukan tanpa studi yang mendalam. Bangunan baru hasil pemugaran adalah gapura megah di muka, bangunan-bangunan dari kayu tempat pertapaan, patung-patung Sabdapalon, Nayagenggong, Brawijaya V, serta phallus, dan bangunan kubus pada bagian puncak punden.
Selanjutnya, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, dengan alasan untuk menyemarakkan gairah keberagamaan di sekitar candi, menempatkan arca Dewi Saraswati, sumbangan dari Kabupaten Gianyar, pada bagian timur kompleks candi.
Pada keadaannya yang sekarang, Candi Cetho terdiri dari sembilan tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati dua pasang arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman dan di sini terdapat petilasan Ki Ageng Krincingwesi, leluhur masyarakat Dusun Cetho.
Pada aras ketiga terdapat sebuah tataan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa, surya Majapahit (diduga sebagai lambang Majapahit), dan simbol phallus (penis, alat kelamin laki-laki) sepanjang 2 meter dilengkapi dengan hiasan tindik (piercing) bertipe ampallang. Kura-kura adalah lambang penciptaan alam semesta sedangkan penis merupakan simbol penciptaan manusia. Terdapat penggambaran hewan-hewan lain, seperti mimi, katak, dan ketam. Simbol-simbol hewan yang ada, dapat dibaca sebagai suryasengkala berangka tahun 1373 Saka, atau 1451 era modern.
Pada aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudhamala, seperti yang terdapat pula di Candi Sukuh. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruwatan. Dua aras berikutnya memuat bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat ini pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan upacara-upacara keagamaan. Pada aras ketujuh dapat ditemui dua arca di sisi utara dan selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabdapalon dan di selatan Nayagenggong, dua tokoh setengah mitos (banyak yang menganggap sebetulnya keduanya adalah satu orang) yang diyakini sebagai abdi dan penasehat spiritual Sang Prabu Brawijaya V.
Pada aras kedelapan terdapat arca phallus (disebut "kuntobimo") di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud mahadewa. Pemujaan terhadap arca phallus melambangkan ungkapan syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Aras terakhir (kesembilan) adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus.
Di sebelah atas bangunan Candi Cetho terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat membersihkan diri sebelum melaksanakan upacara ritual peribadahan (patirtan). Di dekat bangunan candi, dengan menuruni lereng yang terjal, ditemukan lagi sebuah kompleks bangunan candi yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Candi Kethek ("Candi Kera").
Quote:
Candi Sukuh berada tepatnya di Dusun Sukuh, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso. Di antara pepohonan, sosok candi tersebut terlihat begitu gagah, sekaligus lembut dan menenangkan. Berbeda bentuk dengan candi-candi lainnya di sekitar Yogyakarta maupun Jawa Tengah, Candi Sukuh mirip sekali dengan bentuk kuil peninggalan Suka Maya berupa piramida (punden berundak). Meski tak ada dari kami yang pernah ke piramida-piramida di Peru, Chili, atau pun Meksiko, tapi kami berani jamin bahwa Candi Sukuh tak kalah indahnya dengan candi-candi yang ada, bahkan dengan piramida di belahan dunia lain.
Selain bentuknya yang mengesankan, Candi Sukuh juga dihiasi dengan berbagai arca dan relief yang dipahat langsung pada dinding-dinding candi. Pahatannya memang tidak sehalus pada Candi Prambanan atau Borobudur, tetapi lebih dalam (relief lebih menonjol) dan sosok-sosok pada relief candi mirip dengan sosok pada candi-candi di Jawa Timur, seperti Candi Jago. Berdiri di gapura pertama, adalah titik terbaik dan tepat untuk menyaksikan keindahan Kota Solo dan kawasan pemukiman dan perkebunan yang hijau dari ketinggian 910 m di atas permukaan laut. Rasanya seperti sedang berada di atas awan melihat hamparan kota dan bukit di bawah sana. Melewati gapura kedua yang lebih tinggi, hingga gapura dan teras ketiga di mana candi induk berupa piramid berada, kami begitu takjub melihat simbol-simbol binatang, burung garuda, dan kelamin perempuan maupun laki-laki.
Candi Sukuh diprediksi sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit pada pertengahan abad ke-14 sampai 15 atau menurut kalender Jawa bertahun 1359 Saka atau 1437 Masehi (“Gapuro Bhuto Anguntal Jalmo” yang setiap kata masing-masing mewakili huruf 9-5-3-1). Sebagai candi yang berorientasi pada Siwa Buddha Tantrayana, lambang kelamin memiliki makna yang sakral atau kekuatan keseimbangan Tantrayana (penyatuan lingga/kelamin laki-laki dan yoni/kelamin perempuan). Salah satu ajaran Tantrayana adalah mengenai penjelasan tentang Bhuana Alit (mikrokosmos) dan Bhuana Agung (makrokosmos) atau dalam Hindu berupa Purusa-Pradana yang dilambangkan dengan perkimpoian Bhatara Siwa (sacred masculine/penis) dan Betari Durga (sacred feminine/vagina dan rahim). Keduanya tak bisa dipisahkan layaknya mikrokosmos sebagai bagian kecil dari makrokosmos (semesta atau “Tuhan”). Tantrayana mengajarkan bahwa tubuh manusia (mikrokosmos) merupakan miniatur alam semesta (makrokosmos). Denah candi pun mewakili kesatuan lingga-yoni. Candi induk berupa piramid yang menonjol di bagian atas adalah representasi falus, sementara pembagian ruang dengan tiga teras dan gapura dengan lorong yang menyempit begitu mirip vagina, rahim, dan saluran kelamin perempuan. Maka, candi dikaitkan sebagai jembatan antara mikrokosmos (tubuh manusia) dan makrokosmos (semesta/Tuhan).
Keterkaitan simbol lingga-yoni dan pencapaian manusia (moksa) sangat erat ditampilkan pada candi ini. Tiga teras dan gapura juga memiliki arti sebagai Dunia Bawah (Nisat Mandala/Njaba) ditandai dengan relief Bima Suci; Dunia Tengah (Madya Mandala/Njaba Tengah) dengan relief Ramayana, Garudeya, dan Sudhamala; dan Dunia Atas (Utama Mandala/Njeroan) melalui relief Swargarohanaparwa (Nirwana). Tiga dunia juga merupakan tahapan kehidupan manusia: lahir, hidup, dan mati/moksa/penyatuan yang sangat erat hubungannya terhadap seks maupun seksualitas tanpa prasangka terhadap identitas maupun preferensi seksual atau stigma tabu terhadap seks/kelamin.
Dari bentuk dan ornamennya (denah, relief, dan arca) menegaskan bagaimana struktur tubuh manusia (alat kelamin) memiliki makna yang dalam dan sakral sebagai bagian mikro dari semesta atau proses menuju Sang Maha Esa. Candi Sukuh adalah simbol penyempurnaan manusia menuju tahapan selanjutnya atau tertinggi. Orang Jawa menyebutnya dengan ruwat atau (upacara) ruwatan di mana manusia ditasbihkan untuk “naik” atau penyembuhan/pembebasan dari segala dosa. Sampai saat ini, masyarakat yang beragama Hindu maupun orang-orang Jawa yang masih mempercayai dan melakukan tradisi kuno, masih berdoa di candi sebagai sarana komunikasi kepada Tuhan untuk pengampunan atau pembersihan diri.
Kisah dan Penokohan
Tak hanya memiliki sosok relief dinding yang mirip dengan candi di Jawa Timur, Candi Sukuh ternyata juga memiliki kisah yang serupa, salah satunya adalah kisah tentang Dewi Kadru yang beranak Naga dan Dewi Winata yang beranak Garuda terkait pencarian air kehidupan (Tirta Amerta). Mitologi tersebut mungkin terasa tak masuk akal, namun memiliki makna simbol dan metafor yang dekat dengan sains tentang proses penciptaan bumi. Bentuk piramid yang menyerupai Gunung Mandara, adalah pasak dengan lilitan ekor Naga Basuki yang menjadi goncangan sirkular untuk memulai pengadukan “lautan susu” mencari air kehidupan di mana tiga kura-kura berperan sebagai penyangga gunung. Selain memberikan pemahaman proses penciptaan semesta, pada relief lain yang menunjukkan balai/rumah di mana terdapat seorang ibu tengah berjongkok dan adanya orang tarik-menarik, menurut tafsiran Suro Gedeng, penulis buku kecil tentang Candi Sukuh yang bisa didapatkan pada loket atau pos informasi candi, merupakan penggambaran seorang manusia yang tinggal pada rahim dan pemeliharaan ibu, hingga kelak sang embrio menjadi manusia yang tarik-menarik dengan karma baik (Subakarma) dan karma buruk (Asubakarma).
Ada pula relief “Sangkan Paraning Dumadi” yang mensejajarkan Dewa Siwa dan Bima yang manusia berdiri dalam lingkup tapal kuda dengan ornamen naga berkepala dua dan Kala, dapat dimaknai sebagai pencapaian manusia yang berasal dari Sang Tunggal terhadap suatu kesadaran (wujud fisik sebagai wadah belaka). Penyatuan tersebut merupakan pelepasan ego manusia (keduniawian/fisik).
Tafsiran pada relief dan patung di Candi Sukuh juga menjadi tafsir kitab Jawa Kuno Sudamala. Kisahnya bisa sangat mirip dengan tafsir agama monoteisme (Samawi) tentang bagaimana manusia turun ke bumi. Dikisahkan bahwa Dewi Uma (Parwati) yang berkhianat dari “suami”-nya Sang Batara Guru (Dewa Siwa), diusir dan dikutuk menjadi Durga. Untuk bisa kembali ke Swargaloka, Durga memerlukan Pandawa (bernama Sadewa) yang bersedia meruwatnya. Namun Sadewa yang menolaknya, diikatnya pada pohon randu, hingga terjadi perkelahian dan penyerahan (ruwat/kembalinya kemuliaan Durga sebagai Dewi). Kisah tak berhenti sampai situ, namun berlanjut hingga Sadewa meminang kekasih dan pertempuran Bima membinasakan Kalantaka dan Kalanjaya.
Yang menarik dari relief Candi Sukuh, yaitu kemunculan tokoh Semar pada banyak adegan penting. Kyai Lurah Semar Inanabhadra adalah sosok yang sakral pada kitab Jawa dan pewayangan, serta menjadi teman atau bapak (pendamping sakti) bagi para Pandawa. Kata “Semar” sendiri dalam bahasa Jawa, dapat diartikan “samar” atau berasal dari kata “sar” (imbuhan “-am”) yang bermakna cahaya atau menjadi kata kerja “nyamar.” Ia muncul dengan mimik yang ekspresif (manusiawi) dengan perangai lucu, jenaka, kadang canda-tawa, tapi kadang bisa menangis. Meski begitu, Semar memunculkan banyak kebijaksanaan dalam tingkah lakunya. Ia pun dianggap sebagai jelmaan dari dewa (Sang Hyang Ismoyo) yang me-“manusia”-kan dirinya.
Keruntuhan Majapahit memunculkan peradaban agama baru di Jawa. Candi Sukuh saat ini mungkin hanya dilihat sebagai atraksi pariwisata bagi penduduk desa ketimbang tempat sakral. Namun cerita para orang-orang tua yang menitipkan pesan kepada generasi selanjutnya, memunculkan banyak interpretasi tentang hal-hal gaib, sehingga candi masih dihormati, dirawat, dan tak ada yang berani mencuri potongan relief maupun patung meski candi hanya dipagari seadanya.
Keberadaan candi pada lereng gunung yang dikelilingi hutan pinus ini sebetulnya telah diketahui sejak dulu. Tahun 1815, Johnson sudah melaporkannya kepada Pemerintah Britania Raya, dilanjutkan oleh arkeolog Belanda Van der Vlis yang kemudian memugar candi pertama kali tahun 1928. Tahun 1995, Candi Sukuh didaftarkan ke UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia. Walaupun belum juga mendapat pengakuan dunia, kemegahan dan sakralitas Candi Sukuh tetap menarik bagi para spiritualis, arkeolog, serta para traveler dari seluruh dunia yang mencari petualangan jiwa di lokasi yang bagai Nirwana di dataran tinggi Kabupaten Karanganyar.
Ada yang berani ga yah aganwati :
Pada teras ketiga ini terdapat pelataran besar dengan candi induk dan beberapa relief di sebelah kiri serta patung-patung di sebelah kanan. Jika para pengunjung ingin mendatangi candi induk yang suci ini, maka batuan berundak yang relatif lebih tinggi daripada batu berundak sebelumnya harus dilalui. Selain itu lorongnya juga sempit. Konon arsitektur ini sengaja dibuat demikian. Sebab candi induk yang mirip dengan bentuk vagina ini, menurut beberapa pakar memang dibuat untuk mengetes keperawanan para gadis. Menurut cerita, Jika seorang gadis yang masih perawan mendakinya, maka selaput daranya akan robek dan berdarah. Namun apabila ia tidak perawan lagi, maka ketika melangkahi batu undak ini, kain yang dipakainya akan robek dan terlepas.
Cerita Dulunya Candi Cetho :
Quote:
Candi Cetho (ejaan bahasa Jawa: cethå) merupakan sebuah candi bercorak agama Hindu peninggalan masa akhir pemerintahan Majapahit (abad ke-15). Laporan ilmiah pertama mengenainya dibuat oleh Van de Vlies pada 1842. A.J. Bernet Kempers juga melakukan penelitian mengenainya. Ekskavasi (penggalian) untuk kepentingan rekonstruksi dilakukan pertama kali pada tahun 1928 oleh Dinas Purbakala Hindia Belanda. Berdasarkan keadaannya ketika reruntuhannya mulai diteliti, candi ini memiliki usia yang tidak jauh dengan Candi Sukuh. Lokasi candi berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, pada ketinggian 1400m di atas permukaan laut.
Sampai saat ini, komplek candi digunakan oleh penduduk setempat yang beragama Hindu sebagai tempat pemujaan dan populer sebagai tempat pertapaan bagi kalangan penganut kepercayaan asli Jawa/Kejawen.
Susunan bangunan
Ketika ditemukan keadaan candi ini merupakan reruntuhan batu pada empat belas dataran bertingkat, memanjang dari barat (paling rendah) ke timur, meskipun pada saat ini tinggal 13 teras, dan pemugaran dilakukan pada sembilan teras saja. Strukturnya yang berteras-teras membuat munculnya dugaan akan kebangkitan kembali kultur asli ("punden berundak") pada masa itu, yang disintesis dengan agama Hindu. Dugaan ini diperkuat dengan bentuk tubuh pada relief seperti wayang kulit, yang mirip dengan penggambaran di Candi Sukuh.
Pemugaran yang dilakukan oleh Humardani, asisten pribadi Suharto, pada akhir 1970-an mengubah banyak struktur asli candi, meskipun konsep punden berundak tetap dipertahankan. Pemugaran ini banyak dikritik oleh pakar arkeologi, mengingat bahwa pemugaran situs purbakala tidak dapat dilakukan tanpa studi yang mendalam. Bangunan baru hasil pemugaran adalah gapura megah di muka, bangunan-bangunan dari kayu tempat pertapaan, patung-patung Sabdapalon, Nayagenggong, Brawijaya V, serta phallus, dan bangunan kubus pada bagian puncak punden.
Selanjutnya, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, dengan alasan untuk menyemarakkan gairah keberagamaan di sekitar candi, menempatkan arca Dewi Saraswati, sumbangan dari Kabupaten Gianyar, pada bagian timur kompleks candi.
Pada keadaannya yang sekarang, Candi Cetho terdiri dari sembilan tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati dua pasang arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman dan di sini terdapat petilasan Ki Ageng Krincingwesi, leluhur masyarakat Dusun Cetho.
Pada aras ketiga terdapat sebuah tataan batu mendatar di permukaan tanah yang menggambarkan kura-kura raksasa, surya Majapahit (diduga sebagai lambang Majapahit), dan simbol phallus (penis, alat kelamin laki-laki) sepanjang 2 meter dilengkapi dengan hiasan tindik (piercing) bertipe ampallang. Kura-kura adalah lambang penciptaan alam semesta sedangkan penis merupakan simbol penciptaan manusia. Terdapat penggambaran hewan-hewan lain, seperti mimi, katak, dan ketam. Simbol-simbol hewan yang ada, dapat dibaca sebagai suryasengkala berangka tahun 1373 Saka, atau 1451 era modern.
Pada aras selanjutnya dapat ditemui jajaran batu pada dua dataran bersebelahan yang memuat relief cuplikan kisah Sudhamala, seperti yang terdapat pula di Candi Sukuh. Kisah ini masih populer di kalangan masyarakat Jawa sebagai dasar upacara ruwatan. Dua aras berikutnya memuat bangunan-bangunan pendapa yang mengapit jalan masuk candi. Sampai saat ini pendapa-pendapa tersebut digunakan sebagai tempat pelangsungan upacara-upacara keagamaan. Pada aras ketujuh dapat ditemui dua arca di sisi utara dan selatan. Di sisi utara merupakan arca Sabdapalon dan di selatan Nayagenggong, dua tokoh setengah mitos (banyak yang menganggap sebetulnya keduanya adalah satu orang) yang diyakini sebagai abdi dan penasehat spiritual Sang Prabu Brawijaya V.
Pada aras kedelapan terdapat arca phallus (disebut "kuntobimo") di sisi utara dan arca Sang Prabu Brawijaya V dalam wujud mahadewa. Pemujaan terhadap arca phallus melambangkan ungkapan syukur dan pengharapan atas kesuburan yang melimpah atas bumi setempat. Aras terakhir (kesembilan) adalah aras tertinggi sebagai tempat pemanjatan doa. Di sini terdapat bangunan batu berbentuk kubus.
Di sebelah atas bangunan Candi Cetho terdapat sebuah bangunan yang pada masa lalu digunakan sebagai tempat membersihkan diri sebelum melaksanakan upacara ritual peribadahan (patirtan). Di dekat bangunan candi, dengan menuruni lereng yang terjal, ditemukan lagi sebuah kompleks bangunan candi yang oleh masyarakat sekitar disebut sebagai Candi Kethek ("Candi Kera").
Spoiler for Ember kobokannye gan:
[URL="http://travel.detik..com/read/2013/11/07/124305/2406190/1520/2/taman-penis-perawan-yang-tenggelam-di-korea']Ember kobokan[/URL]
Ember kobokan
Ember kobokan
Ember kobokan

Diubah oleh aseli.kompeni 29-12-2013 17:55
nona212 memberi reputasi
1
21.5K
Kutip
59
Balasan
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan