- Beranda
- Komunitas
- Story
- Stories from the Heart
[TAMAT] The End of Horizon
TS
ladeedah
[TAMAT] The End of Horizon
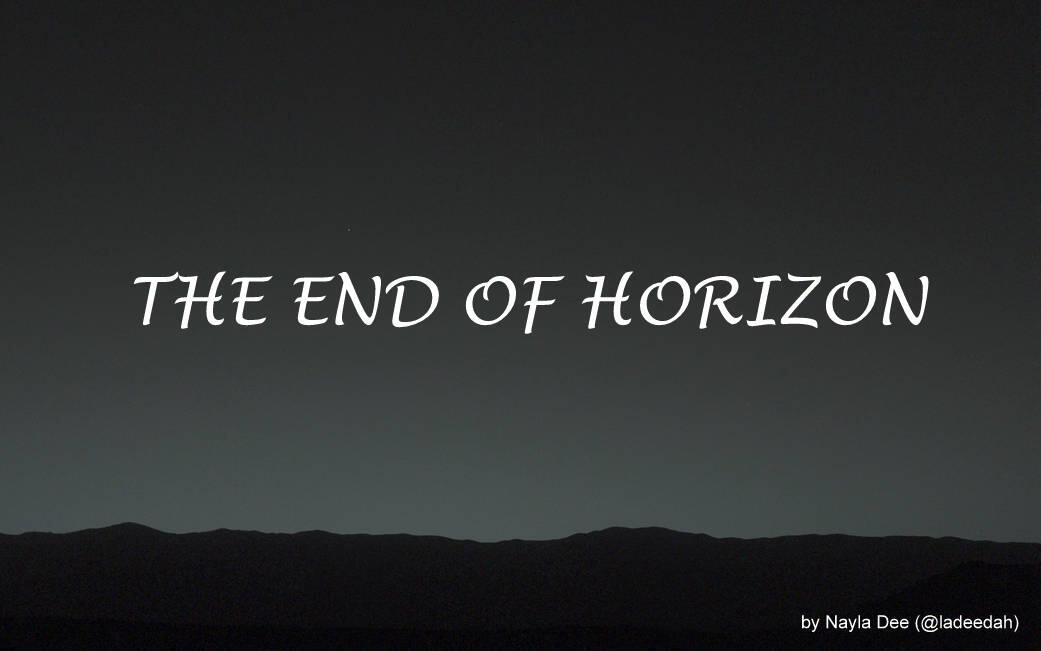
courtesy of picture: nasa.gov
I’ve learned that waiting is the most difficult bit, and I want to get used to the feeling,
knowing that you’re with me, even when you’re not by my side
--Paulo Coelho in Eleven Minutes--
knowing that you’re with me, even when you’re not by my side
--Paulo Coelho in Eleven Minutes--
A Love Story
by
Nayla Dee
by
Nayla Dee
Diubah oleh ladeedah 09-11-2017 12:03
ugalugalih dan 9 lainnya memberi reputasi
10
183K
870
Thread Digembok
Tampilkan semua post
TS
ladeedah
#216
RUMAH

I Am Sorry -- composed by Per Olov Kindgren
"Ajeng, tunggu!!" Brian mengejar kami ke depan pintu saat gue sudah membuka pintu mobil Davi. Gue melihatnya yang masih membawa sebungkus makanan yang gue yakin itu untuk gue. Lampu teras depan yang tak cukup terang membentuk bayangan rambut Brian di wajahnya, menutupi mata tajamnya, yang hanya mampu gue tangkap sorot sedih dan paniknya. Benarkah?
"Jeng plis, kalo ini gara-gara gue, plis kasih gue kesempatan buat jelasin semuanya!" Brian mendekati gue yang sudah berdiri di balik pintu mobil. Gue hanya menatap Brian, marah, sedih, dan merasa bodoh berbaur jadi satu dalam diri gue.
Gue tak ingin bicara apa-apa lagi. Gue naik ke mobil Davi dan Brian menahan pintu yang hendak gue tutup.
"Ajeng, tolong bilang sesuatu Jeng, jangan diem aja!" mohon Brian. Tenaganya cukup kuat untuk menahan pintu tetap terbuka.
"Woy!! Minggir!" teriak Davi yang sudah duduk di kursi kemudi dan menyalakan mesin mobil. Brian hanya melihat Davi kesal dan tak mengatakan apapun. Brian menatap gue lagi.
“Lo pengen gue bilang sesuatu ke lo, Bri?” tanya gue pelan. Brian mengangguk.
“Jangan temuin gue lagi!”
Bersamaan dengan itu pegangan tangan Brian melemah dan gue segera menutup pintu.
Ada beberapa hal yang keindahannya membuat gue merasa terluka. Ingin tetap melihatnya meskipun ada sebagian diri yang meluruh dalam rasa sakit dan sedih yang sepi:
Berenang saat hujan deras.
Melihat jalanan yang sepi saat hujan.
Berjalan di alam bebas.
Membaca buku sendirian di dalam perpustakaan umum yang luas.
Melihat bintang di langit yang terpaut ribuan tahun cahaya.
Melihat lampu-lampu kota dari kejauhan.
Bar setelah jam dua malam.
Melihat bulan yang berganti fasa dari malam ke malam.
Melihat ke langit gelap dan menyadari betapa sedikitnya yang gue pahami tentang alam semesta.
Dan Brian.
Bayangan Brian di spion semakin mengecil seiring Davi menjauhi rumah kos dan berbelok di ujung gang.
Love is strange. Always new and comes like stranger.
Gue bisa bertahan dengan keadaan paling menyakitkan sebelum ini. Menghadapi semuanya dengan senyum dan cuek meskipun hati ingin berteriak kesakitan dan mencukupkan semua penderitaan. Gue bisa menjadi kuat dengan tempaan cobaan dan menyimpannya rapi di dalam dada, tanpa menunjukkannya ke air muka. Kehilangan, kekecewaan, pengkhianatan, dusta, dan kemarahan, bisa terlewati dengan menyembunyikan duka itu dalam-dalam dan tak ingin memunculkannya bahkan di lapisan sebelum ekspresi wajah karena gue tidak ingin orang lain melihat gue lemah.
Gue adalah seorang Promotor Demo Mahasiswa. Gue biasa berdiri di garda paling depan dan mengangkat kepalan tangan ke atas untuk menumbangkan keangkuhan penguasa negara. Menjadi sosok yang bersuara paling keras membuat gue mudah dikenali dan gue sudah biasa menerima omongan yang paling hina dan menjijikkan. Ditampar dan dihujat. Dikutuk sebelum mengutuk. Dicaci sebelum mencaci.
Gue tetap kuat. Gue memang kuat.
Lalu sebuah pertemuan dengan orang asing oleh sebuah buku tanpa suara membuat gue—collapsed—seluruh tubuh, hati dan pikiran gue, collapsed.
Dentuman techno music dalam mobil Davi perlahan merasuk ke dalam lamunan gue. Bergabung dengan sisa-sisa ingatan akan Brian.
“Jeng!” suara Davi mempurnakan lamunan gue. Gue mengerjapkan mata dan menoleh ke arah Davi yang melihat gue heran.
“Ya?”
“Yah! Ngelamun lo Jeng? Lo ga denger apa yang gue omongin barusan?”
Gue hanya nyengir menanggapi muka Davi yang kesal. Kami sudah melewati Cimahi dan mulai masuk daerah Padalarang. Lumayan lama juga gue ngelamun. Davi menurunkan kaca mobilnya dan menyalakan sebatang rokok. Lalu melihat sesekali ke gue.
“Tadi itu, si Brian, kok dia kekeh banget pengen ngomong sama lo, Jeng?”
“Ga tau, ngerasa bersalah kali udah mencemarkan nama baik gue” gue mengambil rokok gue sendiri di dalam tas.
“Halah! Taik lo! Kayak nama lo bagus aja!” ejek Davi menanggapi ke-songong-an gue. Gue hanya tertawa dan membantu Davi memenuhi mobilnya dengan asap rokok.
“Dia suka sama lo Jeng?” Davi masih penasaran.
“Kagak Dav, kan semua orang udah tau kalo gue calon bini lo!”
“Sumpah ya gue sumpel pake bibir tuh mulut!”
“Bibir lo Dav? Nih!” gue memanyunkan mulut ke arah Davi dan dia hanya tertawa kesal.
“Lo sendiri kenapa ga cari pacar lagi Dav?”
Bicara tentang kisah cinta pentolan BEM seperti Davi seperti bicara tentang matahari yang terbit dan tenggelam setiap hari. Membosankan. Bagi orang di luar sistem kami, kisah cinta kami mungkin tampak menarik. Bisa berpacaran dengan pentolan BEM dan Kongres yang sudah pasti dikenal oleh seluruh massa kampus. Kedekatan kami dengan siapapun selalu menjadi sorotan, entah nilai baik atau nilai buruk, yang penting menjadi sorotan.
Davi beberapa kali pacaran, gonta-ganti pacar dengan alasan putus yang selalu sama: “lo kurang perhatian sama gue, Dav. Keseringan rapat dan pergi sana-sini”
Davi menjadi seseorang yang selalu ditinggalkan. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk fokus ke BEM dan kuliahnya.
Gue yang sudah sangat lama kenal Davi (kami dari SMA yang sama) paham bahwa ini membosankan. Ada saat kami ingin punya seseorang untuk berbagi hal-hal paling rahasia, namun mereka sudah pergi karena tak sabar menunggu hingga rapat selesai. Kami ingin bercanda mesra seperti pasangan pecinta lainnya, namun si dia sudah angkat kaki karena agenda rapat tak kunjung usai.
“Lo nanya? Apa nyari kisi-kisi buat daftar jadi pacar gue?”
“Serius atuh Dav! Gue kiss beneran loh lo ntar!” ancam gue manis. Davi terkekeh.
“Takut gue, takut ditinggal lagi!” jawab Davi kesal. Ada sisi lembut dari Davi yang selengekan, sisi yang sebenarnya sangat rapuh dan sensitif.
“Lah sekarang kan udah turun jabatan Dav, lo lebih santai dong, bisa manjain cewek lo, nemenin mereka spa, nyalon, dan renang”
“Jadi lo mau gue nemenin lo spa, nyalon dan renang?” goda Davi berbalik ke gue. Gue hanya melengos tak menanggapi guyonannya.
Sepanjang jalan kami membicarakan hal-hal tak penting hingga tak terasa kami sudah memasuki kawasan puncak. Davi membelokkan mobilnya di sebuah pelataran penginapan. Resepsionis menyerahkan kunci kamar pada kami, dua kamar yang letaknya berhadapan.
“Udah lo tidur aja dulu sekarang!” perintah Davi.
Gue memeriksa hape setelah seharian tidak membukanya sama sekali. Ada satu SMS dari Brian.
‘Ajeng, kalo lo ga mau ketemu gue lagi ga apa-apa, tapi seenggaknya lo harus tau kalo gue ga pernah bohong ke lo. Gue beneran udah putus sama Kalia. Kalo Kalia bilang yang lain, itu Kalia. Bukan gue. Ati-ati di jalan’
AH MASA BODO LAH!
Gue membanting badan di kasur dan tidur.
Gue bangun dengan ketukan Davi di pintu kamar gue. Sudah jam delapan pagi.
“Lo kebo banget sih Jeng! Gue gedor-gedor dari jam tujuh! Gue miskol ga aktif lagi HP lo!” Davi rebahan di kasur. Dia sudah mandi. What, Davi mandi pagi??
“Lo mandi, Dav?” gue mengamati Davi dari dekat dan mengendus badannya, ada aroma wangi sabun.
“Anjrit! Apaan sih lo Jeng! Kayak anjing tau ga!” Davi berusaha menyingkir dari endusan gue.
“Tapi lo emang bau sabun Dav!” gue masih mengendus-endus.
“So what kalo gue bau sabun? Ga boleh? Emang gue apaan dah!” elaknya kesal.
“Hahaha lo pake berapa botol sabunnya sampe bisa bau sabun gini? Daki lo aja ga akan rontok pake seliter sabun juga!”
“Taik lo Jeng! Gue kan mau ajak lo jalan-jalan, jadi pacar gue selama di Puncak ya Jeng ya!” Davi mulai genit.
“OK, ya udah yuk jalan-jalan!”
“JENG! GUE UDAH MANDI! LO ILERAN GITU MAU JALAN MA GUE?? NAJIS JENG! Mending gue cari Mbak-Mbak disonoh!”
Gue hanya nyengir dan melangkah ke kamar mandi.
Kami sarapan bubur ayam di pinggir jalan dan pergi berkeliling di Taman Safari. Hari Sabtu kawasan Puncak ramai oleh keluarga bersama anak-anak mereka.
“Sayang, kapan kita mau punya anak kayak mereka?” goda Davi.
“Bikin yuk sekarang!” ajak gue. Tiba-tiba ponsel Davi berdering.
“Yah Bokap lo Jeng!” Davi langsung mengangkat. Pasti Papa panik nyariin gue yang dari kemaren ga ada kabarnya.
‘Halo Om’
‘Baik Om, Om sama Tante apa kabar?’
‘Iya Ajeng ada kok Om, ini lagi sama saya’
“Nih herder lo nyariin!” bisik Davi sambil menyerahkan hapenya.
‘Ya Pa?’
‘Kamu kemanaa aja! Ga nelepon Papa Mama, SMS ga dibales, hape ga aktif! Mau ke Cina kamu ya?”
‘Habis batre, lagi di Puncak!’
‘Di Puncak? Ngapain?’
‘Maen sama Davi’
‘Kamu pacaran sama Davi? Jangan pacaran sama anak BEM! Makan ati terus kamu, kayak Mama dulu!’
‘Kagak, najis! Kayak ga ada laki lain aja selain Davi!’
Davi menjitak kepala gue keras.
‘Kamu nginep?’
‘Iya’
‘Berdua doang sama Davi? Di Puncak? Tidur sekamar ya kalian? Bawa kondom kan?’
‘Apaan sih Pa! Kagak ada apa-apa sama Davi! Cuma refreshing aja, besok pagi balik lagi ke Bandung’
‘Lah Mas Brian kemana Mbak Ajeng?’
‘Oh shut up! He’s bad Papa, he’s a liar!’
‘O’ow ada yang habis patah hati ga cerita ke Papa nih!’
‘Udah ah, ntar aja Ajeng ceritain, kalo mood. Lagian ngapain nyeritain orang cem dia’
‘OK, be careful, smooch from Papa mmmuuaaacc...’
Gue langsung menutup telepon sebelum Papa menyelesaikan ciuman basahnya.
Gue dan Davi melanjutkan jalan-jalan dan wisata kuliner. Kami mengelilingi taman bunga, mencoba paralayang, dan berkunjung ke toko bunga anggrek.
“Jeng, tobat yuk!" Davi membelokkan mobilnya ke arah masjid At Ta’awun. Gue hanya menuruti Davi berjalan ke arah masjid. Kami segera berwudhu karena sholat maghrib berjamaah sudah dimulai.
Kau adalah Rumah.
Rumah yang selalu menerima siapapun untuk pulang. Untuk duduk, diam, dan mengosongkan pikiran. Rumah yang tidak akan mempertanyakan apa masalah gue, apa kesulitan gue, apa kebahagiaan gue, apa pencapaian gue. Rumah yang diam. Namun pelukannya terasa hangat dan diamnya menenangkan.
Quote:
“Heh!” Davi menyikut lengan gue. Udara dingin puncak mulai menusuk kulit yang hanya mengenakan kaos lengan pendek.
“Lo ngelamunan mulu sih Jeng belakangan! Gara-gara si Brian?”
Gue hanya menggeleng. Sekarang justru gue jadi kepikiran Brian setelah Davi tanya.
Davi mengajak makan ke sebuah restoran yang tak jauh dari kawasan masjid. Setelah makan malam Davi membawa gue ke—sebuah tanah lapang di puncak—entah, mungkin kebun teh atau jurang di bawah sana. Tapi gue bisa melihat lampu kota Bogor dari atas.
“Keren ga Jeng?”
“Iya keren sumpah!” gue langsung turun dan ingin melihat dari luar.
“Jangan jauh-jauh! Lo nggelinding dari atas sini bisa mokat! Gue digorok ma bokap lo yang ada!” bentak Davi saat gue terus melangkah maju. Gue pun kembali lagi ke mobil Davi.
“Sini naik kalo mau liat lebih jelas!”
Davi naik ke atap mobilnya, menggelar sebuah selimut di atasnya dan mengulurkan tangannya untuk membantu gue naik.
Beautiful sadness.
Davi membuka sebotol whiskey. Kami meminum whiskey sambil merokok, terus mengamati lembah gemerlap di kejauhan dalam diam.
“Liat deh Jeng!” Davi menunjuk ke langit. Ada beberapa bintang di langit, tak banyak namun cukup terang nyalanya.
“Bintang. Yang ga kedip-kedip itu Venus Dav” lirih gue sambil menunjuk sebuah titik putih yang tak gemerlap seperti lainnya. Davi hanya mengangguk-angguk.
“Bumi dilihat dari sana mungkin juga setitik gitu juga ya Jeng?”
“Iya Dav”
Davi merebahkan tubuhnya, menatap ke langit. Ada risau yang pasrah di wajahnya. Wajah Davi yang hanya ia tunjukkan saat kami sudah terlalu lelah dengan politik kampus dan mempertanyakan esensi kepemimpinan kami.
“Di titik itu ada kita. Ada rumah kita. Ada Mama dan semua orang yang kita cintai, ada Papa gue yang gue benci. Orang yang pernah kita kenal, orang yang cuma kita denger namanya, semua manusia yang hidup dari jaman Adam sampe sekarang, yang udah mati dan yang masih hidup. Kebahagiaan dan penderitaan, ribuan agama, ideologi, doktrin-doktrin ekonomi, pemburu dan penjelajah, pahlawan dan pengecut, pencipta dan penghancur peradaban, raja dan budak, orang-orang yang sedang jatuh cinta, para orang tua, anak-anak, para penemu, para guru, politikus-politikus yang korupsi, bintang film, pemimpin-pemimpin tertinggi, para orang suci dan pendosa. Sejarah spesies kita ada disana, di sebuah titik sebesar debu yang cuma bisa keliatan kalo ada cahaya”
“Dan kita yang kecil ini wondering ada apa di dalam gelap. Berusaha membuat hipotesa dari cahaya” sambung gue pelan.
“Lo pernah marah Jeng?”
“Pernahlah Dav”
“Lo pernah maafin?”
Gue diam.
“Gue masih belom bisa maafin Papa sampe sekarang Jeng. Dia udah berusaha baik-baikin gue, tapi gue benci banget sama Papa” Davi bangkit dari rebahannya dan meraih botol di tangan gue lalu meneguk isinya. Ada kilatan air di matanya.
Davi tumbuh dalam keadaan yang broken home. Papanya meninggalkan Mamanya sewaktu Davi masih bayi untuk menikah lagi. Betrayal. That must be hard to accept.
“Kata Mama gue harus maafin Papa, lalu lupakan. Tapi cinta bukan sesuatu yang bisa kita kasih atau kita dapet kan Jeng. Cinta itu sesuatu yang kita tumbuhkan dan kita rawat. Gue gabisa maafin Papa karena gue ga pernah cinta sama Papa. Karena Papa udah nyakitin Mama.”
Gue masih diam. Mengikuti pandangan Davi ke lampu-lampu kota. Pengkhianatan selalu meninggalkan sakit yang rasanya melebihi rasa sakit fisik. Rasa sakit dari rasa sakit, yang keberadaannya tak disadari hingga rasa sakit itu datang. Ada yang bilang, pengkhianatan lebih buruk dari kematian. Semua orang memahami konsep kematian, secara sains dan religius. Tapi pengkhianatan?
Gue mengelus pundak Davi dan meletakkan kepala gue di bahunya.
“It’s alright Davi. It’s alright” bisik gue pelan.
Davi benar.
Cinta bukanlah sesuatu yang bisa diberi atau didapatkan. Cinta adalah sesuatu yang tumbuh, lalu harus dirawat agar berkembang dan menghasilkan hasil panen yang indah.
Allah Maha Pengampun, Ajeng. God is good. Always Good.
Then why you keep angry to yourself, Lady?
Diubah oleh ladeedah 09-11-2017 18:53
JabLai cOY memberi reputasi
1